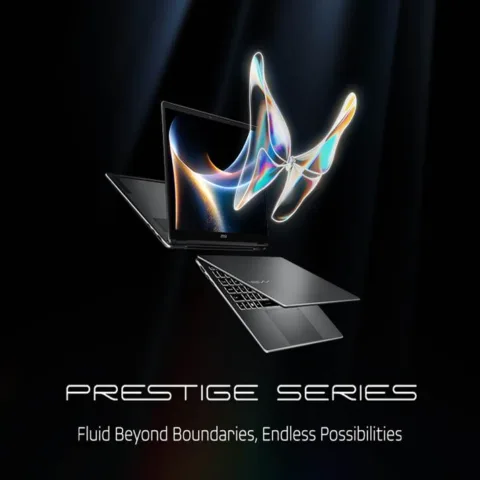Atlet esports dewasa ini telah menjadi profesi yang menjanjikan. Sama seperti atlet-atlet olahraga seperti sepak bola atau bola basket, seorang pemain profesional yang berkompetisi di level tinggi bisa memiliki penghasilan yang luar biasa besarnya, bahkan dielu-elukan sebagai seorang selebritas. Apalagi bila mereka bermain di negara-negara maju yang sudah punya ekosistem esports mapan, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, atau Korea Selatan.
Akan tetapi terkadang mungkin kita lupa keberhasilan meraih ketenaran besar dan menjadi miliarder itu tidak dimiliki oleh semua orang. Di antara sekian banyak pemain esports, hanya segelintir yang bisa menjadi top player dan bermain di level tertinggi. Sebagian lainnya yang bermain di tim kecil tentu akan mendapat penghasilan kecil juga, bahkan di beberapa kasus malah tidak mendapat bayaran.
Mirip seperti profesi industri hiburan ataupun profesi atlet olahraga lainnya, esports bisa dibilang termasuk mata pencaharian yang “high risk high reward”. Seberapa besar risikonya, dan bagaimana nasib para pemain yang tidak termasuk dalam jajaran top player tadi? Untuk memahami kenyataan di lapangan secara lebih jelas, kita dapat melihat terlebih dahulu penghasilan atlet esports di berbagai negara. Berikut ini beberapa datanya.
Amerika Serikat
Mencari data tentang penghasilan setiap atlet esports secara pasti adalah hal yang cukup sulit karena pada umumnya organisasi tidak mau membuka informasi tersebut ke publik. Namun sesekali ada beberapa tim, pemain, atau lembaga survei yang mau membeberkannya dalam acara khusus. Contohnya di bulan April 2019 kemarin, ketika Komisaris League of Legends Championship Series (LCS) Chris Greeley mengungkap gaji para atlet esports di liga Amerika Serikat tersebut.
Riot Games menerapkan aturan dalam LCS di mana setiap tim peserta harus menggaji atletnya sebesar minimal US$75.000 (Rp1,1 miliar) per tahun. Akan tetapi secara rata-rata, pemain-pemain profesional LCS memiliki gaji sekitar US$320.000 (Rp4,6 miliar). Data ini hanya berupa gaji pokok, tidak termasuk bonus atau uang hadiah turnamen.
Overwatch League (OWL) juga memiliki aturan gaji serupa, namun batas minimalnya lebih kecil yaitu US$50.000 (Rp715,9 juta). Sementara itu pemain OWL terkenal bisa mendapat gaji US$150.000 (Rp2,15 miliar) per tahun, seperti yang diterima sinatraa (Jay Won) ketika bergabung dengan tim NRG.
Sebagai perbandingan, gaji rata-rata penduduk Amerika serikat di tahun 2019 ini menurut U.S. Bureau of Labor Statistics adalah sekitar US$46.644 per tahun, atau kurang lebih Rp667,9 juta. Dapat kita lihat bahwa baik di LCS ataupun OWL, gaji minimum yang ditawarkan sudah lebih tinggi dari penghasilan penduduk rata-rata negeri Paman Sam.
Korea Selatan
Korsel adalah negara yang maju di dalam bidang esports. Ini dapat dilihat dari pendapatan para atletnya yang bisa mencapai angka sangat tinggi. Sebagai contoh, atlet-atlet yang bermain di League of Legends Championship Korea (LCK) rata-rata memperoleh gaji tahunan senilai 175.000.000 Won (Rp2,1 miliar), bahkan pemain paling top bisa meraih sampai 500.000.000 Won per tahun (Rp6,1 miliar).

Akan tetapi raihan gaji sedemikian besar hanya dirasakan segelintir orang, sekitar 5% dari jumlah pemain keseluruhan. Sebagian besar atlet (37,2%) justru hanya memiliki pendapatan antara 20.000.000 – 50.000.000 Won. Ini bahkan lebih rendah daripada rata-rata penghasilan penduduk Korsel yang nilainya adalah sekitar 63.000.000 Won (Rp770 juta) per tahun).
Korsel juga sempat dikabarkan memiliki masalah di cabang StarCraft II, di mana tim-tim esports sepakat untuk memberikan gaji tidak lebih dari 75.000.000 Won (Rp913,7 juta) kepada para atletnya. Akan tetapi kabar ini muncul di tahun 2016, jadi bisa saja sekarang kondisinya sudah berubah.
Tiongkok
Dengan populasi dan pangsa pasar begitu besar, Tiongkok dikenal sebagai salah satu negara top di bidang esports. Bahkan sangat sering ada atlet dari luar negeri yang bermain untuk tim Tiongkok karena tergiur dengan gaji yang ditawarkan. Beberapa waktu lalu, JD Gaming yang merupakan tim untuk League of Legends Pro League (LPL) sempat buka-bukaan tentang gaji atlet mereka.
Pemain baru yang bermain di tim akademi JD Gaming (Joy Dream) akan mendapat gaji minimal 250.000 Yuan (Rp524,2 juta). Ini masih berada di bawah gaji rata-rata penduduk Tiongkok yang ada di angka 293.000 Yuan (Rp614,6 juta), akan tetapi perbedaannya tidak sedrastis Korsel. Sementara itu atlet di tim inti JD Gaming memiliki gaji minimal 500.000 Yuan, alias Rp1,05 miliar per tahun.
Bila berbicara top player di Tiongkok, hanya langit yang menjadi batasnya. Contoh saja Vici Gaming, pemain paling mahal di divisi Dota 2 mereka dapat menerima gaji hingga 8.000.000 Yuan per tahun (Rp16,8 miliar), dan ini di tahun 2016. JD Gaming di tahun 2019 menawarkan gaji maksimum yang menyentuh angka 10.000.000 Yuan (Rp20,1 miliar). Ini angka yang fantastis.
Indonesia
Kita sudah melihat gambaran kehidupan atlet esports di beberapa negara maju. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Pertama-tama kita harus tahu dulu berapa gaji rata-rata penduduknya. Badan Pusat Statistik di akhir tahun 2018 menyatakan bahwa gaji rata-rata buruh laki-laki Indonesia ada di angka Rp3.060.000 per bulan. Sementara buruh perempuan mendapat rata-rata Rp2.400.000 juta per bulan.
Salah satu tim Indonesia yang pernah membuka nilai nominal gaji adalah EVOS Esports. Dalam sebuah wawancara di tahun 2018, General Manager EVOS Esports Indonesia Aldean Tegar (sekarang menjabat Assistant Vice President) menyebut bahwa gaji pokok tim Dota 2 EVOS adalah sekitar Rp5.000.000 – 6.000.000 per bulan. Laporan dari TribunNews juga menyebutkan gaji pokok Rp6.000.000 untuk divisi Mobile Legends, tapi kemudian ditambah Rp4.000.000 dari pihak Mobile Legends Professional League (MPL), dan bonus sebesar Rp1.000.000 setiap kali mereka mengikuti turnamen.
Di luar EVOS, Donkey (Yurino Putra) yang merupakan pemain Mobile Legends asal Surabaya pernah membeberkan gaji beberapa tim lain. Salah satunya Louvre yang ia sebut sebagai tim dengan penawaran tertinggi, yaitu Rp35.000.000 per bulan. Ia juga menyebut bahwa tim REVO eSports menawarkan gaji di atas Rp5.000.000 per bulan, tapi tidak memberi angka pastinya.

Angka-angka di atas menunjukkan bahwa profesi atlet esports di Indonesia layak dijadikan mata pencaharian. Namun di sisi lain, salah satu mantan pemain Team NXL yaitu Afrindo “G” Valentino pernah mengungkap fakta yang cukup miris. Dalam wawancara bersama Tirto, ia mengaku hanya mendapat Rp500.000 per bulan sebagai gaji pokoknya. Ini ditambah dengan bonus Rp2.000.000 bila berhasil masuk top global ranking, serta Rp3.900.000 per minggu dari pihak Moonton yang dibagi dengan rekan-rekan setimnya.
Kesenjangan jadi masalah utama
Seperti badan usaha pada umumnya, tim esports pun pada dasarnya adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk mencari untung. Besaran gaji yang dapat mereka keluarkan sebagai biaya operasional pun sangat tergantung dari kesuksesan serta ketenaran tim itu sendiri.
Newzoo melaporkan bahwa sebagian besar (82%) revenue di bidang esports datang dari investasi brand yang terdiri atas sponsorship, hak media, serta iklan. Jadi penghasilan ini berkaitan sangat erat dengan exposure, alias jumlah publikasi yang bisa didapatkan oleh suatu tim.
Masalahnya, tidak semua tim bisa mendapatkan exposure yang sama. Tim-tim terkenal yang sering juara turnamen tentu akan mendapat exposure lebih besar. Begitu pula tim-tim yang bertanding di liga dan turnamen besar, seperti OWL, LCK, atau MPL. Namun jumlah tim yang bisa tampil di liga-liga besar ini terbatas. MPL misalnya, hanya bisa diikuti oleh 12 tim tiap musimnya. Sementara AOV National Championship (ANC), meski jumlah slotnya lebih banyak, tetap saja terbatas pada 32 tim.
Layaknya atlet-atlet sepak bola yang bermain bukan di divisi utama, tim-tim yang tidak lolos ke liga esports terbesar harus puas dengan exposure terbatas dan gaji terbatas pula. Memang ada jalan lain untuk memperoleh penghasilan, misalnya dari streaming, penciptaan konten, hingga menjadi brand ambassador suatu produk. Tapi jalur-jalur ini pun bergantung pada popularitas. Selain kemampuan bermain, kepribadian di depan kamera hingga penampilan fisik juga jadi aset penting yang harus dimanfaatkan secara maksimal.
Tingginya minat masyarakat terhadap esports seolah jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, semakin banyak peminat artinya pasar semakin luas, dan itu akan membuat semakin banyak brand tertarik untuk berinvestasi dalam industri ini. Di sisi lain, pertumbuhan ini juga akan memunculkan lebih banyak pemain-pemain “biasa”, yang dalam perjalannya, mungkin tidak akan pernah meraih kesuksesan finansial besar seperti JessNoLimit.
Bukan bermaksud mematahkan kepercayaan bahwa impian itu pasti akan jadi nyata bila kita mau berusaha. Namun kenyataan memang tidak bisa memfasilitasi semua orang secara merata. Tidak mungkin tim Mobile Legends yang ada di Indonesia masuk ke dalam MPL semua. Dalam sepak bola yang usianya sudah berabad-abad pun banyak pemain profesional yang seumur hidupnya tidak pernah jadi juara Premier League. Lalu bagaimana nasib atlet-atlet level “biasa” seperti ini?

Memandang atlet esports sebagai profesi secara utuh
Bila kita kembali ke tujuan awal dari sebuah profesi, sebetulnya sederhana saja. Seseorang menjalani sebuah profesi pastilah untuk bisa mencari makan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Terlepas dari pada akhirnya ia jadi kaya raya atau tidak, setidaknya tujuan yang satu ini merupakan hal wajib yang tidak bisa dilepaskan.
Dengan berkaca pada tujuan dasar tadi, maka tujuan industri esports berikutnya sudah jelas, yaitu membuat para atlet profesional setidak-tidaknya dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, seminimal mungkin gaji seorang atlet esports hendaknya setara dengan nilai Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tempat ia berdomisili.
Di sinilah pemerintah memiliki peran penting. Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia mengatur bahwa setiap badan usaha wajib memberikan upah sesuai nilai minimum yang telah ditetapkan. Tim-tim esports besar memang pada umumnya sudah memberikan gaji di atas UMK, namun kita tidak tahu sebanyak apa atlet-atlet “underpaid” yang tak terekspos. Pengakuan negara terhadap status atlet esports sebagai sebuah profesi serta penerapan aturan ketenagakerjaan dapat menjadi dukungan besar bagi perlindungan kesejahteraan para atlet ini.
Developer dan penerbit game, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan kompetisi resmi, juga punya andil besar. Bila kita lihat dalam data di atas, sudah ada beberapa liga yang menerapkan aturan soal gaji minimum para atletnya, seperti OWL dan LCS. Sebagai kompensasi, liga-liga tersebut memberikan komitmen berupa wadah kompetisi jangka panjang kepada tim partisipan.
Ini juga menguntungkan para brand, karena kompetisi jangka panjang artinya mereka mendapat ruang untuk beriklan lebih banyak. Apalagi di OWL setiap tim juga merupakan perwakilan dari suatu kota, mirip seperti liga sepak bola. Artinya brand punya kesempatan untuk memanfaatkan keunikan kota tersebut sebagai pendukung metode periklanan. Brand lokal tiap kota juga punya peluang besar untuk beriklan, karena mereka memiliki basis pasar yang sangat dekat.
Esports butuh wadah kompetisi kelas menengah
Penciptaan wadah kompetisi jangka panjang dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah sistem franchising, seperti yang dilakukan OWL. Cara kerja sistem ini adalah dengan membuka slot bagi tim-tim yang ingin berkompetisi di OWL dengan syarat pendaftaran berupa pembayaran sejumlah uang. Kompetisi berbayar sekilas memang terdengar negatif, tapi dengan cara ini, komitmen tim dengan OWL menjadi lebih kuat. OWL juga berhak menerapkan kewajiban-kewajiban lain kepada tim selain soal gaji minimum, misalnya kewajiban untuk mempromosikan ekosistem esports lokal, program akademi dan regenerasi, dan sebagainya.

Untuk memfasilitasi atlet-atlet yang belum bisa bermain di level kompetisi tertinggi, Blizzard juga memiliki program kompetisi kelas menengah yang disebut Overwatch Contenders. Dalam kompetisi ini, tim-tim besar yang merupakan partisipan OWL diberi kesempatan untuk mendirikan divisi Academy untuk bertanding di Overwatch Contenders. Sambil menyelam minum air, kompetisi ini bisa membantu para atlet esports yang belum menjadi top player untuk mendapat exposure, memperoleh penghasilan, sekaligus mengasah kemampuan bermain.
Cara kedua adalah cara yang dilakukan oleh Ubisoft dalam Rainbow Six: Siege Pro League. Liga ini menerapkan pendaftaran terbuka, namun menyediakan wadah kompetisi bagi tim-tim yang masih berada di level bawah—bukan hanya kualifikasi, tapi juga kejuaraan sendiri yang bernama Challenger League. Ibarat sepak bola divisi 2, liga ini menawarkan hadiah walau jumlahnya tak besar, dan setiap tim memiliki kesempatan untuk mendapatkan exposure.
Tim-tim terbaik Challenger League nantinya berhak mendapatkan promosi ke Pro League yang merupakan liga utama, begitu pula tim-tim Pro League bisa saja degradasi ke liga bawahnya. Sistem ini memunculkan dinamika yang menarik karena popularitas sebuah tim bisa naik turun secara lebih luwes, meskipun tentunya tetap ada beberapa tim “mainstay” yang hampir tak mungkin sampai terdegradasi.
Peran lain developer/penerbit game terhadap kesejahteraan atlet juga bisa datang dari program revenue sharing. Perputaran uang di industri esports begitu besar, dan developer game populer bisa mendapat pemasukan hingga jutaan dolar tiap harinya. Para pelaku industri esports ini sebetulnya bisa dipandang sebagai “alat marketing” juga bagi para developer, jadi sudah sewajarnya mereka turut dapat bagian karena telah membantu membuat suatu game jadi lebih populer.
Beberapa game besar seperti Dota 2 dan Rainbow Six: Siege sudah menerapkan program revenue sharing itu. Caranya yaitu dengan menciptakan in-game item yang berhubungan dengan atlet atau tim esports tertentu. Pasar yang hendak diraih tentulah para penggemar atlet/tim yang bersangkutan, dan hasil penjualan berbagai item ini nantinya akan dibagi sesuai dengan suatu perjanjian kerja sama. Game yang sudah memiliki ekosistem esports cukup besar dan stabil hendaknya memiliki program revenue sharing seperti ini agar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan atlet-atlet esports di bawahnya.
Sustainability demi jaminan masa depan
Industri esports saat ini diprediksi masih akan terus berkembang, setidaknya hingga tahun 2021. Akan tetapi pasti akan tiba masanya perkembangan itu terhenti, dan industri esports masuk ke tahap kedewasaan. Bila sudah demikian, fokus industri esports harus bergeser dari mengincar pertumbuhan menjadi mengincar keberlanjutan (sustainability). Lagi pula, bila esports terbukti hanya merupakan sebuah bubble, dampaknya bagi industri esports sendiri akan buruk karena dapat membuat para stakeholder enggan terjun dan berinvestasi.
Industri yang sustainable juga penting agar para gamer muda yang ingin menjadi atlet esports di masa depan dapat mengejar impian mereka dengan lebih yakin. Tanpa adanya sustainability, dan tanpa adanya jaminan kesejahteraan untuk level kompetisi menengah, esports akan jadi profesi elit yang manfaatnya hanya dapat dinikmati oleh segelintir top player saja. Padahal dengan nilai revenue global yang mencapai US$1,1 miliar (sekitar Rp15,8 triliun), potensi untuk persebaran kesejahteraan itu jelas ada.
Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rasanya developer dan penerbit game adalah kunci dari penanganan masalah kesenjangan ini. Merekalah yang dapat mencetuskan program-program dengan sifat mengikat kuat, seperti sudah dilakukan OWL. Tinggal apakah mereka mau melakukannya, dan kapan?