Sejak 2018 kemarin, perputaran uang di industri esports Indonesia memang sudah mencapai miliaran Rupiah. Menurut catatan kami di Hybrid, kompetisi dengan total hadiah yang ‘hanya’ mencapai Rp1 miliar saja tidak masuk daftar 10 turnamen dengan hadiah terbesar di 2018.
Gemerlap dan hingar bingar esports juga mungkin membuat banyak orang awam takjub dengan industri baru ini. Namun demikian, dari perbincangan saya dengan sejumlah orang-orang di belakang layar, ada sebuah kekhawatiran tentang bagaimana industri dan ekosistem esports di Indonesia bisa sustain untuk jangka panjang dan scaling ke tingkat yang lebih tinggi ataupun lebih lebar.
Berhubung saya kebetulan sudah bekerja di industri game (khususnya media) dari 2008, menurut saya pribadi, ada satu kekurangan utama yang menjadi penyebab kekhawatiran atas sustainability dan scalability di industri game dan esports Indonesia yakni: minimnya kapasitas (skills, knowledge, dan perspectives) dan romantisme hiperbolis atas passion. Hal ini juga disadari oleh Yohannes Siagian, Kepala Pengembangan Esports Sekolah PSKD; sekaligus pionir yang membawa esports masuk ke dalam institusi pendidikan formal kala ia menjabat sebagai Kepala Sekolah untuk SMA 1 PSKD.
Menurutnya, banyak orang di esports Indonesia saat ini memang tidak mengenal bidang yang ia geluti. Ia memberikan pengandaian seperti seorang ABG yang baru saja punya pacar. ABG tersebut hanya tau yang sebatas kasat mata, seperti namanya siapa, mukanya cantik atau tidak; namun ia tidak memahami level yang lebih mendalam seperti kepribadian, kebutuhan, idealisme, tujuan hidup, impian, dan lain sebagainya.
Masalah kompetensi ini sebenarnya sudah ada sejak lama di industri ini; bahkan ketika esports belum sebesar sekarang ini. Namun, satu pertanyaan dari kawan saya, Wibi Irbawanto (yang mencoba menggalakan kesadaran dan kebutuhan soal legalitas dan hukum di esports), yang membuat saya akhirnya ‘terpaksa’ menuliskan artikel ini.
Pertanyaannya kala itu ke saya adalah, “apa yang terjadi jika pertumbuhan industri di esports tidak berbanding lurus dengan kapasitas para profesional yang menjalankannya?”
Faktanya, hal tersebut sebenarnya sudah terjadi meski memang gap antara pertumbuhan industri dan kapasitas para profesionalnya memang belum terlalu besar; karena nilai industrinya sendiri juga masih imut-imut menurut saya. Tribekti Nasima, salah satu penggiat esports Indonesia kelas kakap yang juga sudah malang melintang bekerja dari berbagai elemen ekosistem seperti publisher, tim esports, ataupun event organizer ini juga menyatakan keresahannya saat saya ajak berbincang. Menurutnya, rendahnya kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang memunculkan keresahan atas keberlanjutan (sustainability) esports Indonesia. “Uangnya (industri esports) ada buat sustain tapi kualitas (SDM) nya yang sangat minimalis.” Ujarnya.
Contoh pertama adalah soal konten di ekosistem dan industri game (termasuk esports) di Indonesia. Karena pengalaman saya yang memang lebih banyak di media dan konten, izinkan saya mengutarakan pendapat soal ini.
The Bad
Para pembuat konten dan para pengambil kebijakannya di industri ini masih banyak sekali yang berpatokan pada kuantitas semata, mengesampingkan kualitas, dan bahkan mengorbankan banyak hal lainnya demi kuantitas tadi (seperti reputasi, hubungan baik dengan ekosistem, ataupun paradigma tentang industrinya itu sendiri).
Menurut saya pribadi, salah satu penyebabnya ada di kapasitas orang-orang itu yang memang masih minim. Maksud saya seperti ini, setiap pelaku industri tentu harus punya tolak ukur keberhasilan di ranahnya masing-masing namun karena kapasitasnya masih minim mereka baru mampu melihatnya dari sisi kuantitas. Saya percaya bahwa setiap orang ingin juga mengukur seberapa bagus hasil karya/produksi mereka sendiri namun, karena keterbatasan tadi, acuan yang yang paling mudah digunakan adalah angka-angka yang terpampang jelas seperti jumlah subscriber, follower, pageviews, users, dan lain sebagainya.
Kenapa saya bisa bilang demikian? Argumentasi saya ada dua. Pertama, produk kreatif tak bisa hanya ditakar dari segi kuantitatif. Misalnya saja antara seri Lord of the Rings (Tolkien), seri Harry Potter (Rowling), atau malah Fifty Shades of Grey (James). Buat yang benar-benar tahu soal karya populis, saya kira jawabannya sudah jelas mana yang menang dalam soal plot, penokohan, penyajian cerita, ataupun soal pengaruhnya ke ekosistem di sekitarnya. Lainnya, andai dunia kreatif hanya mengenal popularitas sebagai tolak ukur keberhasilan, mungkin kita tidak akan punya nama-nama besar seperti Jostein Gaarder, Dream Theater, Quentin Tarantino, George Carlin, dan kawan-kawannya.
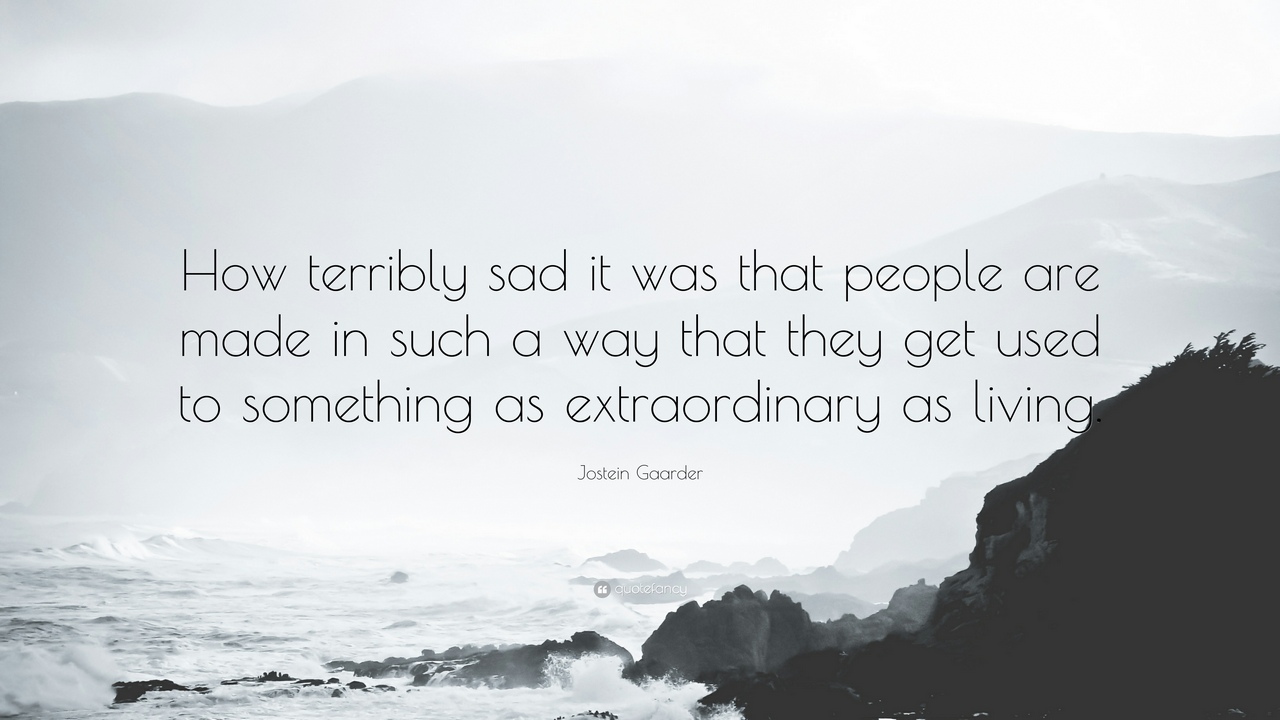
Kedua, popularitas/viralitas itu tidak selalu berbanding lurus dengan keuntungan. Kita mungkin memang hidup di jaman duopoli digital oleh Google dan Facebook yang sangat besar pengaruhnya terhadap pola pikir banyak orang, termasuk para pembuat konten. Berkat kedua perusahaan raksasa tadi, para produsen konten digital dan orang-orang di sekitarnya (seperti sponsor, pengiklan, dkk.) jadi seolah tak mampu berpikir kritis dan menemukan alternatif dari popularitas sebagai tolak ukur keberhasilan dan keuntungan.
Padahal, kenyataannya, popularitas dan keuntungan perusahaan tidak selalu berbanding lurus. Setelah artikel ini, saya akan lebih detail membahas soal media dan konten karena bisa jadi terlalu panjang untuk dijabarkan semuanya di sini. Namun, satu hal yang pasti, kenapa saya bisa bilang popularitas atau kuantitas itu tak selalu berbanding lurus dengan keuntungan perusahaan; karena kelas sosial dan ekonomi itu nyata, sedangkan Google dan Facebook belum mampu mengukur hal tersebut…
Contoh lainnya adalah dari sisi bisnis event di esports. Dari beberapa obrolan saya dengan sejumlah sponsor yang sudah mencoba masuk ke esports, ada sejumlah kekecewaan yang mereka utarakan. Untuk membahas hal ini, saya pun menghubungi kawan saya lainnya, Kris Ardianto yang sekarang menjadi Head of Business Development untuk MET Indonesia. Keistimewaan kawan saya yang satu ini, dibanding orang-orang bisnis lain yang bekerja di perusahaan esports di Indonesia sekarang, ada di pengalamannya yang pernah bekerja untuk perusahaan-perusahaan endemic kelas kakap, seperti NJT (salah satu distributor hardware PC terbesar di Indonesia), NVIDIA, dan ASUS. Karena sebelumnya ia bertanggung jawab mengurus masalah penjualan, pemasaran, dan penjenamaan, ia jadi pernah merasakan bagaimana berada di posisi sponsor. Perspektifnya tentu saja berbeda dari orang-orang bisnis lain yang belum pernah merasakan di posisi yang sama.
Kekecewaan yang diutarakan oleh beberapa sponsor tadi, menurut saya, memang karena banyak pelaku di industri ini masih terlalu mengagungkan yang namanya viewership. Kris pun setuju soal ini. Ia memang tidak menafikkan pentingnya viewership namun tidak hanya itu yang harus dipikirkan oleh para penyelenggara event esports. “Viewership itu ibarat IPK (Indeks Prestasi Kumulatif). Penting memang tapi kemampuan seseorang yang sebenarnya kan tidak bisa hanya diukur dari sana.”
Menurutnya, sponsor event di jaman sekarang pasti juga sudah mengejar ke arah engagement ataupun activation. Bentuk konkretnya seperti apa? Kris pun memberikan beberapa contoh. Pertama, ada sponsor yang ingin menargetkan product experience. Ada juga yang ingin langsung mengejar transaksi atau penjualan. Menurutnya, penyelenggara acara yang baik juga seharusnya mampu merumuskan dan menjalankan campaign seperti apa yang diinginkan sponsor.

“Kalau memang ada yang kecewa, itu berarti ada ekspektasi sponsor yang tidak tercapai. Sampai hari ini, selama saya kerja di MET, belum pernah ada sih sponsor yang kecewa.” Ujar Kris yang memulai kariernya sejak 2009.
Lalu apa rule of thumb untuk mereka yang ingin terjun jadi orang bisnis? Saya pun bertanya. “Know your market. Know your product. Semuanya harus based on data. Memang ga bisa kalau nekat.”
Dua contoh konkret tentang pemahaman pasar yang ia maksud tadi misalnya adalah berapa banyak kompetitor di pasar ini dan seberapa besar pasarnya? Selain 2 itu tadi, ada satu skill lagi yang dibutuhkan di semua profesi termasuk bisnis, yaitu komunikasi. “Contohnya di ranah bisnis soal komunikasi itu ya soal mencari tahu ekspektasi klien. Kalau sampai ekspektasinya bisa ga sinkron ya berarti skill komunikasinya yang kurang.”
Namun demikian, di sisi lain, Joey (panggilan Yohannes Siagian) juga menambahkan soal ketidaksesuaian ekspektasi bisnis. Menurutnya, “Sebagian masalah soal kekecewaan sponsor tentang esports itu datang dari mereka juga sih. Mereka cuma melihat angka-angka viewer dan mendengar popularitas esports. Tapi mereka tidak punya orang yang benar-benar paham esports. So they make bad or misinformed investments, then they are disappointed with results.”
Itu tadi beberapa contoh konkret dari yang saya lihat di ekosistem kita sekarang. Namun demikian, terlalu picik juga rasanya jika kita tidak mencoba mencari tahu akar permasalahannya. Daniel J. Boorstin, pernah mengatakan kurang lebih seperti ini, “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.”
Hal itu senada dengan apa yang dikatakan Joey. “Banyak juga orang esports yang sangat tertutup mengenai input dari luar pemahaman mereka mengenai esports. Tidak sekali dua kali saya mendengar dari orang yang dianggap ‘ahli’ bahwa “ini kan esports”, berbeda dengan olahraga atau bidang lainnya. Ada semacam pandangan di antara beberapa komponen ekosistem bahwa esports itu bidang yang unik dan berbeda yang tidak bisa dipahami oleh orang dari luar ekosistem esports.”
Menurutnya, hal itu juga lah yang menyebabkan banyak pelaku di esports yang hanya punya parameter kesuksesan itu-itu saja.
Berhubung saya memang fans beratnya Socrates, saya percaya bahwa hal terpenting yang harus dimiliki setiap manusia untuk berkembang adalah kesadaran diri bahwa kita memang belum tahu apa-apa tentang hidup, dunia ini, dan segala macam yang ada di dalamnya. Sebaliknya, merasa sudah tahu dan berhenti bertanya membuat kita terjebak dalam kebodohan kita sendiri.
Sebenarnya ada satu lagi penyebab yang diutarakan oleh Yohannes mengenai minimnya kompetensi di antara para pelaku esports. “Overall, the whole esports industry is lacking experience; and I’m not just talking esports experience but things like life experience and maturity as well. The average age in the esports industry is pretty low in comparison to other fields that have similar amounts of money flowing through it.”
Di satu sisi, saya setuju dengan pendapatnya bahwa usia dari kebanyakan para pelaku esports yang relatif muda – jika dibandingkan dengan nominal uang yang berputar di dalam industri ini – memang bisa berarti minimnya pengalaman, baik soal pengalaman hidup ataupun pengalaman sebagai seorang profesional. Saya percaya minimnya pengalaman hidup (personal) dan bekerja (profesional) memang berpengaruh terhadap kekayaan perspektif ataupun tingkat kesadaran menjalani proses namun, di sisi lain, saya harus menambahkan perspektif saya agar hal tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran.
Pertama, saya percaya bahwa usia dan kedewasaan berpikir itu bisa saja tidak berbanding lurus. Maksudnya, ada orang-orang yang masih muda tapi cukup dewasa dalam berpikir. Sebaliknya, ada juga generasi tua yang berpikir kekanak-kanakan. Di sisi lainnya, usia muda ataupun minimnya pengalaman itu tidak bisa jadi alasan untuk malas belajar dan lamban menyadari proses.
The Solution
Lalu, bagaimana solusinya?

Sebelum ke sana, saya harus tegaskan bahwa bukan berarti tulisan ini menihilkan pentingnya passion di esports. Bagaimana pun juga, saya percaya passion tetap bisa jadi landasan yang baik untuk menggeluti dan belajar di satu bidang. Namun, seperti judulnya, tujuan saya menuliskan artikel ini adalah untuk menyuguhkan argumentasi agar kita semua tidak terjebak dalam romantisme passion yang terlalu hiperbolis karena ada hal-hal lanjutan yang harus disadari dan dipelajari.
Jika kita berbicara soal solusi, ada 2 yang opsi yang sebenarnya bisa dipilih atau dijalankan bersama-sama. “Salah satunya menarik SDM berkualitas masuk. Karena orang bagus akan menarik orang-orang bagus juga. Namun pertanyaannya adalah bagaimana caranya membuat orang-orang tersebut tertarik masuk ke esports.” Ujar Bekti.
Hal ini sebenarnya jugalah yang sudah dilakukan oleh MET Indonesia. Selain kawan saya Kris tadi, ada juga beberapa nama profesional berpengalaman dari industri terkait yang ditarik ke MET Indonesia, seperti Reza Afrian Ramadhan (Head of Marketing MET Indonesia) ataupun Herry Wijaya (Head of Operation MET Indonesia).
Sayangnya, nama-nama di atas memang berasal dari industri terkait. Reza sebelumnya dari ASUS dan Acer. Sedangkan Herry merupakan salah satu senior di ranah EO esports Indonesia yang paling dipandang. Menarik saja rasanya, menurut saya, andai ada para senior dari industri non-endemik (perbankan, hukum, properti, dkk.) yang berubah halauan ke esports karena ada perspektif baru yang bisa ditawarkan. Itulah sebabnya, Yohannes Siagian sering jadi target narasumber saya di banyak artikel berat (wkakwkkwa) karena ia sudah mengantongi belasan tahun pengalaman dari industri pendidikan.
Mencari orang-orang yang tepat dan punya jam terbang tinggi di spesialisasi tertentu itu, bagi saya, salah satu cara yang tepat untuk memperbesar peluang kesuksesan sebuah perusahaan ataupun keseluruhan ekosistem. Sayangnya sampai hari ini, tidak sedikit juga yang masih meremehkan ranah-ranah tertentu.
Mungkin memang gampang kalau yang dikejar adalah kualitas KW 2; namun untuk tingkatan yang benar-benar dapat dijaga konsistensi kualitas atau performanya, saya kira hal tersebut tidak mudah diberikan. Ibaratnya, anak SD saja juga bisa masak mie instant ataupun merebus air. Tapi untuk meracik hidangan yang sekelas hotel ataupun restoran bintang 5?

Selain solusi pertama menarik orang-orang yang memang sudah punya kapasitas (baik dari industri endemik ataupun non-endemik), solusi lain yang bisa dilakukan adalah dengan memaksa para profesional yang sudah ada di industri esports sekarang (ataupun akan datang) untuk belajar dengan cepat dan terbiasa untuk melihat segala sesuatunya dari beragam perspektif.
Ada banyak sekali hal yang bisa dikejar untuk meningkatkan kemampuan, tergantung dari skill yang diinginkan. Menurut Bekti, misalnya, buat yang ingin jadi orang bisnis, mereka bisa baca Never Eats Alone (Keith Ferrazi & Tahl Raz) ataupun buku-buku lain yang bisa digunakan untuk meningkatkan skill jualan. Di sisi lain, jika yang dibutuhkan adalah posisi Project Manager (PM), “PM itu kan paling utama ada di organizational skill nya. Jadi, harus belajar terstruktur. PM itu juga harus mempelajari semua hal yang dikerjakan oleh anak buahnya sehingga bisa menakar beban kerja masing-masing anggotanya. Belajar stress management dan self development itu juga saya kira penting buat yang mau jadi PM berkualitas.” Ujarnya.
Buku-buku teori tentunya bisa jadi sumber utama bagi mereka-mereka yang memang serius ingin belajar. Namun, berhubung saya tahu kadang waktu kita sebagai para pekerja sudah tidak sebanyak dibanding saat kita kuliah dulu, berbagai video seminar bisa jadi semacam ‘cemilan sehat’. Artikel-artikel panjang seperti yang kami coba tawarkan di Hybrid (Meninjau Kembali tentang Tren BA Esports Cantik di Indonesia: Sebuah Opini, Upaya Mengurai Permasalahan Ekosistem Esports Dota 2 Indonesia, Regenerasi Esports: Sebuah Abstraksi dan Kedewasaan Menjadi Solusi, dkk.) juga sebenarnya bisa jadi langkah awal untuk mengusik rasa keingintahuan. Promosi dulu yak… Wkwkawkwak.
Berbicara soal belajar, saya kira saya juga harus membahas soal ilmu yang kita dapatkan dari institusi pendidikan formal. Pasalnya, menurut saya, ada salah kaprah yang terjadi di pola pikir kaum muda termasuk di para pekerja esports. Dari perbincangan saya dengan banyak orang, tidak sedikit yang percaya bahwa ilmu yang didapat di bangku kuliah itu tidak relevan lagi termasuk di bidang esports.
Memang, belajar itu bisa dilakukan di mana pun kita berada; tak harus terkurung di ruang-ruang edukasi formal. Memang, tidak semua teori yang kita dapatkan saat sekolah dan kuliah itu punya nilai pragmatis di setiap desk job kita sebagai seorang profesional. Namun, saya sungguh percaya mindset dan logika berpikir yang bisa dipelajari dari ruang pendidikan formal itu bisa digunakan di setiap keputusan kita (jika memang disadari dan dipahami).
Misalnya, mereka-mereka yang belajar dan memahami aljabar linear bisa mencari logika apa yang ada di balik sistem itu. Saya sendiri yang lulusan Fakultas Sastra juga bisa menggunakan mindset storytelling (atau malah teori Hegemoni dari Gramsci) yang saya dapatkan saat saya kuliah dulu dalam banyak hal yang saya lakukan sebagai seorang pekerja sekarang: bagaimana bercerita tentang perusahaan, produk, event, atau apapun. Setidaknya menurut Yuval Noah Harari, cerita dengan kekuatan narasi yang istimewa bahkan mampu menguasai dunia.
https://youtu.be/nzj7Wg4DAbs
Saya sungguh percaya ada banyak benang merah yang bisa ditemukan dari teori-teori yang kita dapat di institusi pendidikan formal dengan yang kita hadapi sehari-hari (personal ataupun profesional), asalkan kita memang mampu memahaminya di tingkat yang paling dalam.
The Good News
Meski penjabaran dan argumentasi saya tadi mungkin terasa pesimistis, perspektif positif sebenarnya juga bisa digunakan untuk membaca kondisi esports kita sekarang ini.
Dengan kapasitas SDM saat ini saja, esports Indonesia sudah berhasil menarik perhatian banyak pihak dan mengalirkan dana yang lumayan. Bayangkan jika SDM nya bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi…
Saya sudah berada di industri ini cukup lama dan melihat naik turunnya bak jungkat-jungkit. Bagi saya, hal ini tidak bisa dimaklumi, apalagi dijadikan pembenaran. Jujur saja, ambisi pribadi saya saat ini adalah bagaimana industri ini tidak kehilangan momentumnya sehingga bisa terus berkembang dan memakmurkan semua pihak yang terkait di dalamnya.
Semoga saja, artikel ini bisa menjadi memancing kesadaran dan keinginan belajar bagi semua orang yang berkepentingan dan berkeinginan melihat industri game dan esports Indonesia bisa terus berkembang dan bertahan. Satu hal yang saya percayai sejak lama, belajar itu bisa juga menyenangkan. Apalagi buat mereka-mereka yang memang punya passion bermain game, proses pembelajaran itu sendiri juga bisa dimaknai sebagai sebuah permainan.
Akhirnya, izinkan saya menutup artikel panjang ini dengan sebuah kutipan dari salah satu tokoh yang menjadi inspirasi saya untuk terus belajar dan bermain game.
“The spirit of playful competition is, as a social impulse, older than culture itself and pervades all life like a veritable ferment. Ritual grew up in sacred play; poetry was born in play and nourished on play; music and dancing were pure play….We have to conclude, therefore, that civilization is, in its earliest phases, played. It does not come from play…it arises in and as play, and never leaves it.” Johan Huizinga (Homo Ludens: A Study of the Play-Elements in Culture).













