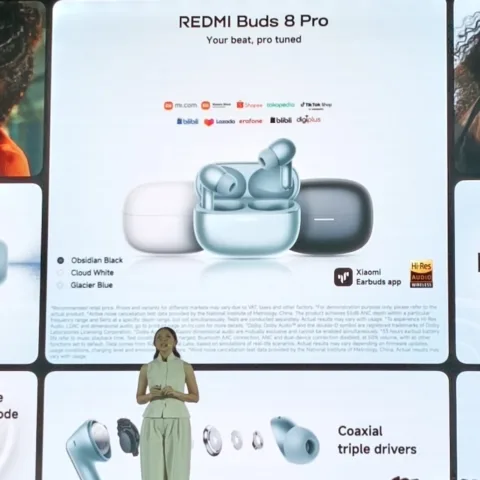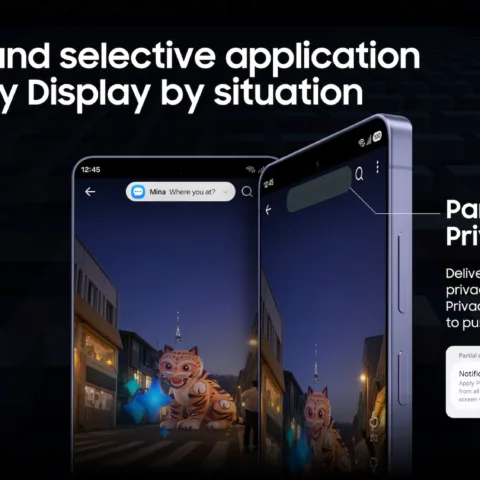Bulan April 2019 kemarin menjadi bulan berkabung buat para pemerhati esports Dota 2 Indonesia. Pasalnya, tanggal 25 April 2019, Rex Regum Qeon (RRQ) menutup divisi Dota 2 mereka. Tak lama berselang, 29 April 2019, The Prime Esports juga turut menutup divisi tertua mereka.
Memang, tim Dota 2 Indonesia yang paling berprestasi sampai sekarang, BOOM ID masih terus bertahan dan malah mengukir prestasi-prestasi baru di tingkat internasional. Selain itu, PG Barracx juga bahkan punya 3 tim Dota 2 (setidaknya sampai artikel ini ditulis, sepengetahuan saya). EVOS Esports juga sepertinya masih punya keyakinan dengan divisi Dota 2 mereka, berhubung belum lama menarik salah satu pemain bintang; Muhammad “inYourdreaM” Rizky.

Namun demikian, bubarnya RRQ dan The Prime bisa jadi bukti nyata memang ada masalah yang tak terurai (atau bahkan tak disadari) dengan ekosistem esports Dota 2 Indonesia. Pasalnya, kedua organisasi ini memang bisa dibilang sebagai salah dua tonggak sejarah perkembangan ekosistem esports Dota 2 Indonesia.
RRQ merupakan salah satu pionir esports Dota 2 di sini dan menjadi rumah bagi salah satu legenda Dota Indonesia, Farand “Koala” Kowara. RRQ juga menjadi tempat berkembang besarnya Kenny “Xepher” Deo, yang sempat bermain untuk TNC Tigers dan sekarang membawa nama Geek Fam. Kedua tim tadi adalah tim besar asal Malaysia.
Di sisi lain, The Prime Esports juga tak bisa dipandang sebelah mata atas signifikansinya memantapkan Dota 2 jadi game esports terlaris selama bertahun-tahun di Indonesia; sebelum mobile esports menyerbu. Mereka sempat menguasai dunia persilatan Dota 2 Indonesia beberapa tahun silam. The Prime Esports, yang dulu dikenal dengan nama TP NND, juga menjadi kampung halaman yang membesarkan nama-nama besar di Dota 2; seperti inYourdreaM, KelThuzard, Nafari, Rusman, R7, dan yang lainnya.
Untuk mencoba mengurai masalah ekosistem esports Dota 2 di Indonesia kali ini, saya pun menghubungi berbagai pihak terkait. Saya menghubungi General Manager The Prime Esports, Anton Sarwono, dan CEO Team RRQ, Andrian Pauline. Tidak lupa juga saya menanyakan beberapa pendapat shoutcaster Indonesia yang besar dari scene Dota 2 seperti Gisma “Melon” Priayudha Assyidiq, Riantoro “Pasta” Yogi, dan Dimas “Dejet” Surya Rizki.
Dari obrolan saya bersama kawan-kawan saya tadi, ada sejumlah masalah yang saling terkait yang saya temukan di ekosistem esports Dota 2. Sebelum kita membahas masalah-masalah tadi, saya kira penting saja untuk menyebutkan motivasi saya menuliskan ulasan ini. Saya pribadi sudah berkecimpung di industri game Indonesia dari 2008. Jadi, saya punya kepentingan dan keinginan untuk melihat industri ini terus bertahan (sustainable) sampai nanti di masa mendatang (atau paling tidak sampai saya sudah tak bisa bekerja lagi).
Karena itulah, saya tak bermaksud membuat tulisan ini menjadi ‘drama’ dengan menyudutkan satu pihak tertentu. Motivasi utama saya hanyalah bagaimana Anda dan kawan-kawan sekalian yang peduli dengan industri ini menyadari masalah dan berupaya bersama untuk ekosistem yang lebih baik.
Regenerasi Ekosistem yang Tersendat
Beberapa waktu yang lalu, saya sebenarnya pernah menuliskan perbincangan saya dengan Yohannes Siagian, Vice President EVOS Esports, tentang masalah regenerasi ini (Regenerasi Esports: Sebuah Abstraksi dan Kedewasaan Menjadi Solusi). Namun mungkin memang proses regenerasi sendiri adalah proses panjang yang butuh waktu.
Ketika kita berbicara soal regenerasi, hal ini tidak harus selalu berarti kehabisan pemain karena masalah usia. Saya kira saya harus meluruskan hal ini karena banyak yang masih salah kaprah. Namun permasalahan regenerasi adalah juga soal bagaimana ekosistem mampu mencetak pemain-pemain baru, dengan jenjang yang jelas.
Saya sebenarnya sudah mulai melihat persoalan ini sejak tahun 2018. Pasalnya, di banyak bursa transfer tahun lalu pun, tidak banyak nama-nama pemain yang baru muncul. Hampir semua bursa transfer pemain Dota 2 di 2018 adalah soal pemain lama yang pindah dari tim profesional ke tim lain. Bukan pemain yang benar-benar belum pernah bergabung dengan tim profesional sebelumnya.
Imbas dari impotensi regenerasi ini pun dirasakan oleh The Prime dan RRQ. Menurut pengakuannya masing-masing, baik Anton dari The Prime ataupun AP dari RRQ sebenarnya juga sudah mencoba memasukkan pemain rookie ke dalam divisi Dota 2 mereka. Namun solusi ini tak berhasil karena kendala yang tak jauh berbeda.
AP dari RRQ mengatakan bahwa kendala di para pemain rookie yang ia temukan adalah tingkat permainan mereka yang terlalu jauh di bawah standar. “Standarnya jauh banget (dengan pemain pro).” Kata AP. Standar yang terlalu jauh ini memang jadinya tidak masuk akal untuk kondisi tim Dota 2 RRQ terakhir. Pasalnya, sebelum bubar, tim mereka masih punya pemain-pemain berpengalaman seperti Rusman, R7, Yabyoo, dan Acil.
Sedangkan Anton bercerita bahwa kendalanya ada di para pemain baru yang tidak bisa full time alias bootcamp karena kesibukan mereka sebagai pelajar ataupun mahasiswa. Tanpa bootcamp, jelas perkembangan mereka jadi tak maksimal. Jadwal latihan mereka pun jadi tak bisa optimal seperti layaknya para pemain yang bisa terus tinggal di gaming house.
Masalah regenerasi tadi terjadi karena memang tak ada ruang-ruang kompetitif untuk kelas amatir ataupun pelajar (mahasiswa) sebelumnya. Tahun 2018 dan 2019 ini sebenarnya sudah ada beberapa kompetisi Dota 2 untuk kelas di bawah profesional, seperti JD HSL untuk kelas SMA dan IEL untuk kelas mahasiswa. Namun demikian, sekali lagi, proses regenerasi butuh waktu.

Di sisi lainnya lagi, menurut saya, persoalan regenerasi ini juga terjadi tak hanya untuk suplai pemain namun juga untuk orang-orang di belakang layarnya. Dalam kasus ini, ekosistem esports kita juga masih kekurangan suplai manajer tim yang mumpuni.
Saat saya berbincang dengan Anton dari The Prime, saya pun menanyakan hal ini, “jika punya manajer tim yang hebat, apakah memungkinkan sebuah tim bisa berkembang tanpa bootcamp?” Anton pun menjawab, “mungkin saja.”
“Betul (talent pool manajer yang kurang juga). Makanya ada beberapa divisi (The Prime) yang masih gua pantau dari jauh. Cuma, kalau manajernya qualified, langsung gua lepas.” Cerita Anton.
Berhubung akan terlalu panjang jika dibahas detailnya di sini, mungkin saya akan bahas khusus soal manajer tim esports di lain waktu. Namun singkatnya, meski memang idealnya manajer tim bisa ditempati oleh mantan-mantan pemain seperti Aldean Tegar Gemilang dari EVOS Esports ataupun Brando Oloan dari BOOM ID, jalur tersebut makan waktu terlalu lama untuk mencetak sumber daya manusia baru yang kompeten.

Meski demikian, persoalan suplai pemain profesional mungkin lebih pelik ketimbang manajer tim. Karena kemampuan mengatur sumber daya manusia bisa dilatih di ruang-ruang lain, di luar ekosistem esports. Sedangkan mencetak para pemain rookie yang siap naik kasta memang hanya bisa dilakukan di dalam ekosistem esports-nya sendiri.
Absennya Dukungan Publisher
Jika berbicara mengenai ruang kompetitif buat kelas rookie, memang ada 2 pihak yang bisa dibilang ideal untuk menangani hal ini: pemerintah dan publisher game tersebut. Sayangnya, untuk Dota 2, mungkin kita tidak akan bisa sampai pada kondisi ideal.
Jika berbicara soal peran pemerintah di esports, jujur saja, saya tak berharap banyak. Kenapa? Karena industri esports Indonesia sendiri belum bisa menjadi sumber devisa untuk negara. Lain halnya jika esports sudah bisa menyumbangkan sebagian keuntungannya untuk negara.
Di sisi lainnya, AP dari RRQ mengutarakan pendapatnya bahwa publisher game-nya lah yang seharusnya memerhatikan masalah ekosistem rookie. “Ini dari developer/publisher game-nya yang harusnya notice. Mereka yang punya power lebih. Tapi ada baiknya juga semua pelaku di industri aware tentang hal ini.” Ujar AP.
Saya sepenuhnya setuju dengan pendapat AP tadi. Sayangnya, dari awal Dota 2 dirilis, saya belum pernah mendengar bisikan-bisikan tentang keseriusan Valve menggarap scene esports game mereka di Indonesia.
Kenapa publisher merupakan pihak yang ideal untuk menggarap scene rookie? Karena hal tersebut adalah bentuk investasi jangka panjang untuk pihak ketiga, tim dan event organizer, dan tidak semua pelakunya punya kapasitas untuk itu.
Namun demikian, ketimbang menanti Valve melirik esports Indonesia yang mungkin tak akan pernah terjadi, para pelaku industri esports kita harus mau bertindak dan berbuat sesuatu.

“Harusnya ada roadmap yang jelas, setiap turnamen besar harus dipaketin sama turnamen amatirnya. Bahasa sederhananya… Amatir scene perlu disubsidi. Nyari untung di pro-scene; tapi supaya industrinya sustain, harus ada timbal baliknya dong. Jangan semua mau metik tapi ga mau menabur. Hahaha!” Jelas AP seraya berseloroh.
Hal yang serupa juga diutarakan oleh Gisma A.K.A Melondoto. Para pelaku industri harus mau membagi porsi antara mobile esports (yang mungkin sekarang dianggap lebih menguntungkan) dan PC. Misalnya, 70% resource untuk mobile dan 30% untuk PC. Menurut Melon, ajang kompetitif untuk kelas amatir memang bisa jadi solusi untuk regenerasi.
Saya kira memang solusi soal ajang kompetitif untuk amatir ini memang harus segera dijalankan, ataupun digalakkan buat yang sudah berjalan, karena proses pematangan para pemain amatir butuh proses yang tidak sebentar.
Minimnya Pemahaman Exposure sebagai Komoditas Industri
Jika berbicara soal esports mobile, tak jarang hal tersebut juga sering dijadikan kambing hitam atas menurunnya popularitas esports di PC; seperti yang diutarakan oleh Dimas Dejet. Ia berpendapat bahwa esports mobile membuat esports PC kalah dalam hal exposure. Lagipula, Dejet juga menambahkan bahwa esports sekarang adalah soal industri. Jadi, menurutnya, ada ideologi yang harus dikorbankan. “Ada kalanya nyerah sama ideologi daripada memaksakan sesuatu yang tidak menghasilkan.” Ungkap Dejet.
Saya pribadi setuju dengan sebagian pendapatnya. Dari sisi exposure, saya kira saya tak perlu menjelaskan panjang lebar kenapa esports PC memang kalah popularitasnya saat ini. Menurunnya exposure esports PC memang ada kaitannya dengan meningkatnya popularitas esports mobile. Namun, masih banyak orang yang mungkin belum sadar betul soal perhatian dan exposure sebagai komoditas.
Faktanya, jika kita berbicara soal exposure atau perhatian end-user, ada satu batasan absolut yang tak dapat dipungkiri; yaitu waktu kita.

Setiap manusia, siapapun itu, cuma punya waktu sehari 24 jam. Jika ada lebih banyak orang yang menghabiskan waktunya bermain game mobile ataupun menonton esports-nya, hal ini berarti lebih sedikit waktu yang tersisa untuk esports lainnya (dalam hal ini PC). Namun demikian, hitung-hitungan tadi hanya berlaku untuk end-user yang memang bermain game ataupun menonton esports untuk 2 platform, PC dan mobile.
Padahal, saya tahu betul bahwa memang ada orang-orang yang hanya bermain game di satu platform dan orang-orang yang tidak menonton semua pertandingan esports untuk semua game yang ada. Misalnya, ada banyak orang yang memang hanya bermain di console ataupun hanya di PC.
Banyak yang mengatakan bahwa platform mobile lebih populer gara-gara harganya dan mobilitasnya. Hal tersebut memang ada benarnya namun jarang saya yang mendengar argumentasi soal keterbatasan waktu untuk gamer console dan PC. Maksud saya seperti ini, bisa jadi, gamer PC dan console itu memang punya waktu luang yang lebih terbatas. Kembali lagi, kita semua punya keterbatasan waktu yang absolut.
Karena itu, gamer PC dan console mungkin tidak akan punya banyak waktu lebih untuk menonton esports-nya. Apalagi, jika berbicara soal exposure dan perhatian, esports Dota 2 sendiri harus bersaing dengan pertandingan-pertandingan tingkat internasional (Minor ataupun Major). Jadwal turnamen luar dan dalam negeri sendiri sudah tak relevan lagi diperdebatkan jika perspektif waktu tadi masih disadari.
Maksud saya seperti ini, anggaplah di satu hari ada turnamen Minor jam 2 pagi. Fans yang menonton pertandingan itu sampai selesai, mungkin tak akan menonton pertandingan lokal keesokan harinya karena masih mengantuk setelah begadang semalaman. Jadwal pertandingan sudah tak lagi relevan dalam berebut perhatian penonton karena, nyatanya, kita punya kesibukan lainnya setiap hari yang menghabiskan waktu.
Kenapa hal ini jadi masalah yang penting disadari? Karena industri yang baik adalah yang paham betul soal komoditas, satuan, dan alat tukar industri tersebut.
Kurangnya Fokus dan Investasi Jangka Panjang
Mengutip kembali kata AP di atas tadi, yang mengatakan bahwa masalah regenerasi harus disubsidi, saya memang setuju sekali dengan tujuannya. Namun, saya pribadi kurang setuju dengan istilah dan konsep soal ‘subsidi’ untuk regenerasi.

Di sisi lain, dari obrolan saya bersama Dejet dan Melondoto, pandangan esports mobile yang lebih menggiurkan dan menguntungkan saat ini memang jadi konsensus sebagian besar pelaku bisnis esports di Indonesia. Tak hanya itu, dari pengalaman saya berbincang dengan berbagai pelaku industri esports belakangan ini juga mengemukakan hal yang senada. Maka dari itu, lebih banyak pelaku bisnis esports (mulai dari tim, EO, sponsor, media, bahkan para pekerjanya) saat ini yang fokus menggarap game-game mobile ketimbang PC; termasuk Dota 2.
Lalu apa benang merahnya antara soal istilah ‘subsidi’ tadi dan pergeseran tren ke mobile esports? Menurut saya, benang merahnya ada di kurangnya fokus dan investasi jangka panjang di banyak pelaku bisnisnya.
Itu tadi kenapa saya kurang setuju dengan istilah ‘subsidi’. Subsidi itu seperti sebuah sedekah atau hibah, yang memang tidak mengharap imbalan. Sedangkan menghidupkan ekosistem kompetitif untuk tingkat amatir adalah soal investasi jangka panjang, setidaknya menurut saya pribadi. Pasalnya, memang harus ada imbas alias keuntungan yang diharapkan dan bahkan direncanakan dari soal investasi untuk ekosistem kelas amatir.
Izinkan saya mengambil contoh dari pemain industri-industri besar di luar sana. Jika kita berbicara soal industri teknologi, R&D (research and development) adalah bentuk investasi jangka panjangnya. Menurut laporan dari Recode yang dirilis di VOX tahun 2018, Amazon bahkan menggelontorkan dana sampai mendekati angka US$23 miliar untuk R&D. Alphabet, induk perusahaan Google, merogoh kocek mereka sampai dengan US$16 miliar untuk kebutuhan yang sama. Sedangkan Intel mencapai angka US$13 miliar dan Microsoft mencapai angka US$12 miliar.
Modal untuk R&D yang besarnya amit-amit tadi memang tak bisa langsung diraih keuntungannya dalam waktu dekat namun hal ini harus dilakukan untuk memastikan para pemain tadi (termasuk industrinya) masih bisa sustain untuk jangka waktu yang panjang.
Kurangnya fokus untuk jangka panjang ini jugalah yang saya lihat dari para pelaku industri esports yang beramai-ramai menggelontorkan sebagian besar anggaran ke mobile esports, hanya karena trennya lagi ramai di sana.
Sebelum salah kaprah, saya harus katakan bahwa saya tak ada masalah dengan ramainya esports mobile. Saya pribadi, sebagai salah satu pelaku industri game Indonesia, sungguh bersyukur ada Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) dan Moonton di Indonesia. Karena, bagaimanapun juga, mereka punya andil besar membawa industri esports Indonesia sampai ke titik ini.

Kritik saya bukanlah soal esports mobile-nya namun kepada perilaku gegabah yang mengambil keputusan hanya dari sebatas tren semata tanpa ada pertimbangan konsekuensi jangka panjang. Jika hal ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin juga game-game esports mobile yang sedang naik daun sekarang akan mengalami nasib yang sama.
Misalnya saja soal tren yang terjadi di ajang kompetitif di 2018. Tahun lalu, sebagian besar turnamen esports pihak ketiga (jika tidak mau dibilang semua) pasti ada pertandingan Mobile Legends nya. Bagi saya pribadi, hal ini juga sebenarnya tidak baik untuk sustainability dari Mobile Legends karena fans esports nya bisa jadi bosan dan ‘kebal’ dengan hype yang coba ditawarkan.
Anggap saja seperti ini, andaikan ada Piala Dunia dan Liga Champion (sepak bola) 5 kali dalam setahun. Apakah hype-nya masih bisa terjaga? Saya kira tidak.
Hal ini juga sebenarnya terjadi untuk kasus Dota 2. Faktanya, sebelum ada Mobile Legends, Dota 2 menjadi favorit para penyelenggara esports di Indonesia. Namun semuanya memang hanya memilih Dota 2 karena trennya saat itu, tanpa ada pertimbangan lebih lanjut.
Memikirkan solusi mencari keuntungan dari investasi jangka panjang itu memang tidak mudah karena tingkat kompleksitasnya yang tinggi. Namun, buat Anda yang membaca artikel ini, tak ada salahnya juga untuk mulai berpikir ke depan dan mulai membuka diskusi tentang ini.
Faktanya, pengetahuan kolektif (collective wisdom and knowledge) adalah yang membuat kita manusia berkembang sampai hari ini, menguasai dunia, dan berbeda dari binatang lainnya.
Soft Skill Pro Player Dota 2 yang Perlu Digali Lebih Jauh

Obrolan saya bersama Pasta lah yang membuat saya menyadari memang butuh satu bagian lagi dalam upaya saya kali ini mengurai permasalah ekosistem Dota 2 Indonesia.
“Sama ini paling, player-nya bisa branding diri mereka juga atau engga, supaya penonton bisa lebih antusias buat nontonin mereka live stream atau tanding. Kalau di MLBB kan gitu.” Ujar Pasta.
Di sisi lainnya, saat saya berbincang dengan AP dan Anton, saya juga sebenarnya menanyakan soal memasukkan pemain luar negeri ke divisi Dota 2 mereka. Kendala yang mereka rasakan soal ini juga sama, yaitu soal bahasa.
2 hal tadi adalah soal soft skill yang saya kira punya pengaruh terhadap masalah ekosistem Dota 2 Indonesia.
Mari kita bahas soal bahasa lebih dulu. Tim-tim Dota 2 luar negeri sebenarnya juga terdiri dari pemain-pemain berbagai negara. OG saat menjadi juara The International 2018 berisikan pemain-pemain dari 5 negara. Team Liquid saat jadi juara The International 2017 bahkan berisikan pemain dari 6 negara.
Di CS:GO, ada 2 pemain Indonesia yang juga bermain untuk tim Tiongkok, TYLOO; Hansel “BnTeT” Ferdinand dan Kevin “xccurate” Susanto. Saya yakin mereka tidak pakai bahasa Indonesia saat berkomunikasi dengan rekan satu timnya yang berasal dari Tiongkok.
Selain berguna untuk timnya sendiri yang memungkinkan untuk mengambil pemain luar negeri, penguasaan bahasa selain bahasa Indonesia sebenarnya penting juga untuk para pemain kita jika tidak ingin terjebak dengan scene esports lokal. Soal ini, solusinya mungkin sudah bisa dimulai dari sekarang untuk tim-tim esports lokal yang bermain game esports yang scene-nya besar di luar sana; seperti menerapkan aturan untuk pembelajaran bahasa Inggris untuk semua pemainnya.
Di sisi lain, seperti yang diungkap oleh Pasta tadi, saya pribadi setuju dengan pendapatnya soal para pemain Dota 2 Indonesia yang memang kurang memanfaatkan panggung mereka sebagai figur publik. Selebritas atau popularitas pemain esports, menurut saya, memang berpengaruh terhadap scene-nya secara keseluruhan.
Maksud saya seperti ini, rivalitas antara Messi dan Ronaldo (sebelum pindah ke Juventus) adalah salah satu faktor juga ramainya penonton pertandingan antara Barcelona dan Real Madrid. Hal ini juga terjadi di pertandingan MLBB antara RRQ dan EVOS Esports, karena masing-masing punya Lemon dan JessNoLimit. Ketokohan dua pemain tadi di MLBB, saya kira berpengaruh terhadap jumlah penontonnya.
Dari pengalaman saya sebagai jurnalis, saya sendiri merasakan bahwa para pemain MLBB itu lebih ramah terhadap media. JessNoLimit yang bahkan punya 5,5 juta subscribers di YouTube itu media darling karena memang ia cukup pandai bersikap kepada para awak media. Demikian juga dengan banyak pemain MLBB yang saya kenal seperti Oura, G, Fabiens, Arss, Jeel, dan kawan-kawannya yang akan terlalu banyak jika disebutkan semuanya di sini.
Memang, tak semua pemain MLBB juga terbuka diwawancarai (buat anak-anak media esports dan game pasti tahu siapa saja yang saya maksud, hahahaha…) Namun, setidaknya jumlah para pemain MLBB yang lebih ramah saat dimintai kutipan ataupun komentar itu lebih banyak ketimbang pemain Dota 2 (setidaknya berdasarkan pengalaman saya pribadi).
Soft skill semacam bahasa ataupun kepandaian memanfaatkan panggung sebagai figur publik ini, saya percaya betul sangat berpengaruh terhadap ekosistem esports-nya secara keseluruhan. Harapannya, lebih banyak manajemen tim yang juga mulai menyadari betapa pentingnya hal ini untuk diajarkan.

Penutup
Sebelum jadi skripsi ratusan halaman, itu tadi 5 masalah yang saya temukan berpengaruh terhadap ekosistem Dota 2 di Indonesia. Saya kira masalah-masalah ini juga sebenarnya terjadi di ekosistem game esports lainnya di Indonesia (CS:GO uhuk…).
Jadi, dari upaya saya mengurai permasalahan ini, semoga saja kita semua bisa belajar lebih jauh dan berdiskusi sehat demi ekosistem esports Dota 2 ataupun game esports lainnya yang lebih dewasa dan berumur panjang.