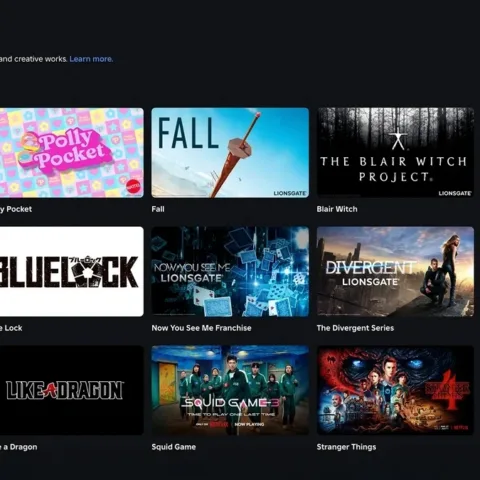PlayStation baru saja memamerkan video gameplay dari game Harry Potter terbaru, Hogwarts Legacy. Namun, sambutan akan game eksklusif PlayStation itu terpolarisasi. Di satu sisi, banyak fans Harry Potter yang mengungkap bahwa mereka tidak sabar untuk memainkan game tersebut. Di sisi lain, tidak sedikit orang yang mendorong para gamers untuk tidak membeli game itu atau bahkan membajaknya. Biasanya, orang-orang yang masuk dalam kategori kedua adalah mereka yang pro dengan transgender.
Alasan sebagian orang mengajak gamers untuk tidak membeli game Hogwarts Legacy adalah karena J.K. Rowling, penulis dari novel Harry Potter, dianggap transfobik. Memang, terkadang, Rowling membuat kicauan yang antagonistik pada orang-orang transgender. Alasan lain mengapa Rowling dianggap transfobik adalah karena dia menggunakan nama Robert Galbraith sebagai nama samaran.
Galbraith adalah psikiater asal Amerika serikat yang percaya bahwa penyakit mental disebabkan oleh masalah fisik. Dia dikenal karena pernah melakukan eksperimen dengan memberikan stimulasi listrik ke otak pasien. Dia juga pernah memasang elektroda Deep Brain Stimulation (DBS) ke otak pasien. Biasanya, DBS dilakukan untuk mengatasi penyakit seperti Parkinson. Jumlah pasien Galbraith yang pernah mendapatkan “metode pengobatan” itu mencapai lebih dari 54 pasien. Pada 1972, dia mengklaim bahwa dia bisa mengubah seksualitas seseorang, dari homoseksual menjadi heteroseksual. Namun, sekarang, apa yang Galbraith merupakan kontroversi. Karena, seksualitas seseorang dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diubah.
Kembali ke J.K. Rowling dan Harry Potter. Terlepas dari perilaku Rowling yang terlihat transfobik, tidak bisa dipungkiri, ratusan juta orang membaca seri Harry Potter. Buktinya, total penjualan seri Harry Potter di dunia mencapai lebih dari 500 juta unit. Tak hanya itu, Harry Potter juga memiliki fandom terbesar kedua setelah boyband asal Korea Selatan, BTS. Semua hal ini menunjukkan, banyak orang yang memang mencintai franchise Harry Potter.
Pertanyaannya, apakah fans Harry Potter itu salah, karena mereka menyukai karya dari seseorang yang dianggap bermasalah? Bisakah sebuah karya seni — dan game adalah karya seni — berdiri secara mandiri, terlepas dari bayang-bayang perilaku sang kreator?
Developer Game yang Punya Budaya Bermasalah
J.K. Rowling bukan satu-satunya penulis ternama yang dianggap punya perilaku bermasalah. Ada banyak penulis besar lain yang juga mendapatkan label yang sama. Sebut saja, HP Lovecraft yang dikenal sebagai rasis atau Ernest Hemingway yang memiliki perilaku self-destructive dan memperlakukan semua orang di sekitarnya dengan tidak baik.
Dan, penulis bukan satu-satunya seniman yang bisa memiliki perilaku bermasalah. Di bidang seni lain pun, ada kreator yang memang bermasalah. Contohnya, di industri musik, ada Chris Brown, yang pernah melakukan kekerasan fisik pada Rihanna ketika penyanyi perempuan itu masih menjadi kekasihnnya. Sementara di industri film, ada Harvey Weinsten, yang dituduh telah memerkosa atau melecehkan puluhan perempuan. Sayangnya, industri game pun tidak bebas dari individu-individu bermasalah.

Activision Blizzard adalah salah satu perusahaan game yang memiliki budaya bermasalah. Pada pertengahan 2021, perusahaan itu dituntut oleh Departemen Ketenagakerjaan California atas tuduhan diskriminasi dan pelecehan seksual di tempat kerja. Diskriminasi serta pelecehan tampaknya merupakan masalah yang sudah mengakar di perusahaan. Buktinya, per Januari 2022, Activision Blizzard dikabarkan telah memecat lebih dari 35 pekerja dan mendisiplinkan hampir 40 orang yang memiliki andil dalam budaya diskriminasi dan pelecehan. Dengan itu, Activision Blizzard menunjukkan bahwa mereka ingin memperbaiki budaya perusahaan.
Walau Activision Blizzard punya budaya kerja yang bermasalah, tak bisa dipungkiri, mereka adalah salah satu perusahaan game terbesar di dunia. Mereka telah meluncurkan banyak franchise game populer, mulai dari Call of Duty, Diablo, Overwatch, StarCraft, World of Warcraft, sampai Candy Crush. Setiap tahun, Activision Blizzard bahkan menggelar BlizzCon, acara yang menjadi ajang promosi bagi perusahaan dan wadah bagi fans untuk bertemu. Dan di tengah skandal sekali pun, Activision Blizzard masih mendapatkan tawaran akuisisi. Tidak tanggung-tanggung, Microsoft rela mengeluarkan hampir US$70 miliar untuk bisa mendapatkan Activision Blizzard. Hal ini menunjukkan bahwa walau punya budaya bermasalah, Activision Blizzard tetap dianggap sebagai perusahaan game besar.
Selain Activision Blizzard, perusahaan game besar lain yang pernah terkena skandal adalah Riot Games, kreator di balik League of Legends, Wild Rift, dan VALORANT. Tak terbatas ke game, Riot juga membawa cerita League of Legends ke media lain, termasuk komik, musik, dan animasi. Seri animasi dari League of Legends, Arcane, bahkan berhasil menjadi Best TV Show di 2021. Arcane juga merupakan seri orisinal Netflix dengan rating tertinggi.
Serupa dengan Activision Blizzard, Riot juga terkena skandal terkait diskriminasi di tempat kerja. Pada 2018, Kotaku membuat artikel hasil wawancara dengan pekerja dan mantan pekerja Riot tentang budaya perusahaan. Salah satu narasumber Kotaku menceritakan, pekerja perempuan di Riot biasanya mendapatkan perlakuan yang tidak adil.
Contoh diskriminasi yang terjadi di Riot antara lain, pegawai perempuan tidak bisa memegang jabatan sebagai pemimpin di perusahaan dan ide yang dilontarkan oleh pekerja perempuan cenderung diacuhkan. Sebagian pekerja Riot pun mengeluhkan pelecehan seksual dari bos atau kolega mereka. Baik pegawai perempuan maupun laki-laki mengaku, mereka pernah mendapatkan gambar dari alat kelamin bos atau kolega mereka alias unsolicited dick pics.
Ubisoft menjadi contoh lain dari perusahaan game besar yang bermasalah. Pada pertengahan 2020, mereka dituduh karena membiarkan budaya kerja yang toxic. Ketika itu, Ubisoft bahkan sempat dituntut ke pengadilan oleh Informatique Jeu Vidéo, serikat yang berisi pekerja di industri game. Sejak saat itu, Ubisoft mengatakan bahwa mereka akan mengubah budaya perusahaan. Meskipun begitu, satu tahun kemudian, pada 2021, pegawai Ubisoft mengatakan bahwa tidak banyak perubahan yang terjadi. Misalnya, Florent Castelnérac, kepala dari Nadeo, salah satu studio milik Ubisoft, tetap masih bekerja seperti biasa. Padahal, dia dituduh memaksa pekerja untuk mengambil lembur dan memiliki gaya bicara yang terkadang, membuat anak buahnya terintimidasi.

Contoh terakhir perusahaan game besar bermasalah yang akan saya berikan adalah Sony Interactive Entertainment. Pada awal Maret 2022, SIE dituduh memiliki budaya seksis. Skandal ini dimulai pada November 2021, ketika Emma Majo, mantan security analyst, menuntut Sony atas tuduhan diskriminasi gender dan pemecatan tidak adil. Saat itu, Sony mengajukan dokumen ke pengadilan untuk mengacuhkan tuntutan Majo karena kurangnya bukti spesifik akan diskriminasi di perusahaan.
Namun, pada Maret 2022, pengacara Majo memberikan bukti baru ke pengadilan, berupa pernyataan dari tujuh mentan pegawai dan satu pekerja PlayStation tentang masalah seksisme di perusahaan. Menurut pernyataan tertulis dari delapan perempaun tersebut, bentuk seksisme di SIE beragam, mulai dari mengacuhkan ide dari pegawai perempuan, pelecehan seksual, sampai sulitnya pekerja perempuan mendapatkan promosi.
Dari contoh di atas, bisa disimpulkan bahwa perusahaan game besar pun tidak bebas dari budaya kerja yang bermasalah. Dan budaya toxic di tempat kerja tidak menghentikan Activision Blizzard, Riot Games, atau Ubisoft untuk membuat game-game berkualitas. Dalam kasus Sony, mereka tidak hanya membuat game, tapi juga konsol game. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh gamers ketika perusahaan game yang membuat game favorit mereka ternyata bermasalah?
Tentu saja, gamers bisa mengacuhkan masalah tersebut dan terus memainkan game favorit mereka. Business as usual. Namun, jika gamers tetap membeli game atau konsol dari perusahaan-perusahaan yang bermasalah, hal itu sama saja seperti mengirimkan pesan bahwa mereka tidak peduli dengan bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan, selama mereka tetap membuat game dan konsol yang bagus.
Opsi lain yang gamers bisa ambil adalah berhenti membeli atau memainkan game-game yang dirilis oleh perusahaan bermasalah. Hanya saja, jika gamers mengambil pilihan ini, ada berapa banyak game yang harus dihindari? Dan dalam kasus Sony, apakah gamers seharusnya tidak membeli konsol PlayStation atau tidak lagi memainkan konsol tersebut?
Memisahkan Karya Seni dari Sang Seniman
Dalam dunia literasi, ada metode untuk menganalisa karya seni yang disebut New Criticism. Muncul di era awal abad 20, paska Perang Dunia I, metode New Criticism fokus pada nilai intrinsik dari sebuah karya seni, tanpa mempedulikan kapan seni itu dibuat atau sudut pandang sang kreator.
Metode New Criticism muncul dengan tujuan untuk membuat studi/kritik literasi menjadi studi yang lebih ilmiah. Pasalnya, pada awal abad ke-20, ilmu studi yang diagung-agungkan memang ilmu sains. Mengingat metode New Criticism menganalisa karya seni secara mandiri, maka seseorang bisa menganalisa — atau menikmati — sebuah karya tanpa harus memikirkan kepercayaan dan persepsi sang kreator.
“New Criticism mencoba untuk mengubah analisa literasi menjadi sains,” kata Clare Hayes-Brady, dosen literasi Amerika di University College Dublin, lapor Vox. “Tidak lama sebelum kemunculan New Criticism, kritik literasi baru saja mulai diakui sebagai disiplin ilmu yang pantas untuk dipelajari. Dan salah satu alasan mengapa kritik literasi harus dibuat menjadi ilmiah adalah agar ilmu itu terlihat valid.”
Dengan menjadikan ilmu analisa literasi sebagai studi ilmiah, maka para kritikus literasi tidak lagi perlu mencoba memahami pemikiran sang penulis untuk mengerti apa yang dia coba sampaikan melalui tulisannya. Dengan begitu, sebuah karya tulis bisa berdiri mandiri, tanpa pengaruh dari sang penulis. Dalam kasus ketika sebuah karya tulis hanya bisa dianalisa dengan mempertimbangkan latar belakang dan sudut pandang sang penulis, tulisan tersebut akan dianggap sebagai karya yang buruk.
Pada 1923, penulis puisi dan kritikus literasi, T.S. Eliot berkata, “I have assumed as axiomatic that a creation, a work of art, is autonomous.”
Daniel Swift, dosen senior jurusan Bahasa Inggris di New College of the Humanities London, mencoba untuk menjelaskan pendapat Eliot tersebut. Swift mengatakan, Eliot percaya, puisi yang ideal adalah puisi yang tidak memiliki karakteristik sang penulis. Senada dengan itu, cara terbaik bagi pembaca untuk memahami puisi adalah dengan menganalisa puisi itu sendiri, tanpa harus menghubungkan apa yang tertulis dalam puisi dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sang penulis.
Mengingat metode New Criticism hanya mengharuskan pembaca untuk menganalisa sebuah tulisan, metode itu sangat efektif untuk dipelajari dalam pendidikan formal, seperti di dalam kelas. Karena, dengan metode New Criticism, murid tidak lagi perlu mencari sumber sekunder — seperti kehidupan sang penulis — untuk memahami tentang sebuah karya tulis.
Pada pertengahan abad ke-20, muncul metode analisa literasi baru, menggantikan New Criticism, yaitu Postmodernism. Menurut Vox, metode Postmodernism juga berusaha untuk memisahkan karya seni dari persepsi sang kreator. Hanya saja, Postmodernism punya alasan yang berbeda untuk tidak mengaitkan sebuah tulisan dengan sang penulis. Dalam Postmodernism, alasan yang paling populer untuk menganalisa karya tulis secara mandiri adalah: “The author is dead“.
Alasan “kematian sang penulis” diperkenalkan oleh Roland Barthes pada 1967. Ketika itu, Barthes mengatakan, seorang penulis tidak menciptakan interpretasi dari sebuah tulisan, tapi pembaca dari tulisan itulah yang bisa memberikan makna pada sebuah karya tulis. Artinya, setiap pembaca membaca tulisan baru, dia seolah-olah memberikan makna baru pada karya tersebut dengan memberikan interpretasi sesuai pemikiran mereka. Dan sang penulis tidak punya kendali atas interpretasi para pembaca.

Tentang argumen Barthes, Hayes-Brady menjelaskan, “Sebuah tulisan tidak punya arti yang spesifik atau kebenaran spesifik yang harus dipahami. Sebuah tulisan dan pembacalah yang punya tugas untuk memberikan arti dari sebuah karya.” Menggunakan metode Postmodernism, seorang pembaca bisa menganggap penulis sudah dan tiada. Dengan itu, dia akan punya kebebasan untuk menerjemahkan atau menikmati karya sang kreator, tanpa mempedulikan kehidupan pribadi sang seniman, yang mungkin bermasalah.
Kritikus budaya New Republic, Josephine Livingstone menganggap, jika pembaca peduli dengan persepsi penulis dan menggantungkan interpretasi mereka pada sudut pandang penulis, hal ini justru menjadikan sang penulis sebagai “author-god“. Karena, pembaca seolah-olah memberikan kuasa pada sang penulis untuk mendikte bagaimana dia memahami sebuah karya. Dan ketika seorang seniman menjadi “author-god“, maka dia seolah-olah punya kuasa dan dapat melakukan apapun yang dia mau, termasuk memperlakukan orang lain dengan semena-mena.
Livingstone menjadikan film-film buatan Woody Allen dan Roman Polanski sebagai contoh. Allen dituduh melakukan pelecehan seksual pada anak perempuan angkatnya ketika dia masih berumur tujuh tahun, sementara Polansi dituduh telah melakukan pemerkosaan.
“Bagi saya, film-film buatan Allen dan Polansi adalah sebuah berkah, baik untuk saya sendiri maupun untuk budaya, bahkan ketika film itu memiliki kualitas buruk,” katanya. “Saya tidak ingin Allen dan Polanski punya kuasa atas karya yang mereka buat. Jika mereka tidak mendikte interpretasi saya akan film yang mereka buat, mereka tidak akan punya kuasa apapun di industri film. Justru, penontonlah yang akan memegang kekuasaan itu.”
Untuk tidak memberikan kuasa pada seorang penulis atau seniman, seseorang juga bisa fokus pada kontribusi yang diberikan oleh pihak lain dalam membuat sebuah karya seni. Sebagai contoh, dalam kasus Hogwarts Legacy, daripada fokus pada kontribusi J.K. Rowling sebagai pencipta dari franchise Harry Potter, gamers bisa fokus pada peran Avalanche Software sebagai developer dari game tersebut. Dengan menerapkan metode New Criticism atau Postmodernism, maka seharusnya, gamers bisa menilai Hogwarts Legacy sebagai karya mandiri, lepas dari bayang-bayang Rowling sebagai kreator Harry Potter.
Namun, tetap saja, sekelompok orang percaya, membeli atau memainkan Hogwarts Legacy sama artinya dengan mendukung Rowling. Karena, Rowling mendapatkan royalti dari game tersebut. Selain itu, diskusi tentang Hogwarts Legacy justru memberi kesempatan para Rowling untuk menjadi lebih dikenal. Dan hal ini akan memperluas audiens Rowling untuk menyebarkan opininya yang transfobik. Tak hanya itu, mengingat Rowling merupakan seorang tokoh, opininya bisa digunakan sebagai justifikasi atau validasi argumen dari orang-orang yang juga punya pemikiran transfobik.
Dan, di sinilah peran cancel culture.
Cancel Culture: The Good, The Bad, and The Toxic
Media sosial menjadi panggung baru bagi selebritas dan tokoh masyarakat. Fans tidak lagi hanya melihat aktor di dalam film, musisi di kala konser, atau atlet di pertandingan olahraga, mereka kini juga bisa melihat kehidupan sehari-hari para aktor, musisi, atlet, dan selebritas lain melalui media sosial. Di satu sisi, hal ini membuat para fans merasa lebih dekat dengan tokoh kesayangan mereka. Di sisi lain, media sosial juga bisa digunakan untuk meng-“cancel” tokoh masyarakat yang dianggap bersalah.
Sebagai contoh, jika seorang aktor memberikan komentar rasis dalam wawancara, dia bisa saja diserang melalui media sosial. Tak hanya oleh netizen, aktor itu pun bisa dicecar oleh fans-nya sendiri. Dan semua tokoh masyrakat punya kesempatan untuk di-cancel jika mereka berbuat salah. Karena itu, sekarang, muncul budaya yang disebut “cancel culture.”
Menurut situs Vox, penggunaan kata “cancelling” muncul pada 1991 di film New Jack City. Pada 2010, rapper Lil Wayne menggunakan kata “cancel” dalam lirik lagu “I’m Single”. Sementara itu, penggunaan kata “cancel” baru mulai marak digunakan di media sosial pada 2014, setelah kata itu digunakan dalam episode Love & Hip-Hop: New York. Tak lama kemudian, kata cancel sering digunakan oleh orang-orang berkulit hitam di Twitter saat mereka tidak setuju dengan argumen pengguna lain.

Selain untuk membantah argumen, pada awalnya, kata cancel sering digunakan dalam senda-gurau atau olok-olok. Namun, kemudian, kata cancel juga sering dikaitkan dengan boikot, salah satu bentuk protes oleh masyarakat. Metode boikot sendiri mulai digunakan di Irlandia pada 1880-an. Dalam gerakan hak sipil di Amerika Serikat, boikot menjadi alat sosial-politik bagi masyarakat Amerika keturunan Afrika.
“Jika Anda tidak punya kuasa politik untuk menghentikan suatu kegiatan atau mengubah keadaan, satu-satunya hal yang bisa Anda lakukan adalah menolak untuk berpartisipasi dalam kegiatan itu,” kata Anne Charity Hudley, North Hall Endowed Chair di Linguistics of African Americam University of California, dikutip dari University of Central Florida. “Cancelling adalah pengakuan bahwa Anda tidak punya kuasa untuk mengubah ketidakadilan struktural di dunia. Anda bahkan tidak punya kemampuan untuk mengubah sentimen publik. Tapi, sebagai seorang individu, Anda tetap memiliki kuasa yang sangat besar.”
Keberadaan internet memudahkan masyarakat untuk menyebarkan informasi, yang berarti, meng-cancel tokoh masyarakat pun menjadi lebih mudah. Selain itu, internet juga bisa memberikan tempat bagi orang-orang dari kaum minoritas — yang biasanya juga menjadi korban dari diskriminasi — untuk menyuarakan pengalaman dan opini mereka. Karena, terkadang, golongan minoritas tidak punya tempat atau tidak diberikan kesempatan untuk bersuara di dunia nyata. Bagi kaum mayoritas, internet bisa membantu mereka untuk memahami sudut pandang kelompok minoritas dan mendukung mereka.
Ini mungkin terdengar dramatis, tapi, internet bisa digunakan oleh seseorang yang mendapat perlakuan semena-mena dari orang berkuasa untuk menuntut keadilan. Jika Anda aktif menggunakan media sosial, Anda pasti pernah mendengar berita yang bercerita tentang bagaimana sebuah kasus baru ditanggapi dengan serius ketika kasus tersebut viral di media sosial. Saya rasa, hal itu bisa menjadi contoh tentang bagaimana orang-orang tanpa kuasa bisa mencari bantuan dari masyarakat untuk melawan penguasa yang menindasnya.
Salah satu contoh bagaimana cancelling bisa menjatuhkan orang yang berkuasa adalah kasus Harvey Weinsten. Di Hollywood, Weinstein tidak hanya dikenal sebagai produser, dia juga mendirikan perusahaan entertainment, Miramax, bersama saudaranya, Bob Weinstein. Miramax berhasil membuat berbagai film indie sukses, seperti Sex, Lies, and Videotapes, The Crying Game, Pulp Fiction, dan Shakespeare in Love.

Shakespeare in Love bahkan pernah memenangkan Oscars dan Weinstein merupakan produser dari film itu. Tak hanya Oscars, dia juga pernah memenangkan tujuh Tony Awards berkat berbagai musicals yang dia buat. Setelah meninggalkan Miramax, Weinstein dan Bob mendirikan The Weinstein Company (TWC). Bersama Bob, Weinstein menjabat sebagai co-chairman di perusahaan itu dalam periode 2005 sampai 2017.
Pada Oktober 2017, Weinstein diberitakan dibawa ke pengadilan atas tuduhan pemerkosaan dan pelecehan seksual. Lebih dari 80 perempuan di industri perfilman menuduh Weinstein pernah melakukan pelecehan seksual atau pemerkosaan. Tentu saja, Weinstein membantah tuduhan itu. Namun, dia tetap dipecat dari The Weinstein Company dan dikeluarkan dari Academy of Motion Picture Arts and Sciences serta beberapa asosiasi lain.
Setelah tuduhan pada Weinstein muncul di media, tagar #MeToo menjadi viral di media sosial. Gerakan itu memberikan momentum pada pengadilan Weinstein dan pada akhirnya, dia dikenakan hukuman penjara selama 23 tahun. Selain Weinstein, ada beberapa tokoh masyarakat lain yang terseret ke pengadilan setelah gerakan #MeToo viral.
Salah satunya, komedian Bill Cosby. Pada 2018, dia dituntut atas tuduhan telah membius dan memerkosa seorang perempuan pada 2004. Contoh lainnya, fotografer Prancis, Jean-Claude Arnault dipenjara pada 2018 karena memerkosa seorang perempuan di 2011. Dan terakhir, dokter dari tim gimnastik nasional Amerika Serikat, Larry Nassar. Dia mendapatkan hukuman penjara selama hingga 125 tahun pada 2018. Alasannya, karena dia melakukan pelecehan seksual ketika dia melakukan pemeriksaaan pada pasiennya. Ada lebih dari 260 perempuan dewasa dan remaja yang mengaku menjadi korban dari Nassar.

Tentu saja, media sosial tidak selalu digunakan untuk hal-hal baik. Terkadang, seseorang memanfaatkan media sosial untuk melakukan penipuan. Tidak sedikit orang-orang yang berusaha untuk menjadi viral dengan foto sedih palsu demi meminta belas kasihan netizen dan mendapatkan sumbangan.
Faktanya, gerakan #MeToo pun tidak melulu membawa dampak positif. Gerakan itu tidak hanya membuat masyarakat di Amerika Serikat sadar akan betapa rentannya perempuan akan pelecehan seksual, tapi juga membuat mereka khawatir, laki-laki akan menjadi korban tuduhan salah.
Berdasarkan data dari Pew, mayoritas responden mengaku, gerakan #MeToo membuat laki-laki cenderung takut atau bingung tentang bagaimana mereka harus bersikap ketika mereka menghadapi kolega atau teman perempuan. Sementara menurut polling oleh Morning Consult pada 2018, 57% orang dewasa di Amerika Serikat tidak hanya khawatir perempuan akan menjadi korban pelecehan seksual, tapi juga laki-laki akan dituduh sebagai pelaku pelecehan tanpa bukti alias tuduhan salah.
Dan ketakutan para laki-laki bahwa mereka akan dituduh secara sepihak sebagai pelaku pelecehan memang sudah menjadi nyata. Salah satu pria yang menjadi korban adalah Mike Tunison, menurut laporan Forbes. Awalnya, dia berkarir sebagai penulis freelance. Dia sempat menulis untuk The Washington Post dan buku yang dia tulis juga pernah diterbitkan oleh HarperCollins. Namun, setelah dia dituduh secara salah sebagai pelaku pelecehan, karirnya hancur dan dia tidak punya pilihan lain selain bekerja sebagai tukang bersih-bersih.
Karir Tunison hancur karena namanya dimasukkan ke dalam daftar “Sh-tty Media Men”, sebuah Google Doc yang berisi nama-nama laki-laki yang dianggap memiliki perilaku bermasalah. Nama dalam daftar itu dilaporkan oleh orang-orang secara anonim. Tunison sendiri dituduh telah menguntit, melakukan intimidasi fisik, dan melakukan harassment. Meskipun begitu, dia baru tahu bahwa namanya ada di daftar tersebut setelah kekasihnya memberitahunya.
“Saya rasa, daftar itu bukan satu-satunya hal yang menghancurkan karir saya. Tapi, daftar itu memang punya dampak yang sangat buruk ke karir saya,” kata Tunison pada Forbes. “Saya tidak lagi bisa menghubungi orang-orang yang bisa membantu karir saya karena daftar itu dijadikan senjata oleh para wartawan. Ada jurnalis dengan akun Twitter terverifikasi yang mengatakan, ‘saya tidak kenal dengan siapa pun yang masuk dalam daftar Sh-tty Media Men’.”
Tentang cancel culture, Mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama mendorong masyarakat untuk berhati-hati ketika mereka hendak memviralkan tuduhan akan seseorang. Dia membicarakan hal ini dalam Obama Foundation Summit pada 2019. Menurut Obama, cancel culture menyuburkan pemikiran sempit pada masyarakat. Dan cancel culture juga menelurkan konsep bahwa nilai dari seseorang bisa diketahui dari hal terburuk yang dia pernah lakukan. Jadi, ketika seseorang berbuat salah, maka semua hal baik yang sudah dia lakukan tidak lagi dianggap. Padahal, Obama mengatakan, menutut seseorang untuk menjadi sempurna tanpa cela adalah hal yang tidak realistis.
“Dunia adalah tempat yang kacau… Orang-orang yang mencoba untuk berbuat baik pun pernah berbuat salah,” kata Obama, dikutip dari Psychology Today. Sebagai contoh, Michael Jackson adalah musisi ternama, yang sempat menyandang gelar sebagai King of Pop. Tapi, dia juga pernah dituduh sebagai pedofil. Apakah hal itu berarti semua lagunya tidak boleh didengarkan? Contoh lainnya, di Amerika Serikat, orang-orang yang menjadi Bapak Bangsa juga pernah menjadi pemilik budak. Sementara di Indonesia, Presiden Pertama Soekarno dikenal sebagai playboy. Apakah hal itu berarti kita harus melupakan semua jasa tokoh itu dan meng-cancel mereka?
Salah satu masalah dari cancel culture adalah ia menghilangkan kesempatan untuk diskusi atau kesempatan pada orang yang bersalah untuk berubah. Sebagai contoh, James Gunn, sutradara dari Guardians of the Galaxy, pernah dipecat dari posisinya sebagai sutradara Guardians of the Galaxy 3 oleh Disney pada 2018. Alasannya, karena dia pernah membuat kicauan yang tidak sensitif pada 2009 dan 2010. Di 2018, sebagai jawaban dari masalah itu, Gunn mengatakan bahwa apa yang dia lakukan di 2009-2010 tidak lagi bisa menggambarkan dirinya yang sekarang. Meskipun begitu, dia tetap menerima konsekuensi dari kesalahannya.
Contoh di atas menunjukkan bagaimana cancel culture bisa begitu membabi buta. Seseorang tidak memberikan ruang sama sekali untuk berbuat salah. Karena, jika seseorang berbuat salah, maka hidupnya akan tamat. Dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri. Layaknya kata pepatah: karena nila setitik, rusak susu sebelanga.
Secara pribadi, saya merasa, aspek negatif lain dari cancel culture adalah membuat orang-orang untuk malas berpikir. Karena biasanya, pesan untuk meng-cancel seorang tokoh cenderung fokus pada emosi dan bukannya logika. Sebagai contoh, “Jika Anda tidak ikut memboikot J.K. Rowling, maka Anda berarti mendukungnya dan juga anti pada orang-orang transgender.”
Padahal, dunia itu tidak sesederhana itu, tidak hanya hitam dan putih. Seseorang bisa saja menyukai dunia Harry Potter tapi tetap memperlakukan orang-orang transgender dengan manusiawi. Masalahnya, ketika seseorang mencoba untuk mengajukan pendapat atau opsi baru, biasanya, dia justru akan dikeroyok, membuat diskusi mustahil untuk terjadi. Akhirnya, yang terjadi adalah mobokrasi: siapa pun yang memiliki massa paling banyak akan menjadi pemenang karena dia bisa meng-cancel musuhnya.
Terakhir, cancel culture bahkan bisa berubah menjadi toxic ketika proses meng-cancel seseorang melibatkan ancaman kriminal, doxing atau membocorkan informasi pribadi seseorang, atau bahkan mendorong korban untuk melukai diri sendiri atau bahkan bunuh diri. Misalnya, saya pernah melihat bagaimana kasus seorang pelecehan seksual verbal menjadi cukup viral di Twitter. Keesokan harinya, sang tertuduh dikabarkan telah bunuh diri. Saya tidak mendukung sang tertuduh. Tapi, saya juga merasa, dia tidak seharusnya di-bully sampai dia bunuh diri.
Penutup
Dalam Universal Hak Asasi tahun 1948 pasal 30, hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia. Jadi, setiap orang berhak untuk memiliki dan mengeluarkan pendapat, tidak peduli seberapa kontroversial pendapat tersebut. Namun, orang lain juga punya hak untuk menyampaikan opininya tentang pendapat orang lain. Dan hal inilah yang biasanya memulai debat.
Tapi, bagaimana ketika orang yang menyampaikan pendapat adalah penulis atau aktor atau atlet ternama? Orang-orang biasa tetap bisa melawan dengan mencari dukungan dari banyak orang. Sekarang, hal ini sering disebut dengan meng-cancel seseorang. Walau cancel culture bisa digunakan untuk menjatuhkan orang-orang yang punya kuasa, ia juga bisa disalahgunakan, khususnya ketika seseorang di-cancel tanpa alasanya yang jelas.
Pada akhirnya, saya merasa, semua orang bebas berpendapat. Tapi, dia juga harus siap menerima konsekuensi dari semua pendapatnya. Tentang apakah gamers boleh memainkan game-game yang dibuat oleh perusahaan bermasalah atau didasarkan pada franchise yang dibuat oleh bermasalah, saya kembalikan itu pada diri gamer masing-masing. Yang penting, menurut saya, seorang gamer bisa membuat informed decision. Jadi, saat dia membuat sebuah keputusan — untuk membeli atau memainkan sebuah game, misalnya — dia sudah memperhitungkan keputusannya tersebut/
Sumber header: Unsplash/Michael Dziedzic