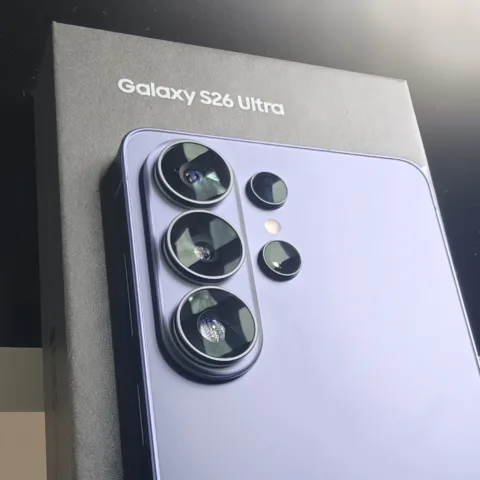Jumlah penonton esports terus naik dari tahun ke tahun. Pada 2023, Statista memperkirakan, jumlah audiens esports akan mencapai 646 juta orang, dengan 351 juta orang sebagai occasional viewers dan 295 juta sisanya sebagai esports enthusiasts. Banyaknya orang yang tertarik untuk menonton esports menjadi salah satu alasan mengapa semakin banyak merek — non-endemik sekalipun — yang tertarik untuk mendukung esports, menjadikan industri competitive gaming bernilai hingga hampir US$1 miliar.
Integritas kompetisi punya peran penting dalam memastikan agar pertandingan esports tetap diminati, Sayangnya, seiring dengan naiknya total hadiah yang ditawarkan dalam turnamen esports, semakin menggiurkan pula bagi para peserta untuk berbuat curang. Masalahnya, jika tidak ditangani, perbuatan curang bisa merusak ekosistem esports secara keseluruhan.
Definisi Kecurangan Dalam Olahraga
Dalam buku Fair Play in Sport, Sigmund Loland mendefinisikan kecurangan dalam olahraga sebagai “usaha untuk mengungguli lawan dengan melanggar peraturan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak”. Sementara itu, di jurnal berjudul Cheating in Contests, Ian Preston dan Stefan Szymanski membagi jenis kecurangan dalam olahraga tradisional ke dalam tiga kategori, yaitu menyabotase musuh, menggunakan doping, dan mengatur jalannya pertandingan alias match fixing.
Esports merupakan kompetisi olahraga dengan game sebagai media pertandingan. Dengan begitu, kita bisa mendefinisikan kecurangan dalam esports sama dengan kecurangan di olahraga tradisional. Dan memang, di dunia esports, menggunakan doping merupakan salah satu bentuk kecurangan yang pernah dilakukan oleh sebagian pemain profesional. Selain itu, juga ada atlet esports yang melakukan match fixing.

Kory “Semphis” Friesen, mantan pemain Counter-Strike: Global Offensive dari Cloud9 mengaku bahwa dia dan timnya pernah menggunakan adderall ketika bertanding dalam kompetisi pada 2015. Adderall sebenarnya adalah obat yang biasa diminum oleh pengidap Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Tujuannya adalah untuk membantu mereka berkonsentrasi. Sayangnya, obat ini terkadang disalahgunakan oleh para pemain profesional. Penggunaan adderall atau doping lain tidak hanya terjadi di skena esports CS:GO, tapi juga Overwatch. Timo “Taimou” Kettunen, mantan pemain Dallas Fuel, mengungkap, ada setidaknya 20 pemain di Overwatch League yang menggunakan adderall.
Maraknya penggunaan doping ini mendorong ESL untuk membuat peraturan terkait penggunaan doping. Mereka menetapkan, pemain yang tertangkap menggunakan doping akan dikenakan ban selama 1-2 tahun. Jika ESL tahu bahwa tim juara menggunakan doping, maka gelar juara dari tim itu akan dicabut. Tak hanya itu, mereka juga tidak akan mendapatkan hadiah uang. Sementara jika seorang pemain atau sebuah tim ketahuan menggunakan doping selama turnamen berlangsung, maka mereka akan didiskualifikasi.
Bentuk kecurangan lain yang bisa terjadi di dunia esports adalah match fixing, yaitu ketika sebuah tim bermain untuk mendapatkan hasil yang sudah ditentukan. Misalnya, sengaja mengalah pada musuh. Salah satu contoh kasus match fixing terjadi di Victoria, Australia. Pada April 2020, polisi berhasil menangkap enam pemain CS:GO yang melakukan match fixing. Mereka sengaja kalah dari musuh dalam setidaknya lima pertandingan di turnamen esports. Mereka melakukan itu karena sudah memasang taruhan bahwa tim mereka akan kalah. Ketika itu, para pelaku dihadapkan pada hukuman hingga 10 tahun penjara.
Esports Integrity Commission (ESIC) bekerja sama dengan Polisi Victoria untuk menangkap para pelaku. Meskipun para pelaku berhasil tertangkap, kepada Bloomberg, Stephen Hanna, Director of Global Strategy and Partnerships, ESIC berkata, “Tidak mungkin untuk menghapuskan judi ilegal dan match fixing sepenuhnya. Tugas kita hanyalah untuk meminimalisir hal itu.”
Kecurangan lain yang bisa dilakukan oleh pemain profesional adalah menggunakan kode cheat. Memang, di industri game, keberadaan kode cheat bukanlah hal yang aneh. Namun, ketika seorang pemain profesional menggunakan kode cheat untuk unggul atau bahkan untuk bisa menang, maka hal ini akan merusak integritas pertandingan esports. Jika dibiarkan, hal itu dapat berujung pada rusaknya kepercayaan fans.
Ada berbagai kode cheat yang bisa digunakan oleh para atlet esports. Misalnya, di game FPS seperti CS:GO, ada aim bot, yang memudahkan pemain untuk membidik musuh. Kode cheat lain yang biasa digunakan adalah wall hack, yang membuat pemain bisa melihat menembus tembok, serta speed hack, yang akan memungkinkan pemain untuk bergerak dengan jauh lebih cepat.
Salah satu atlet esports yang pernah ketahuan menggunakan aim bot adalah Nikhil “forsaken” Kumawat. Dia merupakan pemain CS:GO yang sempat menjadi anggota OpTic India. Dia tertangkap basah menggunakan aim bot di babak final eXTREMESLAND 2018 Asia. Lucunya, ketika tertangkap, dia tidak langsung mengaku dan justru berusaha untuk menghilangkan bukti dengan menghapus aim bot yang terpasang di PC-nya, yang dia namai Word.exe. Penyelidikan lebih lanjut membuktikan bahwa dia juga menggunakan aim bot saat dia bertanding di ESL India Premiership 2018 Fall, lapor Essentially Sports.
Selain kode cheat, ada cara lain bagi atlet esports untuk berbuat curang di turnamen esports. Kecurangan paling simpel yang bisa pemain profesional lakukan adalah dengan melihat layar yang dihadapkan ke para penonton untuk melihat posisi lawan. Hal ini pernah dilakukan oleh Azubu Frost di League of Legends World Championship 2012. Mereka ketahuan berbuat curang karena mengalihkan pandangan dari monitor PC mereka sendiri — sesuatu yang sangat jarang dilakukan oleh para pemain League of Legends. Pada akhirnya, Azubu Frost mendapatkan denda sebesar US$30 ribu, walau mereka tidak didiskualifikasi dari kompetisi itu.
Kecurangan yang Abu-Abu
Di olahraga tradisional, seperti sepak bola misalnya, para atlet tidak akan mendadak mendapatkan kemampuan spesial karena menggunakan peralatan khusus. Pierre-Emerick Aubameyang masuk dalam daftar 10 pesepak bola tercepat karena dia sanggup berlari dengan kecepatan 35,55 km per jam. Tentu saja, jenis sepatu yang dia gunakan dan tempatnya berlari akan memengaruhi kecepatan berlarinya. Namun, Anda tidak akan bisa mendadak berlari sekencang Aubameyang hanya karena mengenakan sepatu yang sama.
Lain halnya dengan esports. Dalam pertandingan esports, kualitas perangkat dan alat yang digunakan sangat memengaruhi performa pemain. Misalnya, jika dalam pertandingan El Clasico Mobile Legends antara RRQ melawan EVOS Esports, salah satu tim memiliki koneksi internet yang lebih baik. Tentunya, tim itu akan diuntungkan. Pasalnya, refleks seorang pemain untuk bereaksi akan menjadi sia-sia jika terjadi lag dalam game.

Contoh lainnya, ketika memainkan game seperti PUBG Mobile, Anda akan mendapatkan field of view yang lebih luas saat menggunakan tablet atau iPad. Hal ini akan memberikan Anda keunggulan jika dibandingkan pemain yang bermain di smartphone. Hal ini memunculkan pertanyaan: pemain yang menggunakan perangkat yang lebih baik, apakah mereka bisa dianggap curang? Di sinilah pentingnya standarisasi.
Dengan memastikan semua peserta kompetisi menggunakan perangkat yang sama, hal ini akan menjamin bahwa pertandingan akan mengadu kemampuan para peserta dan bukannya beradu perangkat siapa yang lebih baik. Karena itulah, dalam beberapa turnamen esports offline, penyelenggara menyediakan perangkat yang digunakan oleh peserta. Selain agar peserta tidak memasang kode cheat, alasan lainnya adalah agar tidak ada peserta yang diuntungkan karena perangkat yang dia gunakan.
Dalam buku peraturan kompetisi resmi PUBG Mobile versi 2019, terdapat peraturan yang mengatur tentang perangkat yang boleh digunakan oleh para pemain. Ketika itu, Proxima — sebagai pemegang hak distribusi game PUBG Mobile di dunia kecuali di Jepang dan Korea Selatan — menentukan bahwa para peserta hanya bisa menggunakan smartphone berbasis Android atau iOS. Penggunaan tablet atau PC dilarang. Aturan ini kemudian dihilangkan pada buku peraturan kompetisi resmi versi 2020.
Meskipun begitu, keputusan Proxima untuk menjadikan smartphone Android atau iPhone sebagai perangkat standar kompetisi menarik untuk dibahas. Alasannya, tablet memungkinkan para pemain untuk melihat sudut pandang yang lebih luas. Dengan begitu, pertandingan bisa menjadi semakin menarik. Pertanyaannya, kenapa justru smartphone yang dijadikan perangkat standar?
Semakin banyak orang yang memainkan sebuah game, semakin besar pula keuntungan yang didapatkan oleh publisher. Jadi, publisher punya kepentingan untuk membuat kompetisi esports tidak hanya menarik untuk ditonton, tapi juga terasa relatable bagi para pemain. Tujuannya adalah agar semakin banyak penonton yang terdorong untuk memainkan game yang diadu. Dan kompetisi esports terbukti efektif menjual harapan demi meningkatkan jumlah pemain. Hal ini telah dibuktikan oleh Ubisoft.

Lalu, apa hubungannya dengan menjadikan smartphone sebagai perangkat standar dalam kompetisi? Harga smartphone lebih murah dari tablet, apalagi iPad. Jadi, tidak aneh jika jumlah pengguna smartphone jauh lebih banyak dari jumlah pengguna tablet. Dengan menjadikan smartphone sebagai perangkat standar kompetisi, publisher akan bisa merangkul lebih banyak fanbase. Dan pada akhirnya, hal ini akan membuat pemasukan publisher naik.
Saat ini, memang ada publisher yang langsung turun tangan dalam mengembangkan ekosistem esports dari game buatan mereka. Sebut saja Riot Games, Moonton, dan Garena. Namun, juga ada perusahaan yang menjadi penyelenggara turnamen esports walau mereka bukanlah publisher. Contohnya adalah ESL. Biasanya, para penyelenggara turnamen ini punya metode sendiri untuk mengatasi kecurangan. ESL mengaku bahwa mereka punya software khusus. Penyelenggara turnamem esports lainnya, FACEIT, juga mengembangkan software anti-cheat mereka sendiri.
Kepada The Esports Observer, Marcel Menge, SVP Play & Platforms, ESL mengungkap bahwa sekitar seperlima sampai seperempat dari budget teknologi ESL digunakan untuk mengembangkan teknologi anti-cheat. Salah satu program anti-cheat yang ESL gunakan adalah ESL Wire Anti-Cheat, yang mereka mulai gunakan pada 2010. Menge mengakui, software anti-cheat yang digunakan oleh ESL memang lebih intrusif daripada sistem anti-cheat dari publisher, seperti Valve. Alasannya, karena fokus dari ESL dan Valve memang berbeda. Sebagai publisher, fokus Valve adalah untuk mencegah para pemain berbuat curang. Sementara ESL lebih fokus untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan pemain.
ESL sangat serius dalam mengembangkan teknologi anti-cheat mereka. Mereka bahkan mempekerjakan orang secara diam-diam untuk memantau forum cheating online. Tugas mereka adalah untuk mendapatkan informasi tentang software cheat terbaru dan melakukan reverse-engineer dari software cheat tersebut.
“Kami punya cheating lab,” kata Menge pada The Esports Observer. “Laboratorium ini punya jaringan internet sendiri. Jadi, alamat IP di lab itu berbeda dari alamat IP kantor kami. Hal seperti ini diperlukan untuk mengalahkan para developer software cheat, karena pasar ini memang pasar yang besar.” Kode cheat standar biasanya dihargai sekitar US$20 sampai US$35. Sementara kode cheat khusus bisa dihargai hingga ribuan dollar.
Selain Publisher, Siapa yang Berhak Menegakkan Hukum di Esports?
Saat ini, ada dua federasi besar yang menaungi esports di dunia, yaitu International eSports Federation (IESF) dan Global Esports Federation (GEF). Bermarkas di Busan, Korea Selatan, IESF merupakan badan nirlaba yang didirikan pada Agustus 2008. Menurut IESF Statutes, salah satu tujuan IESF adalah untuk meningkatkan kualitas industri esports dan mempromosikan nilai-nilai yang terkandung di esports, seperti edukasi, budaya, dan persatuan. Selain itu, mereka juga ingin agar anak muda belajar tentang etika dan semangat fair play dari esports.

Salah satu bentuk kecurangan yang menjadi perhatian IESF adalah penggunaan doping. Terkait hal ini, IESF mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh IOC, Sport Accord, WADA, dan badan lain yang relevan. Sementara daftar substansi yang tidak boleh digunakan dalam kompetisi IESF ditentukan oleh Komite Kompetisi, yang ditunjuk oleh para Dewan IESF. Jika terjadi pertikaian, maka Komite Kompetisi dan Dewan IESF akan bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, jika kedua pihak itu ternyata tidak dapat menyelesaikan masalah yang muncul, maka masalah itu akan dibawa ke Court of Arbitration for Sport (CAS), yang terletak di Switzerland.
Sementara itu, GEF didirikan pada 2019 dengan dukungan Tencent. GEF bermarkas di Singapura. Dalam situs resminya, GEF mengungkap bahwa salah satu tujuan mereka adalah menjaga integritas esports dan GEF. Untuk itu, mereka membuat kode etik dan menegakkan kode etik tersebut. Pihak yang melanggar kode etik dan peraturan yang telah ditetapkan oleh GEF akan dikenakan sangsi. Sangsi yang dikenakan oleh GEF beragam, mulai dari sekedar peringatan tertulis atau verbal, pencabutan gelar atau denda, diskualifikasi, skors, sampai pemecatan.
Untuk menentukan sangsi yang diberikan para pelaku, salah satu hal yang menjadi pertimbangan GEF adalah jenis pelanggaran yang dilakukan. Beberapa faktor lain yang GEF pertimbangkan sebelum menentukan sangsi untuk pelaku adalah apakah pelaku pernah melakukan pelanggaran sebelumnya, apakah pelaku mau bekerja sama saat GEF melakukan penyelidikan, tujuan pelaku, apakah pelaku merasa penyesalan, dan lain sebagainya.
Selain IESF dan GEF, esports juga punya ESIC. Badan yang didirikan pada 2016 itu bertujuan untuk melindungi integritas esports. Mereka melakukan itu dengan menyelidiki kasus kecurangan di dunia esports dan memberikan hukuman pada para pelaku. Beberapa kecurangan yang ditangani oleh ESIC adalah match fixing dan penggunaan doping. Sebelum ini, mereka telah membantu polisi Australia untuk menangkan enam pemain CS:GO yang melakukan match fixing.
Saat ini, ada 13 penyelenggara turnamen yang menjadi anggota ESIC, termasuk ESL, DreamHack, dan WePlay Esports. Anggota tertua ESIC bergabung sejak tahun 2017, sementara anggota terbaru badan tersebut bergabung pada tahun ini. Dalam situs resminya, ESIC menjelaskan, para anggota punya hak untuk menentukan bagaimana ESIC beroperasi.
Dalam wawancara dengan The Esports Observer, Ian Smith, Integrity Commissioner, ESIC mengungkap bahwa banyak perusahaan esports yang punya sumber daya pas-pasan. Perusahaan-perusahaan itu akan kesulitan untuk menangani kecurangan dilakukan para pemain. Memang, para penyelenggara turnamen esports bisa membuat software anti-cheat sendiri, seperti yang dilakukan oleh ESL. Namun, sebagai pihak ketiga, ESIC mampu membuka komunikasi dengan penyelenggara turnamen esports lain.
Di Indonesia, badan yang menaungi game dan esports juga ada lebih dari satu. Indonesia Esports Association (IESPA) adalah yang tertua, berdiri pada 2013. Sementara Asosiasi olahraga Video Game Indonesia (AVGI) dibentuk pada Juli 2019 dan Federasi Esports Indonesia (FEI) berdiri pada Oktober 2019. Organisasi yang terbaru adalah Pengurus Besar Esports (PB Esports), yang terbentuk pada Januari 2020.

Kemunculan lebih dari satu badan yang menaungi esports menimbulkan masalah tersendiri. Pasalnya, hal ini akan menimbulkan kontroversi dan membuat komunitas dan pelaku esports menjadi bingung: organisasi mana yang harus mereka patuhi? Bagaimana jika peraturan yang dibuat oleh satu organisasi bertentangan dengan peraturan dari organisasi lain? Kabar baiknya, para pelaku esports bisa belajar dari dunia tinju soal ini.
Sama seperti esports, tinju juga punya lebih dari satu badan internasional. Faktanya, ada empat organisasi tinju di dunia. Keempat badan itu antara lain World Boxing Association (WBA), World Boxing Council (WBC), International Boxing Federation (IBF), dan World Boxing Organizaation. Keempat organisasi itu juga punya gelar juara dunia/sabuk masing-masing. Hal itu berarti, ada 4 juara dunia untuk masing-masing 17 kelas tinju.
Menurut laporan MK Boxing, gelar juara dunia WBC merupakan gelar yang paling populer. Alasannya, gelar inilah yang biasanya diincar oleh para petinju. Sejauh ini, ada sejumlah petinju ternama telah memenangkan gelar juara WBC, seperti Muhammad Ali, Floyd Mayweather, dan Joe Calzaghe. Menariknya, walau keempat badan ini sama-sama menaungi olahraga tinju, mereka jarang bekerja sama. Alasannya klasik: uang. Setiap organisasi tinju akan mendapatkan uang ketika pertandingan untuk memperebutkan sabuk dari organisasi itu diperebutkan.
Dari tinju, para pelaku industri esports bisa belajar satu hal: beberapa organisasi yang menaungi olahraga yang sama bisa eksis dalam satu waktu selama memang uangnya masih bisa dibagi-bagi… Pelajaran ekstra yang bisa dipetik dari industri tinju adalah uang merupakan salah satu insentif untuk menciptakan badan yang menaungi olahraga tertentu. Dan karena esports kini tengah naik daun, tidak heran jika ada banyak pihak yang tertarik untuk membuat badan esports.
Kesimpulan
Liga Premier merupakan salah satu liga sepak bola domestik paling sukses di dunia. Salah satu alasannya adalah liga itu sangat kompetitif. Hasil pertandingan di Liga Premier tidak selalu bisa ditebak. Misalnya, walau di atas kertas Arsenal lebih unggul dari Aston Villa — Arsenal duduk di peringkat 8 pada musim lalu, sementara Aston Villa di peringkat 17 — tapi Aston villa tetap berhasil mengalahkan Arsenal 1-0 pada 5 Februari 2021 lalu. Hasil yang terkadang tidak terduga inilah yang membuat banyak orang senang menonton Liga Premier.
Selain persaingan yang ketat, integritas juga punya peran penting untuk menjamin sebuah kompetisi olahraga bisa terus hidup. Memang, siapa yang mau menonton pertandingan olahraga yang para pemainnnya berbuat curang? Tidak ada. Dan jika jumlah penonton turun, hal ini juga akan memberikan dampak langsung pada pemasukan para pelaku di dunia olahraga, termasuk tim dan pemain. Tanpa fans, penjualan merchandise dan tiket pertandingan langsung akan turun. Dan jika tidak ada orang yang mau menonton kompetisi olahraga, hanya masalah waktu saja sebelum para sponsor ikut pergi, seperti yang disebutkan oleh Genius Sports.
Saat ini, industri esports tengah berkembang pesat. Hal ini membuat banyak perusahaan — endemik atau non-endemik — tertarik untuk mendukung para pelaku esports. Jumlah penonton esports yang mencapai ratusan juta menjadi salah satu alasan mengapa banyak perusahaan yang mau menjadi sponsor di dunia esports. Masalahnya, jika tidak ada jaminan bahwa pertandingan esports bebas dari kecurangan, para penonton tentunya juga akan berpaling. Dan tanpa penonton, para sponsor juga akan kehilangan minat untuk mendukung industri esports.
Sumber header: Talk Esports