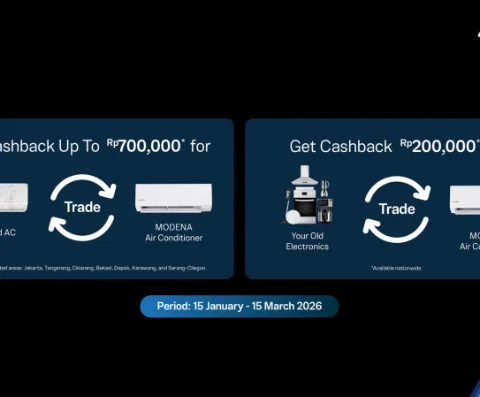Video game kompetitif telah berkembang sangat pesat, dari sekadar persaingan di game center menjadi industri bernilai jutaan dolar. Para pemain, yang kini sudah layak menyandang gelar “atlet”, menyandang reputasi serta popularitas layaknya selebritas. Esports membuat video game berubah bukan hanya hiburan lagi tapi juga menjadi mata pencaharian yang menjanjikan.
Begitu gemerlap dunia esports terlihat di permukaan. Tapi mungkin kita tidak sadar bahwa di balik semua itu ada harga yang harus dibayar. Ketika seseorang terjun menjadi atlet profesional, ia harus mencurahkan seluruh energinya, terkadang sampai harus mengorbankan banyak aspek kehidupan lain.
Stasiun berita CBS baru-baru ini merilis dokumenter singkat yang mengisahkan tentang perjuangan atlet esports dengan judul Esports: The Price of the Grind. Mereka mewawancara orang-orang dari berbagai elemen esports, termasuk di antaranya Doublelift (Yiliang Peng) yang merupakan atlet League of Legends di Team Liquid, SPACE (Indy Halpern) yang bermain di tim Overwatch Los Angeles Valiant, hingga Thresh (Dennis Fong) yang tercatat di Guinness World Record sebagai gamer profesional pertama di dunia.
https://www.youtube.com/watch?v=box4SFtGvA0
Risiko menjadi atlet esports
Para pegiat esports ini sepakat bahwa karier di dunia esports adalah karier yang berisiko. Ada berbagai hal yang dapat membuat profesi tersebut terasa sangat berat, bahkan bisa menghancurkan karier seseorang sewaktu-waktu. Berikut ini di antaranya.
Masalah kesehatan
Anda yang sering bermain MMORPG pasti mengenal istilah “grinding”, yaitu melakukan suatu kegiatan berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama untuk meningkatkan level karakter kita. Banyak atlet esports percaya bahwa untuk menjadi pemain yang baik, mereka pun harus melakukan grinding di dunia nyata. Seorang gamer profesional bisa menghabiskan waktu hingga 12 jam sehari hanya untuk bermain, berlatih, dan meningkatkan keahlian.
Pola hidup seperti ini pada akhirnya bisa berujung pada cedera, terutama cedera tangan. SPACE misalnya, berkata, “Bila saya bermain terlalu lama, saya akan merasa sakit (di pergelangan tangan) pada malam harinya.” Begitu pula dengan bagian tubuh lain seperti punggung atau pundak. Gamer profesional rawan terkena cedera otot, sindrom carpal tunnel, dan berbagai kondisi medis lainnya. Padahal SPACE baru berusia 18 tahun.
Stres dan burnout
Bermain game itu memang menyenangkan. Tapi ketika sudah menyandang gelar profesional, game tak lagi hanya hiburan melainkan juga profesi. Ada tuntutan yang harus dipenuhi, dan seorang pemain harus menghabiskan banyak waktu memainkan satu game saja hingga mahir. Ini bisa menimbulkan rasa bosan, bahkan burnout yang membuat atlet jadi kehilangan motivasi bermain.
“Dulu ketika saya bermain di SMP atau SMA, rasanya tidak terlalu stres karena saya tidak berkompetisi begitu keras. Tapi ketika saya memasuki esports, tingkat tekanannya jauh berbeda karena saya bermain melawan para profesional,” ujar SPACE. Isu stres ini menjadi masalah besar terutama ketika menjelang pertandingan besar. Atlet esports punya banyak penggemar, dan keinginan untuk tidak mengecewakan mereka adalah beban tambahan yang dapat membuat atlet susah tidur. Apalagi bila mereka bermain di tim yang mewakili kota atau negara tertentu.

Stigma negatif masyarakat
Saat ini esports memang sudah sangat populer, bahkan mungkin mendekati mainstream. Di negara seperti Amerika Serikat sudah banyak kampus-kampus yang menawarkan program pendidikan esports, begitu pula di Indonesia sudah mulai ada beberapa. Akan tetapi, mereka yang belum tenar sering kali masih dipandang sebelah mata. Mereka dianggap hanya buang waktu, atau dianggap hanya sekumpulan nerd yang tidak bisa bersosialisasi.
Padahal pada kenyataannya, kehidupan sebagai gamer profesional menuntut atlet untuk bisa bekerja dengan baik dalam tim, malah mungkin menjadi pemimpin di antara kawan-kawannya. Program pendidikan esports pun tidak hanya mengajarkan soal cara bermain, tapi juga cara komunikasi serta penyusunan strategi.
Sulit menjalani percintaan
Tim esports sering kali tinggal di satu rumah yang sama, baik itu sebagai asrama tetap ataupun bootcamp sementara. Selain itu mereka juga banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan. Sulit bagi atlet dengan pola hidup seperti ini untuk berkenalan dengan orang lain dan menjalin hubungan asmara. Mereka yang sudah memiliki kekasih pun, akan merasa teruji ketika salah satu pihak masuk ke dunia esports.
“Ketika Anda tinggal bersama dengan 6-7 lelaki lain, dan semuanya begitu serius berlatih, mana mungkin akan pergi bersantai selama akhir pekan? Saya rasa ada tekanan sosial seperti itu, bahkan meskipun tidak ada yang mengatakan atau membuat aturan tertulis,” kata Thresh.
Sebuah game bisa mati kapan saja
Jurnalis esports senior Richard Lewis memaparkan bahwa esports berbeda dengan olahraga biasa. “(Pemegang kekuatan terbesar) adalah para developer. Mereka yang membuat game, dan game itu adalah properti intelektual mereka. Tidak ada asosiasi pemain, tidak ada perserikatan… Tidak ada orang yang menjaga Anda,” jelasnya.
Tidak ada pemain sepak bola yang perlu takut bahwa tahun depan sepak bola akan punah. Begitu juga cabang-cabang olahraga lainnya. Mereka juga memiliki lembaga-lembaga yang memayungi seperti NFL, FIFA, atau NBA. Tapi hal ini beda dengan esports. Bayangkan bila Valve tiba-tiba memutuskan untuk menutup server Dota 2. Ke mana para atlet Dota 2 harus berpulang? Jangankan menutup server, menutup kompetisi Dota Pro Circuit saja sudah bisa membuat banyak orang kehilangan mata pencaharian. Wajar bila kemudian karier atlet esports sering berumur pendek.

Wujud dukungan yang dibutuhkan atlet esports
Atlet esports telah berkorban begitu banyak, dan hasilnya, mereka pun mendapat penghasilan serta ketenaran yang layak. “Saya selalu berkata bahwa ya, terkadang (esports) menyebalkan, karena semua masalah yang ada. Tapi pada akhirnya, semua itu sungguh setimpal, dan bagi banyak orang hidup saya adalah mimpi yang jadi kenyataan,” kata Doublelift.
Akan tetapi meski pengorbanannya “worth it”, bukan berarti masalah-masalah di atas lalu kita biarkan begitu saja. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak sekitar atlet untuk mendukung perjuangan mereka, yang pada akhirnya juga akan berdampak positif pada ekosistem esports keseluruhan.
Dukungan orang tua
Esports adalah sebuah karier. Profesi. Cita-cita. Sama seperti cita-cita lainnya, seorang anak tidak akan bisa mencapainya dengan maksimal apabila tidak mendapat restu orang tua. Sudah banyak legenda-legenda esports yang membuktikan bahwa dukungan orang tua sangat penting. Sumail dari tim Evil Geniuses misalnya, orang tuanya bahkan rela memboyong seluruh keluarga dari Pakistan ke Amerika agar sang anak dapat bermain Dota. Begitu pula dengan atlet-atlet lain, seperti misalnya JessNoLimit yang selalu berkata bahwa ia ingin membanggakan orang tua.
Salah satu orang tua itu adalah Kara Dang Vu, ibu dari pemuda bernama Conner Dang Vu yang sedang berusaha menjadi pemain Overwatch profesional. Ia sadar bahwa zaman sudah berubah, dan orang tua harus memahami perubahan tersebut. “Mungkin sudah waktunya bagi kita, sebagai generasi yang berbeda, untuk melihat dunia dari mata mereka,” ujarnya.

Dokter dan psikolog dalam tim
Kesehatan atlet sangat penting untuk diperhatikan, jadi tim esports sebaiknya memiliki dokter atau kru medis yang bertugas memantau kondisi para anggotanya. Akan tetapi kesehatan bukan hanya soal fisik, tapi juga soal mental.
Tim esports seperti Los Angeles Valiant memiliki psikolog tersendiri yang dapat membantu para pemain mengatasi stres. Metodenya bisa bermacam-macam, bahkan sebagian melibatkan aktivitas fisik juga. Olahraga memang telah lama dipercaya dapat meredam emosi negatif, karena dengan berolahraga, tubuh akan terangsang untuk memproduksi hormon yang bersifat sebagai antidepresan. Dengan penanganan seperti ini, diharapkan atlet dapat berlatih dengan lebih nyaman dan tidak sampai burnout.
Pendidikan atau beasiswa
Saat ini kita sedang berasa di “generasi pertama esports”. Ekosistem ini muncul dengan menjanjikan jumlah uang yang besar, dan masih terus berevolusi untuk menuju industri yang sustainable. Agar esports bisa menjadi sesuatu yang berkesinambungan layaknya olahraga konvensional, kita butuh regenerasi. Bukan hanya atlet tapi juga peran-peran lainnya. Esports adalah sebuah profesi, dan profesi tidak bisa dilakukan tanpa adanya keahlian sebagai bekal.
Karena itulah, munculnya pendidikan esports di SMA dan kampus-kampus merupakan langkah yang sangat baik. Saat ini kita masih meraba-raba. Tapi di generasi esports berikutnya, mereka akan menjalankan industri ini dengan ilmu serta pengalaman yang terakumulasi dari generasi sebelumnya. Saya pun yakin esports akan terus ada untuk waktu yang lama, tapi tidak ada yang bisa menebak bentuknya nanti seperti apa.

Catatan Tambahan: Sebuah pelajaran dari Daigo Umehara
Ada satu hal yang membuat saya merenung setelah menonton Esports: The Price of the Grind. Bila kita kerucutkan, sepertinya masalah utama esports saat ini ada pada sustainability. Semua pihak sedang berusaha menuju ke sana. Penyelenggara turnamen ingin agar kompetisi bisa lebih sustainable, atlet ingin terus bisa bermain dalam waktu yang lama, dan developer ingin game mereka tetap hidup dan dimainkan oleh banyak orang.
Namun untuk mencapai tahap sustainable itu, sepertinya “grinding” bukanlah jawaban yang tepat. Ketika kita memaksakan diri untuk melakukan sesuatu secara terus-menerus, nilai tambah dari kegiatan itu justru makin mengecil (diminishing result). Kita bisa belajar sedikit tentang sustainability ini dari salah satu atlet esports paling veteran di dunia, Daigo Umehara.
Dalam bukunya yang berjudul The Will to Keep Winning, Daigo berkata bahwa berlatih dan bermain terlalu banyak itu adalah hal yang buruk. Atlet esports seharusnya tidak memforsir diri demi mengejar target jangka pendek, karena itu akan membuat mereka hancur baik secara fisik maupun secara mental.
Daigo sendiri memiliki rutinitas latihan yang berkisar hanya antara tiga sampai enam jam sehari. Menurutnya, kualitas latihan lebih penting daripada kuantitas. Lebih baik menghabiskan sedikit waktu namun berhasil mempelajari hal baru, daripada bermain belasan jam tapi tidak mendapat peningkatan apa-apa.
Mungkin para pegiat esports bisa belajar dari prinsip ini, bahwa untuk menciptakan ekosistem yang sustainable kuncinya adalah dengan menciptakan rutinitas yang sustainable pula. Ini tidak hanya berlaku bagi atlet. Organizer turnamen juga harus merancang jadwal kompetisi yang sustainable, yang memberi ruang bagi tim-tim esports untuk beristirahat serta mengeksplorasi hal baru. Sementara developer game harus bisa menyeimbangkan kecepatan update konten dengan stabilitas meta. Jangan sampai developer terlalu bernafsu merilis konten baru demi monetisasi, sementara para pemain kelabakan dengan meta yang berubah terlalu cepat.
Masalah sustainability di dunia esports ini bisa jadi bahan diskusi panjang sendiri, dan saya rasa para pegiat esports pun sudah banyak yang memikirkannya. Mudah-mudahan artikel ini dan dokumenter dari CBS bisa menjadi pengingat, atau pemicu munculnya ide baru yang akan memajukan ekosistem esports, terutama di Indonesia.
Sumber: CBS