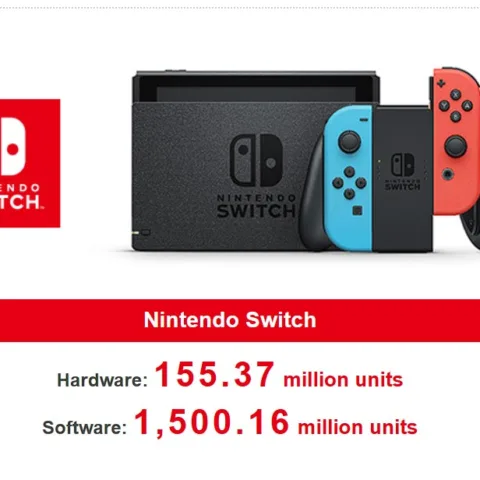Dalam Direct di Februari 2022, Nintendo mengungkap rencana mereka untuk membuat versi remake/remaster dari beberapa game klasik, termasuk Chrono Cross, Front Mission, dan Front Mission 2. Keputusan Nintendo ini mungkin tidak aneh, mengingat beberapa tahun belakangan, semakin banyak proyek untuk menghidupkan kembali game-game lawas, mulai dari Resident Evil 2 dan 3, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Yakuza Kiwami, sampai Final Fantasy VII Remake.
Menariknya, walau sebagian franchise game bisa bertahan hingga berpuluh-puluh tahun — seperti Pokemon, Mario, dan Final Fantasy — tidak sedikit franchise game yang menghilang begitu saja. Padahal, beberapa franchise game yang dianggap telah mati suri tetap memiliki fans yang setia, seperti Suikoden. Konami meluncurkan Suikoden 5 untuk PlayStation 2 pada 2006. Sementara Gensō Suikoden: Tsumugareshi Hyakunen no Toki hanya diluncurkan di Jepang untuk PlayStation Portable pada 2012. Namun, sampai 2022, para fans masih aktif membicarakan tentang seri game RPG klasik tersebut.
Para fans bahkan membuat gerakan yang dinamai Suikoden Revival Movement. Harapan fans akan game Suikoden baru terkabul ketika mantan tim pengembangan Suikoden membentuk Suikoden baru dan membuat proyek berjudul Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes di Kickstarter.
Pertanyaannya, apa yang membuat Suikoden dan Final Fantasy berbeda? Walau dibuat oleh developer yang berbeda, kedua game itu sama-sama merupakan JRPG. Jadi, kenapa salah satu dari game itu bisa bertahan hingga sekarang, sementara yang lain tidak?
Contoh Franchise Game yang Bertahan Lama
Sebelum membahas tentang faktor yang membuat franchise game bertahan lama dan hal-hal yang justru bisa mematikan franchise game, mari kita melihat daftar franchise game yang memang bertahan lama. Salah satu tolak ukur yang saya gunakan adalah umur dari franchise game itu sendiri. Berikut lima franchise game dengan umur paling panjang:
1. The Oregon Trail – 49 tahun
2. Mario – 40 tahun
3. Pac-Man – 40 tahun
4. Galaxian – 39 tahun
5. Space Invader – 38 tahun
Selain umur franchise game, tolak ukur lain yang saya gunakan adalah berapa banyak game yang dibuat untuk sebuah IP. Karena, walau sebuah IP bisa bertahan lama, maka hal itu menjadi kurang berarti jika tidak banyak game yang dibuat berdasarkan IP tersebut. Semakin banyak game yang dibuat berdasarkan pada sebuah franchise, maka saya menganggap, semakin sukses juga franchise tersebut. Berikut lima franchise game yang paling sering dibuat ke dalam game:
1. Mario (115 games)
2. Mega Man (100 games)
3. Sonic (80 games)
4. Final Fantasy (75+ games)
5. Pokemon (55+ games)
Take a look at the history of Mega Man from @CapcomUSA_ #E32018 pic.twitter.com/4AaWTNaK95
— E3 (@E3) June 12, 2018
Selain game, media lain yang bisa digunakan untuk membuat IP yang bertahan lama adalah komik. Kesamaan lain antara game dan komik — khususnya komik buatan penerbit negara-negara Barat — adalah keduanya sering melakukan remake atau reboot. IP populer seperti Batman atau Spider-Man telah dirombak ulang berulang kali oleh DC dan Marvel. Tentu saja, para penerbit tidak merombak ulang cerita dari karakter mereka tanpa alasan.
Salah satu alasan mengapa penerbit seperti DC atau Marvel melakukan reboot adalah karena hal itu memang menguntungkan dari segi bisnis, menurut Screen Rant. Pasalnya, reboot berarti cerita akan kembali ke titik awal. Dan hal ini akan menarik lebih banyak pembaca baru, karena mereka tidak perlu mengikuti cerita yang sudah disajikan sebelumnya. Tak hanya pembaca baru, komik jilid pertama juga biasanya menarik perhatian para kolektor. Alasannya sederhana, karena para kolektor tahu, di masa depan, harga komik jilid pertama punya potensi untuk meroket.
Selain sebagai strategi bisnis, alasan lain penerbit komik melakukan reboot adalah karena mereka mengubah tim kreatif yang bertanggung jawab atas sebuah IP. Satu hal yang harus diingat, sistem pembuatan komik di negara-negara Barat berbeda dengan negara-negara Timur. Di Jepang atau Tiongkok, seorang kreator komik akan bertanggung jawab sepenuhnya atas komik yang dia buat. Kelanjutan dari manga One Piece sepenuhnya ada di tangan Eiichiro Oda. Sementara manhwa Noblesse merupakan karya Son Jeho sebagai penulis dan Lee Kwangsu sebagai ilustrator. Tentu saja, para kreator komik bisa menggunakan jasa asisten untuk membantu mereka. Namun, pada akhirnya, sang kreator punya tanggung jawab penuh atas karyanya.
Lain halnya dengan komik di Barat. Di Amerika Serikat, sebuah komik bisa menjadi tanggung jawab banyak orang. Sebagai contoh, kreator dari Spider-Man — Stan Lee dan Steve Ditko — kini telah tiada. Meskipun begitu, komik Spider-Man masih diterbitkan sampai saat ini. Karena, tim yang membuat komik dari sang superhero itu memang terus berubah. Jadi, jangan heran jika komik-komik dari Marvel atau DC punya banyak timeline.
Ketika penerbit melakukan reboot, cerita dari semua karakter di bawah penerbit itu biasanya juga akan dirombak ulang. Dengan begitu, tim kreatif bisa mengangkat masalah baru yang lebih relevan dengan zaman. Meskipun begitu, bagian fundamental dari sebuah karakter akan tetap dipertahankan. Sebagai contoh, Bruce Wayne akan tetap menjadi orang kaya yang tidak punya kekuatan khusus, dan kematian orang tuanya akan menjadi pemicu mengapa dia ingin menjadi seorang vigilante.

Untuk melihat bagaimana penerbit komik menyesuaikan cerita yang mereka angkat agar tetap relevan, mari kita gunakan Captain America sebagai contoh. Captain America adalah tokoh superhero yang pertama kali tampil di komik pada Maret 1941, tepat di tengah Perang Dunia 2. Saat itu, Amerika Serikat memang sudah memberikan bantuan pada negara-negara Sekutu. Namun, mereka belum menyatakan perang secara terbuka pada kubu Axis.
Komik Captain America bercerita tentang Stever Rogers, pria yang ingin menjadi tentara, tapi ditolak karena tubuhnya yang ringkih. Dia kemudian menawarkan diri untuk ikut dalam eksperimen pembuatan super soldier. Eksperimen itu sukses dan voila! Rogers pun menjadi Captain America. Plot dari Captain America cukup sederhana, yaitu tentang seorang pahlawan yang melawan berbagai penjahat. Salah satu villain yang harus dihadapi oleh Rogers adalah seorang Nazi bernama Red Skull.
Kunci kesuksesan komik Captain America ketika itu adalah karena para pembaca merasa bahwa Rogers merupakan representasi dari identitas mereka. Dan saat Pearl Harbor diserang pada Desember 1941, Captain America telah menjadi komik yang paling laku. Sepanjang Perang Dunia 2, komik Captain America bercerita tentang petualangan Rogers melawan pasukan Axis, bersama dengan sidekick-nya, Bucky Barnes.
Setelah perang selesai, popularitas komik Captain America menurun. Karena, masyarakat tak lagi terlalu tertarik dengan genre superhero. Genre yang populer ketika itu adalah horror, romance, funny animals, dan lain sebagainya. Komik Captain America bahkan sempat berhenti dicetak untuk sementara. Captain America Comis berakhir pada Juli 1949. Empat tahun kemudian, pada 1953, Captain America kembali muncul dalam komik Young Men no. 25. Dan komik Captain America sempat kembali dicetak pada 1954. Tapi, pada tahun yang sama, seri komik tersebut diberhentikan. Komik Captain America baru kembali pada tahun 1960-an.
Sekarang, Captain America merupakan salah satu tokoh penting dalam Marvel Cinematic Universe (MCU). Pada awalnya, alias Captain America dipegang oleh Steve Rogers. Namun, Rogers memutuskan untuk berhenti menjadi superhero di Avengers: Endgame. Posisi Captain America yang kosong lalu diisi oleh Sam Wilson, yang sebelumnya dikenal dengan nama Falcon. Cerita tentang bagaimana Wilson menyesuaikan diri dengan perannya sebagai Captain America ditampilkan dalam seri TV Falcon and the Winter Soldier.

Satu hal yang menarik dari seri TV itu adalah karena ia tidak hanya bercerita tentang para superhero yang melawan para villains. Seri TV itu juga mengangkat masalah tentang rasisme, yang merupakan isu abadi di Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bagaimana franchise superhero berubah dan beradaptasi, mengangkat topik yang relevan dengan masalah yang muncul ketika media itu diluncurkan.
Dari masa ke masa, cerita yang ditampilkan dalam komik, film, atau game memang terus berubah. Namun, satu hal yang tetap konstan adalah kecintaan manusia akan cerita. Dan hal ini sudah dibuktikan dalam sebuah studi. Pada 2014, Neuroeconomist, Paul J. Zak mengungkap bahwa cerita bisa memicu dirilisnya hormon oksitosin. Salah satu fungsi oksitosin adalah membuat seseorang menjadi kooperatif, karena hormon itu memperkuat rasa empati yang seseorang rasakan.
Hormon oksitosin bisa dirilis ketika seseorang menonton film atau membaca buku. Asalkan, film atau buku itu memang bisa menarik perhatian sang penonton atau pembaca. Buktinya, seseorang cenderung merasa puas diri setelah menonton bagaimana James Bond menyelamatkan dunia. Contoh lainnya, seseorang akan menjadi lebih termotivasi untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka setelah menonton pasukan Sparta dalam film 300.
Sementara contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seorang karyawan merasa lebih puas ketika dia mendengar cerita tentang bagaimana apa yang dia lakukan bisa membantu klien perusahaan. Menariknya, mendengar cerita yang lebih personal akan membuat seorang karyawan merasa lebih puas daripada jika mereka mendapatkan informasi tentang betapa suksesanya perusahaan; berapa banyak produk yang berhasil mereka jual.
Jadi, manusia memang cenderung suka dengan cerita. Dan cerita yang menarik dan relevan merupakan salah satu kunci di balik kesuksesan IP di komik. Hal yang sama juga berlaku untuk franchise game.
Apa yang Membuat Franchise Game Bertahan Lama?
Dari industri komik, kita tahu bahwa menyajikan isu yang terus relevan merupakan salah satu kunci untuk membuat franchise yang bisa bertahan lama. Namun, dalam game, narasi bukan satu-satunya faktor yang harus disesuaikan. Untuk membuat game klasik tetap relevan, hal lain yang harus disesuaikan oleh developer adalah gameplay. Hal inilah yang dilakukan oleh Square Enix ketika membuat Final Fantasy VII Remake.
Jika Anda pernah memainkan Final Fantasy VII orisinal, Anda pasti tahu bahwa game itu menggunakan turn-based combat system. Namun, ketika Square Enix meluncurkan versi remake dari game tersebut, mereka merombak combat system yang digunakan. Tujuannya adalah agar game itu tidak ketinggalan zaman dan tetap seru untuk dimainkan. Tak hanya gameplay, terkadang, developer bahkan harus mengubah genre dari sebuah franchise game. Sebagai contoh, pada awalnya, Mario dikenal sebagai game platformer. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Nintendo merilis game Mario dalam berbagai genre, mulai dari balapan, RPG, sampai fighting.
Untuk mencari tahu tentang faktor lain yang membuat franchise game bisa bertahan lama, sekarang, mari kita mengamati Pokemon, franchise game yang telah bertahan selama lebih dari 25 tahun dan menghasilkan lebih dari 50 games. Pokemon selalu memiliki tokoh utama yang masih sangat muda. Namun, sang tokoh utama punya kebebasan untuk menentukan apa yang ingin dia lakukan. Dia bisa memilih kemana dia akan pergi, Pokemon seperti apa yang ingin dia tangkap dan latih. Kebebasan tersebut menjadi daya tarik tersendiri untuk gamers anak dan remaja.
Di saat yang sama, Pokemon tetap menarik perhatian gamers dewasa. Dan mereka tidak hanya memainkan game-game lawas, tapi juga game-game Pokemon yang paling baru. Menurut Vice, alasan mengapa gamers dewasa tetap menyukai Pokemon adalah karena game itu mengingatkan mereka akan masa kecil mereka.
Dengan kata lain, memainkan game Pokemon membuat gamers dewasa merasa nostalgia. Dan nostalgia memang bisa jadi motivasi bagi seorang gamer untuk membeli atau memainkan sebuah game. Karena itu, jangan heran jika Nintendo berencana untuk menghidupkan kembali game-game lawas mereka, seperti yang disebutkan oleh Games Industry.
Bagi perusahaan game, keuntungan lain yang mereka dapat ketika mereka menargetkan gamers yang lebih dewasa adalah karena mereka memiliki daya beli yang lebih kuat. Saya pertama kali memainkan Chrono Cross ketika saya masih SD. Ketika itu, uang saku saya hanya cukup untuk membeli versi bajakan dari game tersebut. Tapi sekarang, setelah saya bekerja, saya tidak hanya bisa membeli game orisinal, tapi juga merchandise dari game itu jika saya mau.
Membuat remake atau remaster dari franchise game klasik juga bisa menjadi strategi perusahaan game untuk mempertahankan IP lama yang mereka miliki. Karena, salah satu karakteristik dari franchise yang bisa bertahan lama adalah kontennya bisa dinikmati oleh beragam generasi. Sebagai contoh, Batman dan Spider-Man telah berulang kali dibuat menjadi film yang ditayangkan dalam layar lebar. Sementara IP seperti Mario dan Final Fantasy selalu menawarkan game-game baru bagi fans-nya. Meskipun, game baru yang dirilis merupakan spin-off dari seri utama.
Salah satu kunci agar franchise game bisa bertahan lama adalah kemampuan untuk beradaptasi, menyesuaikan diri dengan zaman. Menariknya, sebuah franchise game juga bisa menjadi awet ketika ia selalu mengusung inti yang sama. Contohnya, Pokemon. Dari tahun ke tahun, selalu ada game baru untuk Pokemon. Namun, “inti” dari game-game Pokemon tetap sama, yaitu berpetualang sebagai Pokemon trainer: mengumpulkan dan membesarkan Pokemon sesuai gaya bermain para gamer. Dan hal ini menjadi ciri khas dari game Pokemon, yang memunculkan rasa familier pada para pemain, khususnya pemain lama.
Satu hal yang unik, walau game-game Pokemon biasanya memiliki inti yang sama, setiap gamer bisa memainkannya dengan caranya masing-masing. Karena, para gamers biasanya punya gaya bertarung dan tipe Pokemon favorit yang berbeda-beda. Jadi, walau pun gameplay dari game-game Pokemon tetap sama, tapi pengalaman yang didapatkan dari masing-masing pemain bisa berbeda.
Apa yang Bisa Membunuh Franchise Game?
Setelah membahas tentang franchise game yang dapat bertahan hingga berpuluh-puluh tahun, sekarang, mari kita mengamati franchise game yang justru terhenti di tengah jalan, walau sempat populer. Salah satu faktor yang bisa membuat pengembangan franchise game menjadi morat-marit adalah pertikaian antara developer dan publisher. Hal ini terjadi pada franchise game simulasi farming, Harvest Moon/Story of Seasons.
Pada awalnya, game Harvest Moon dikembangkan oleh developer XSeed dan dirilis oleh publisher Natsume. Namun, kemudian, keduanya memutuskan untuk berpisah karena perbedaan visi tentang apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan franchise Harvest Moon.
Dari pertikaian itu, Natsume mendapatkan hak untuk menggunakan nama Harvest Moon. Sementara XSeed mendapatkan lisensi atas game-game Harvest Moon. Karena itu, ketika XSeed membuat game simulasi farming, mereka menggunakan judul Story of Seasons. Walau pun, game tersebut terkadang menampilkan karakter-karakter yang sama dengan Harvest Moon. Sebaliknya, Natsume bisa merilis game simulasi farming dengan judul Harvest Moon. Namun, mereka tidak boleh merilis ulang game-game Harvest Moon buatan XSeed.
Lucunya, setelah berpisah, XSeed dan Natsume terus membuat game simulasi farming masing-masing. Tentu saja, Story of Seasons buatan XSeed dan Harvest Moon dari Natsume memiliki perbedaan dengan satu sama lain. Selain perbedaan tentang karakter, hal lain yang membedakan Harvest Moon dengan Story of Seasons adalah fitur untuk menyesuaikan keadaan ladang milik pemain. Dalam Story of Seasons, pemain tidak bisa memilih jenis ladang yang mereka miliki. Namun, di Harvest Moon, pemain bisa memilih tampilan dari ladang pertanian yang mereka dapatkan.
Selain perbedaan dalam game yang dibuat oleh XSeed dan diterbitkan oleh Natsume, keduanya juga punya perbedaan dalam strategi bisnis. XSeed tidak pernah tertarik untuk meluncurkan versi mobile dari game yang mereka buat. Mereka baru menunjukkan ketertarikan untuk menjajaki platform mobile pada 2019. Sementara itu, Natsume justru pernah meluncurkan game Harvest Moon khusus untuk mobile. Walau kemudian, mereka melakukan porting ke konsol, menurut laporan dari The Gamer.
Sebelum ini, Hybrid.co.id pernah membahas kenapa belakangan, semakin banyak developer yang membuat versi remake atau remaster dari game klasik. Salah satu alasannya adalah karena franchise game lawas sudah memiliki fanbase sendiri. Jadi, perusahaan game tidak perlu repot-repot untuk mencari target pasar. Menariknya, keberadaan fans — khususnya fans hardcore — juga bisa menjadi bumerang bagi perusahaan yang ingin menghidupkan kembali franchise game lama.
Buktinya, salah satu alasan mengapa Ubisoft enggan untuk menghidupkan kembali franchise Splinter Cell adalah karena mereka khawatir, game baru yang mereka buat akan mendapat protes dari para fans. Hal ini diakui oleh CEO Ubisoft, Yves Guillemot pada 2019. Memang, ketika developer membuat game baru dari franchise lama, mau tidak mau, pasti akan ada elemen dari game itu yang diubah. Ingat, terkadang, developer memang harus mengubah genre atau gameplay dari game lama untuk membuat game itu tetap relevan. Hanya saja, Ubisoft khawatir, jika mereka mengubah beberapa elemen dari Splinter Cell, hal ini justru akan membuat para fans hardcore dari franchise itu marah.
Alasan lainnya adalah karena Ubisoft telah merilis Splinter Cell: Blacklist pada 2013. Dan meskipun game itu mendapatkan sambutan hangat, penjualan dari game tersebut tidak sesuai harapan, lapor GameSpot.
Kabar baiknya, pada akhir 2021, Ubisoft akhirnya mengungkap rencana mereka untuk membuat remake dari game Splinter Cell. Hanya saja, game itu tidak akan diluncurkan dalam waktu dekat. Karena, proyek pengembangan game tersebut baru saja disetujui. Matt West, Producer di Ubisoft Toronto mengatakan, mereka ingin memastikan bahwa identitas dari franchise Splinter Cell tetap ada di dalam game terbaru yang mereka buat.
Contoh perusahaan game lain yang memiliki franchise game populer yang berakhir terbengkalai adalah Konami. Perusahaan Jepang itu memegang lisensi atas sejumlah seri game yang sempat populer, seperti Castlevania, Metal Gear Solid, dan Suikoden. Dalam kasus Castlevania, Konami sebenarnya sempat meluncurkan sejumlah game untuk IP tersebut. Hanya saja, karena tidak semua game Castlevania sukses, maka Konami memutuskan untuk tidak melanjutkannya.
Game Castlevania pertama dirilis pada 1986. Game-game dari franchise Castlevania juga pernah diluncurkan di konsol NES Classic dan SNES Classic. Jadi, dari segi umur, franchise Castlevania sebenarnya tidak kalah dari sejumlah franchise ikonik milik Nintendo. Game Castlevania yang paling populer adalah Symphony of the Night, yang dirilis untuk PlayStation pada 1997. Game tersebut tidak hanya mempopulerkan seri Castlevania, tapi juga menjadi salah satu pelopor dari genre Metroidvania. Ketika pertama kali diluncurkan, Symphony of the Night mendapatkan sambutan yang sangat baik dari para gamers dan kritikus. Reputasi itu bahkan bertahan hingga sekarang.
Setelah sukses dengan Symphony of the Night, Konami mencoba untuk membuat beberapa game Castlevania. Namun, tidak semua game itu sukses. Game Castlevania yang Konami rilis setelah Symphony of the Night adalah Castlevania: Legends. Hanya saja, game yang dirilis untuk Game Boy itu dianggap sebagai game Castlevania yang paling buruk. Hal ini terliihat dari rating-nya yang paling rendah. Namun, Konami tidak berhenti di sana. Mereka merilis dua game Castlevania untuk Nintendo 64. Game pertama mendapatkan rating yang cukup baik, walau tidak sefantastis Symphony of the Night. Namun, game kedua — Legacy of Darkness — justru menuai protes dari para gamers. Di masa depan, tren ini akan terus berlanjut. Konami akan meluncurkan beberapa game Castlevania. Tapi, setiap kali satu game Castlevania dianggap sukses, game berikutnya justru hadir mengecewakan.
Konami bahkan sempat mengganti nama seri Castlevania menjadi Lords of Shadow. Bersamaan dengan pergantian nama, Konami juga mengubah creative directors yang bertanggung jawab atas seri itu. Koji “Iga” Igarashi, pria yang dikenal sebagai otak di balik Symphony of the Night dan telah memimpin proyek pengembangan game-game Castlevania sejak lama, dipindahkan ke divisi lain. Game pertama dari Lords of Shadow mendapatkan review yang sangat positif, walau ia tetap belum bisa mengalahkan popularitas Symphony of the Night. Sayangnya, kualitas dari Mirror of Fate, sekuel dari Lords of Shadow, mulai mengalami penurunan. Dan ketika Lords of Shadow diluncurkan, game itu dianggap tidak bisa memenuhi ekspektasi para fans.
Prioritas Konami pun berubah. Pada 2014, Igarashi akhirnya memutuskan untuk keluar. Alasannya adalah karena dia tidak setuju dengan cara Konami memperlakukan karyawan mereka. Memang, Konami sempat tertimpa skandal tentang perlakuan buruk yang diterima oleh pegawai mereka. Contohnya, Konami dikabarkan memasang kamera untuk memonitor pergerakan karyawan. Para pegawai yang dianggap tidak punya peran penting akan dipindahtugaskan menjadi satpam.
Igarashi bukan satu-satunya kreator Konami yang akhirnya memutuskan untuk pergi. Hideo Kojima, kreator dari Metal Gear Solid, juga akhirnya angkat kaki pada 2015. Padahal, Kojima telah bekerja untuk Konami selama 30 tahun. Dan ketika dia keluar, dia sudah menjabat sebagai Executive Content Officer. Dia juga menjadi Director dari Kojima Productions, studio game di bawah kepemimpinan Kojima. Pertikaian antara Kojima dan Konami inilah yang membuat franchise dari Metal Gear Solid mati.
Game MGS terakhir yang mendapat sentuhan Kojima adalah Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Setelah itu, Konami memang merilis Metal Gear Survive pada 2018. Namun, game tersebut justru menuai kritik dari fans lama MGS. Selain karena pertikaian antara Konami dengan Kojima, tapi juga karena Metal Gear Survive mendaur ulang banyak aset dari The Phantom Pain, mulai dari lokasi sampai mekanik gameplay. Selain Igarashi dan Kojima, kreator lain yang juga berselisih dengan Konami adalah Akira Sakuma, yang membuat Momotaro Dentetsu.
Kesimpulan
Untuk bisa membuat franchise game yang disukai banyak orang, developer harus bisa membuat cerita atau karakter yang membekas di hati para gamers. Dan biasanya, sebuah franchise game akan memiliki karakteristik khas. Sebagai contoh, Final Fantasy dikenal sebagai seri game RPG, sementara Metal Gear populer sebagai stealth game.
Keunikan dari franchise itulah yang membuat para fans setia. Jadi, untuk membuat franchise game awet, developer biasanya akan mempertahankan karakteristik game yang membuatnya menjadi unik. Di sisi lain, developer juga harus bisa menyesuaikan game yang mereka buat agar tetap relevan dengan zaman. After all, it is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent; it is the one most adaptable to change.
Sumber header: Nintendo Life