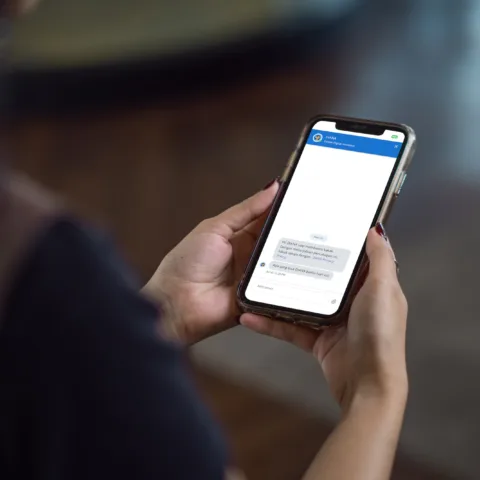Siapa yang tak ingin bekerja sesuai dengan passion mereka? Bagi gamer, menjadi pemain esports profesional tentunya adalah sebuah impian. Bisa bermain game yang disukai setiap hari, bertanding di depan ribuan atau bahkan ratusan ribu orang dan menjadi populer, dibayar pula. Gamer mana yang tak tergiur dengan itu semua? Sayangnya, menjadi pemain esports tidak melulu menyenangkan. Ada pengorbanan yang harus para atlet esports profesional lakukan.
Jika Anda berpikir, “Ah, kan tinggal main aja, gampang!” Bagi seorang gamer, bermain game tentu saja terasa menyenangkan. Tapi ingat, menurut Hukum Gossen: “Jika pemuasan kebutuhan terhadap satu hal dilakukan terus-menerus, kenikmatannya akan terus berkurang sampai akhirnya mencapai titik jenuh.” Ini contoh mudahnya. Misalnya, makanan favorit Anda adalah nasi goreng. Ketika Anda memakan nasi goreng, Anda tentu akan senang. Namun, bayangkan jika setiap hari — pagi, siang, dan malam — Anda hanya bisa makan nasi goreng. Bayangkan jika itu terjadi selama satu minggu, satu bulan, atau mungking satu tahun! Lama-kelamaan, Anda akan merasa bosan dengan nasi goreng, walau tadinya, itu adalah makanan favorit Anda. Begitu juga dengan bermain game.
Apa Masalah yang Dihadapi Pemain Esports Profesional?
Sebelum ini, Hybrid.co.id pernah membahas tentang berbagai masalah yang harus dihadapi oleh para pemain esports dalam meniti karir mereka. Salah satu masalah yang harus mereka hadapi adalah stres dan burnout. Menurut riset yang dilakukan oleh University of Chichester, para atlet esports menghadapi tantangan mental yang serupa dengan atlet olahraga tradisional. Jadi, jangan mengira menjadi atlet esports profesional mudah karena mereka “hanya” duduk di hadapan layar untuk bertanding.

Menurut Yohannes Paraloan Siagian, pemegang gelar M.M dari Universitas Indonesia dan M.B.A. dari I.A.E de Grenoble, Universite Piere Mendes, yang pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA 1 PKSD dan Vice President EVOS Esports, beban mental para atlet esports justru lebih berat daripada atlet olahraga biasa. Pasalnya, atlet olahraga biasanya hanya dituntut untuk memberikan performa terbaik dalam satu ajang olahraga saja. Sementara atlet esports bisa mengikuti beberapa turnamen atau liga dalam satu tahun. Itu artinya, mereka harus memberikan performa terbaik mereka lebih dari satu kali atau mereka harus menjaga agar performa mereka stabil selama waktu yang lebih lama dari atlet olahraga biasa.
“Kemudian, feedback dari publik jauh lebih cepat sampai ke player di dunia esports daripada di olahraga tradisional,” ujar pria yang akrab dengan panggilan Joey ini saat dihubungi melalui pesan singkat. “Memang, di zaman medsos, ini sudah mulai umum. Tapi, perbedaannya adalah atlet esports ‘hidup’ di dunia online: streaming, media sosial, bahkan in-game chat. Hal-hal tadi adalah jalur komunikasi publik yang cepat dan tidak terfilter. Ini berarti, semua pujian bisa cepat sampai. Tapi, semua hinaan, kata-kata kasar, dan lain sebagainya… juga bisa langsung ke player. Dan toxicity netizen Indonesia sudah bukan rahasia lagi…”

Selain tuntutan untuk bermain maksimal, hal lain yang bisa menjadi beban mental atlet esports adalah kontrak dengan tim profesional. Joey mengatakan, saat ini, di Indonesia, kebanyakan kontrak antara pemain profesional dan tim cenderung menguntungkan tim. Para pemain bisa dilepas atau dinonaktifkan kapan saja. “Masih mending kalau dilepas dan bisa main di itm lain. Kalau hanya dinonatkfikan dan tidak bisa bermain?” kata Joey. “Kemungkinan diganti setelah satu atau dua performa buruk itu akan menjadi beban besar bagi player manapun, dan berlaku di cabang manapun. Tapi, di esports, saat ini ancaman itu lebih besar. Dan jika terjadi, jalur kembali ke tim utama seringkali tidak jelas.”
Hal lain yang bisa menambah beban mental pemain esports adalah masalah “META (Most Effective Tactics Available)”. Berbeda dengan basket, sepak bola, atau olahraga tradisional lainnya, perubahan META di esports sangat cepat. “Misalnya, ada teknologi VAR (Video Assistant Referees) di sepak bola. Ini akan dibahas selama beberapa tahun, baru dites, dan setelah itu baru diimplementasi. Contoh lainnya, perubahan taktik tim basket yang bisa dilihat melalui video dan terpantau melalui scouting dan observasi,” ujar Joey. Sebagai perbandingan, perubahan META di game-game esports tidak hanya cepat, tapi juga sering.
Saat developer game merilis update atau patching, maka biasanya akan ada karakter yang di-buff atau di-nerf. Tak tertutup kemungkinan, ada mekanisme game yang juga berubah. Misalnya, ketika update Outlanders dirilis untuk Dota 2. “Ini membuat pemain esports harus selalu up to date dan beradaptasi ke semua perubahan yang terjadi, karena di esports, perubahan kecil saja di satu aspek bisa memengaruhi seluruh META dengan drastis. Tuntutan harus up to date ini juga jadi beban besar yang tidak bisa disepelekan,” kata Joey. “Semua ini, digabung dengan kenyataan bahwa atlet esports tidak punya ‘offseason‘, memberikan tekanan mental yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan olahraga tradisional.”

Mia Stellberg, psikolog esports yang pernah bekerja untuk Astralis, salah satu tim Counter-Strike: Global Offensive terbaik dunia, juga mengatakan hal yang sama. “Secara umum, menjadi atlet esports memiliki beban yang lebih berat daripada atlet olahraga tradisional,” ujar Stellberg dalam wawancara dengan RedBull. Dia mengungkap, ada banyak tanggung jawab atlet esports yang tak terlihat oleh masyarakat awam. Bagi tim internasional, mereka harus sering berpergian ke luar negeri. Dan pergi ke luar negeri untuk ikut serta dalam turnamen esports tentunya tidak sama dengan pergi untuk tamasya. Seorang atlet esports juga dituntut untuk tetap memberikan performa terbaik meskipun mereka mengalami jet lag.
Pentingnya Mengendalikan Emosi Bagi Atlet Esports
Saat bekerja untuk Astralis, Stellberg menjelaskan, tugasnya adalah untuk mengetahui keadaan para pemain dan membantu mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Salah satunya dalam hal mengendalikan emosi. Jika Anda sering bermain game kompetitif, Anda pasti akrab dengan istilah “rage quit“. Sayangnya, pemain esports tak mungkin melakukan itu, apalagi ketika mereka tengah bertanding.
Selain itu, seseorang biasanya merasa frustasi ketika dia melakukan kesalahan atau kalah — apalagi kalau musuh ikut mengolok-olok. Jika tak terkendali, rasa frustasi ini justru bisa membuat seorang atlet esports membuat lebih banyak kesalahan. Membuat kesalahan, kemudian merasa frustasi, yang berakhir pada lebih banyak kesalahan, dan meningkatkan rasa frustasi; seperti terjebak dalam lingkaran setan. Karena itulah, Stellberg mencoba untuk mengajarkan para pemain esports untuk berpikir rasional dan tetap rileks bahkan setelah mereka melakukan kesalahan. Dengan begitu, mereka tetap bisa fokus untuk bermain dengan baik.
“Saya ingin mengajarkan para pemain cara mengendalikan emosi mereka sehingga mereka bisa berpikir lebih rasional. Jika Anda emosional, ini mungkin menyebabkan masalah saat bermain game,” ujar Stellberg. “Agar bisa memberikan performa terbaik, Anda harus bisa berpikir dengan jernih. Karena jika Anda merasa stres, hal ini akan memengaruhi koordinasi mata-tangan dan reaction time Anda. Rasa percaya diri Anda juga memengaruhi performa Anda. Karena, jika Anda tidak merasa percaya diri, Anda akan lebih mudah merasa stres.”

Mengendalikan emosi tidak hanya penting ketika seorang atlet esports membuat kesalahan, tapi juga ketika mereka dalam posisi unggul. Ketika Anda merasa bahwa Anda sudah pasti akan menang, biasanya, Anda menjadi lebih santai. Dan jika tidak hati-hati, rasa percaya diri yang terlalu berlebihan ini justru bisa jadi senjata makan tuan.
CEO BOOM Esports, Gary Ongko Putera mengaku, rasa tidak percaya diri pemain bisa menjadi penghambat tim meraih kemenangan. Berdasarkan pengalamannya, pemain bisa merasa tidak percaya diri ketika menghadapi pemain lain yang dianggap lebih populer. Selain itu, atlet esports juga bisa merasa tertekan karena merasa harus memuaskan para fans. Ini semua bisa menyebabkan pemain atau tim bermain terlalu aman. “Istilahnya, jadi play to not lose bukannya play to win,” ujar Gary melalui pesan singkat. Menurutnya, mental pemain esports juga diuji ketika mereka tak kunjung meraih tujuan mereka, misalnnya memenangkan turnamen.
“Nggak semua orang kuat bisa menerima kegagalan di fase yang sama berturut-turut. Misalnya, kalah di open atau closed qualifier melulu,” kata Gary. “Awal-awal mungkin semangat, tapi habis tiga atau empat kali gagal, mungkin justru akan meragukan diri sendiri atau ketika bermain merasa ada pressure. Atau kebalikannya, sudah pernah ke luar negeri untuk mewakili Indonesia, tiba-tiba mau mewakili Indonesia lagi, jadi merasa ada pressure.”
Bagaimana Cara Pemain Esports Mengatasi Stres?
Masing-masing pemain esports bisa memiliki sumber stres yang berbeda-beda. Joey memberikan contoh, bagi pemain esports yang berasal dari keluarga berada mungkin lebih peduli akan reputasinya daripada penghasilannya. Sementara pemain yang datang dari keluarga kurang mampu mungkin akan lebih cemas dia akan kehilangan sumber penghasilannya jika performanya buruk dan dia dikeluarkan dari tim.
“Jadi, dalam menghadapi keadaan seperti ini, pertama, harus dimulai dari hal-hal yang global,” kata Joey. “Misalnya, membangun rasa percaya diri, mengajari cara melepaskan tekanan agar proses pelepasan tekanan tidak berbahaya.” Dia menjadikan balon sebagai metafor. Jika balon terus ditiup tanpa membiarkan udara di dalamnya keluar, balon akan meledak. Sementara jika udara di dalam balon dikeluarkan begitu saja, balon bisa terbang tanpa arah yang jelas. Begitu juga dengan pelepasan stres bagi pemain esports. Mereka harus dapat melakukannya dengan cara yang tepat agar stres tidak menumpuk dan membuat mereka “meledak”.

Masing-masing atlet esports punya caranya sendiri dalam melepas stres. “Ada pemain yang larinya ke rohani dan iman. Sebelum stream atau latihan atau bertanding selalu berdoa. Ada yang memilih untuk mencari kegiatan refreshing. Ada yang memilih untuk menghabiskan waktu lebih bannyak dengan keluarga,” ungkap Joey. Sayangnya, tidak sedikit juga pemain esports yang memilih melepaskan stres dengan cara yang kurang sehat. “Tidak sedikit pemain profesional yang terlihat sangat akrab dengan alkohol, vape, dan lain sebagainya. Seringkali, jawaban yang diberikan ketika ditanya kenapa mereka sering minum adalah untuk ‘menenangkan pikiran’.”
Padahal, gaya hidup yang tidak sehat — mengonsumsi junk food, rokok, alkohol, dan pola tidur tak teratur — justru bisa menyebabkan kondisi fisik memburuk. Semua itu juga bisa menurunkan kondisi mental seseorang, sehingga mereka lebih muda merasa stres karena tekanan. Dan saat stres, pemain cenderung mencari jalan pintas untuk menghadapi tekanan, yaitu mengonsumsi junk food, rokok, dan alkohol.
Kebanyakan pemain esports masih sangat muda. Tidak jarang, pemain esports sudah mengundurkan diri pada pertengahan umur 20-an. Secara legal, anak di bawah umur 21 tahun, menjadi tanggung jawab orangtua. Artinya, mereka tidak akan bisa menjadi pemain profesional tanpa persetujuan orangtua. Jadi, jika orangtua setuju anaknya meniti karir sebagai pemain profesional, mereka seharusnya juga bertanggung jawab dalam membantu sang anak/remaja untuk mengatasi stres dengan cara yang sehat.
https://youtu.be/WkB0Q42PZdw
“Tapi, menurut saya, secara etis dan moral, ini merupakan tanggung jawab tim yang seharusnya mereka penuhi,” ujar Joey. “Kalau sudah membawa anak muda ke satu lingkungan saat dia harus memberikan performa maksimal, ya seharusnya tim memberikan dukungan full. Tim juga akan bisa lebih untung karena atlet akan bisa bermain dengan maksimal dan mengangkat nama tim.”
Menurut Joey, tim esports profesional seharusnya memiliki psikolog yang bertanggung jawab dalam mengatasi masalah mental dalam organisasinya. Tak hanya itu, atlet profseional juga sebaiknya rela mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan jasa psikolog untuk membantunya mengatasi berbagai masalah mental yang dia alami. “Di luar negeri, atlet sepak bola misalnya, memiliki trainer fisik pribadi, koki pribadi, psikolog pribadi dan lain sebagainya,” kata Joey. Dia sadar, hal ini mungkin tidak bisa diterapkan di Indonesia begitu saja. “Tapi, saya merasa, atlet seharusnya paham bahwa dirinya adalah sumber daya yang perlu dia kembangkan dengan investasi. Hal ini akan membantu untuk menaikkan level mereka.”
Sementara itu, menurut Stellberg, sangat penting bagi para pemain esports untuk bisa menyeimbangkan kehidupan profesional dan kehidupan pribadi mereka. Memang, atlet esports biasanya hobi bermain game. Namun, saat menjadi pemain profesional, bermain tak lagi sekadar menjadi hobi, tapi sebuah pekerjaan. Stellberg percaya, menghabiskan waktu lebih dari 10 jam setiap hari selama seminggu penuh di depan komputer untuk latihan bukanlah ide bagus. Pemain esports sebaiknya menghabiskan waktu istirahat mereka bersama teman, keluarga, atau kekasih mereka.
“Salah satu tugas saya adalah membantu para pemain untuk menyeimbangkan kehidupan profesional dan pribadi mereka,” ujar Stellberg. “Saya merasa, tidak peduli apa pekerjaan Anda, Anda seharusnya tetap memiliki kehidupan pribadi dan kehidupan sosial dan mungkin, seorang kekasih.”
Kesimpulan
Jika Anda sering menonton pertandingan sepak bola, Anda pasti pernah mendengar seorang fans mengeluh, “Seharusnya si A melakukan XYZ!” Atau mungkin, Anda adalah orang yang meneriakkan kata-kata itu ke layar televisi? Sekedar berbicara memang jauh lebih mudah dari melakukan sesuatu. Begitu juga dengan esports. Meskipun para atlet esports terlihat hanya duduk di depan layar dan bermain, mereka juga menghadapi berbagai masalah yang mungkin tidak terlihat, termasuk tekanan mental.
Memang, mengatur stres dan tekanan mental adalah tanggung jawab para pemain esports profesional. Namun, sebagai fans, tidak ada salahnya untuk menjadi lebih baik.
Sumber header: Fortune