Artikel ini adalah bagian dari Seri Mastermind DailySocial yang menampilkan para inovator dan pemimpin di industri teknologi Indonesia untuk berbagi cerita dan sudut pandang.
Industri teknologi bukanlah tempat bermain, tidak ada buku panduan dalam mencapai kesuksesan dalam hal ini. Menjadi salah satu penggiat investasi teknologi, Nicko Widjaja, telah merasakan pahit manisnya industri ini. Sebagai seorang CEO, Nicko berhasil menjadikan MDI Ventures dengan dukungan telkom Indonesia, satu dari sedikit perusahaan modal ventura (PMV) yang menuai profit paling besar.
Pada tahun 2011, Ia memulai PMV bernama Systec Ventures dikala banyak yang masih ragu dengan perkembangan startup teknologi di Indonesia. Setelah tutup buku di tahun 2013, Ia kemudian memimpin sebuah program startup inkubator terbesar oleh Telkom di Indonesia bersama Telkom Indigo Incubator. Di tahun 2015, Ia naik menjadi kepala PMV racikan Telkom Indonesia, MDI Ventures.
Setelah sukses membawa lima perusahaan exit di luar negeri, ekspansi ke Singapura, dan melakukan penggalangan dana kedua untuk MDI Ventures, Nicko kini diangkat menjadi CEO dari PMV baru milik BRI, BRI Ventures, untuk mengelola dana sebesar $250 juta menargetkan ekosistem fintech di Indonesia.
Seluruh pencapaian ini bukan tanpa kerja keras dan dedikasi. Berikut adalah beberapa potongan cerita yang berhasil dirangkum oleh tim DailySocial.
Dimulai dari bagaimana perjalanan awal seorang Nicko Widjaja serta apa yang menjadi dasar di balik setiap pemikirannya?
Pertama-tama, saya terlahir di waktu yang tepat. Jika saya lahir 10 tahun lebih awal, dunia belum siap, sementara lebih lama lagi sudah terlambat.
Saya tidak pernah percaya dengan sistem pendidikan oleh institusi. Hal itu sangat ketinggalan jaman dan secara eksplisit menggambarkan sistem kerja sebuah pabrik – anda masuk, lalu jadilah, dan ditaruh di suatu tempat. Saya tumbuh menjadi seorang rebel. Bukan seorang pembangkang terhadap orangtua, namun lebih kepada iseng terhadap teman.
Selama itu, saya merasa tidak biaa beradaptasi. Saya tidak merasa cocok dimanapun dan mengalami depresi melihat kehidupan di sekitar layaknya sebuah film “Divergent” – di mana sedikit banyak mencerminkan era 90-an. Saya mengampu pendidikan di sebuah institusi Katolik, semacam persiapan untuk ‘orang-orang sukses’ yang dididik untuk berkomitmen pada kehormatan keluarga, karier, reputasi, dan dapat dipercaya seumur hidup.
Percaya tidak percaya, beberapa orang bahkan benar-benar menjadi seperti yang dulu sering mereka bicarakan. Seorang pekerja bank, arsitek, dokter, atau bahkan putra / menantu seseorang – sangat mengerikan, bukan?
Dalam usaha menyesuaikan diri, saya gagal pada banyak subyek seperti matematika, IPA, Bahasa Inggris, dan lainnya. Reputasi sebagai penunda akut melekat sampai akhirnya saya menggagalkan pelajaran olahraga dan orang-orang menganggap itu sebagai pemberontakan. Seketika dunia sekitar berubah, dan saya menjadi ‘tanpa golongan’.
Saat itu saya sadar bahwa mengikuti jejak orang lain bukanlah sebuah keharusan, juga memiliki banyak waktu untuk mempelajari diri sendiri. Hal ini menjadi penting dalam membangun fondasi seorang Mastermind: Know yourself.
Di perguruan tinggi, jurusan apa yang Anda ambil? Mengapa?
Ya, bukankah ini sesuatu yang sudah dirancang untuk kita? Lulus SMA, masuk universitas, membangun karir/menikah, lalu pensiun. Sebuah lingkaran penderitaan yang tanpa akhir.
Alasan saya masuk universitas mungkin berbeda dengan kebanyakan orang yang berfikir: “Ya, saya ambil jurusan akuntansi karena ingin menjadi akuntan!” atau “Yah, sepertinya bakat saya adalah menggambar, saya akan coba jurusan desain grafis!”. Dalam pikiran saya ada keinginan untuk belajar mengenal diri sendiri. Apa hal-hal yang menjadi inspirasi/motivasi serta apa yang tidak. Tempat di mana kita bisa menemukan tujuan/ambisi lain yang lebih besar dalam hidup. Mengapa sebuah mata kuliah bisa membuat saya penasaran sementara yang lain tidak.
Saya belum menetapkan jurusan sampai tahun ketiga di universitas. Beruntung saya memiliki orang tua yang mau mengerti dan tetap mendukung. Pada awalnya saya fokus pada jurusan teknik dan merasa tidak cocok, lalu mengambil beberapa matkul bisnis yang ternyata tidak menarik, sampai akhirnya saya menemukan liberal arts. Pelajaran tentang evolusi manusia, narasi serta interaksi menjadi fokus hidup saya. Apapun itu yang sedang saya lakukan, semua adalah hasil dari pembelajaran saya saat itu.
Coba ceritakan kisah awal kembalinya Anda ke Indonesia. Apa saja yang Anda lakukan?
Setelah lulus dari Oregon, saya pindah ke San Fransisco di tahun 2000. Kota itu dipenuhi dengan ‘situs-situs’, hanya selang beberapa tahun – yang sekarang dikenal dengan nama startup. Semua tentang e-commerce hingga portal pra-sosmed sangat menarik. Saya mencari pengalaman di beberapa perusahaan, aeringkali di bidang pengembangan konten, bisnis analisis, dan bidang lain yang cocok untuk lulusan baru.
Saya kembali ke Jakarta di tahun 2004 dan bergabung dengan Indofood sebagai corporate development officer yang bersinggungan langsung dengan CEO yang mengajarkan banyak hal tentang dasar-dasar bekerja serta hepicopter view dalam mengatur strategi perusahaan. Setelah tiga tahun bekerja, saya mulai mendengar desas desua tentang seseorang yang ingin menciptakan sebuah revolusi.
Setelah resign dari Indofood di 2007, saya menjadi co-founder di beberapa unit bisnis, Thinking*Room (perusahaan desain), Mindcode (perusahaan riset conaumer dan inovasi), serta berinvestasi pada beberapa produksi film. Masa sebelum industri VC adalah masa dimana hidup masih indah dan belum serumit sekarang.
Selama 2009-2010, beberapa teman mengenalkan saya pada dunia teknologi, orang-orang yang membangun Koprol, Urbanesia, Dealoka, di sini juga pertama kali saya mengenal Rama dan DailySocial – tanpa terasa sudah hampir 10 tahun!
Bagaimana bisa muncul ide untuk membangun Systec?
Saat itu saya sedang terlibat dalam industri film pada tahun 2009 ketika dihubungi beberapa rekan, “Ayo kesini dan dengarkan langsung dari orangnya!”
Kemudian mereka diundang ke acara tentang startup lokal yang mencoba menantang Google di Indonesia, sesuatu seperti Google versi Bahasa Indonesia, atau semacamnya – sebuah ide yang revolusioner pada saat itu. Bayangkan, Google bisa menerapkan semua bahasa secara instan begitu saja. Namun, orang ini, entah darimana membawa kebanggaan, nasionalisme bercampur, dan jadilah $ 1-2 juta ia kumpulkan dengan mudah.
Awalnya, mereka minta dikenalkan dengan orang-orang di jajaran atas. Saya melakukan networking sana-sini – saya rasa mengapa tidak – sampai ketika saya tak henti membicarakan ekosistem digital. Saya seperti masuk dalam mode penggalangan dana ketika berbicara tentang digital.
Beberapa bulan kemudian, saya ikut mendirikan Systec Ventures dengan beberapa rekan dari Mindcode. Ini menjadi bagian awal ekosistem mengingat pada tahun 2011 hanya ada sedikit kami yang hadir di acara-acara seperti Sparxup, Echelon, dll. Systec Ventures adalah studio pembangun ventura, inkubator + investor + kolaborator – mirip dengan Science Inc. Hal ini menjadi menarik ketika saya bisa bekerja sama dengan para pengusaha. Mereka dapat memanfaatkan ruang terbuka milik kami (seperti di kantor sekarang) secara gratis selama Anda seorang investee. Di sinilah Anda bisa mendapatkan gambaran akan pengembangan ekosistem.

Apakah ada yang bisa Anda ceritakan mengenai kegagalan berbisnis?
Banyak yang belum menyadari bahwa VC menghasilkan uang dari penjualan saham portofolio mereka – bukan dari dividen. Di Systec Ventures, kami sangat sibuk mengerjakan setiap portofolio untuk menyempurnakan produk, konten, dan model bisnis, sampai kami sadar bahwa tanpa investasi lanjutan maka tidak akan ada profit – sekali lagi ini terjadi di masa awal dunia startup di Indonesia.
Satu per satu portofolio kehilangan likuiditas, sementara bertaruh hanya pada satu atau dua produk fitur.
Hal ini menjadi pelajaran besar yang dipetik, bahwa yang paling berkontribusi terkait industri ini melibatkan pemikiran ‘uang adalah raja.’
Apa yang anda lakukan selanjutnya? Indigo?
Pada tahun 2014, kami diperkenalkan pada Telkom Indonesia, mereka sedang akan memulai kembali Telkom Indigo Incubator untuk startup digital. Kami saling mempelajari terutama ketika Telkom Indonesia memulai program ini di tahun yang sama dengan Systec Ventures, 2011. Sebelumnya, Indigo Incubator adalah ajang untuk mengumpulkan para pendiri startup untuk akhirnya bekerja dalam salah satu proyek di Telkom Group. Tidak jauh berbeda dengan Systec Ventures, atau perusahaan yang didukung konglomerat lainnya.
Ketika kami (sebagian besar adalah tim Systec) masuk ke Indigo Incubator untuk membantu meningkatkan program, kami menyadari bahwa investasi lanjutan harus menjadi metrik kesuksesan – layaknya program inkubator di seluruh dunia.
Saat itu … pendanaan lanjutan jarang sekali terjadi. Sebagian besar program inkubator (terutama di korporat) gagal menarik investor luar. (Satu hal yang dibanggakan dari Systec Ventures adalah akses ke individu/konglomerat yang akan menjajaki bisnis digital).
Kami mengundang berbagai jaringan investor untuk terlibat selama program sebagai mentor/penasihat. Hasilnya, kami mendapatkan 40% pendanaan lanjutan dalam batch pertama, lalu sekarang adalah Indigo Creative Nation yang bisa saja menjadi program akselerator startup paling terkemuka di Indonesia menghasilkan lebih dari 70% follow-on dan $180 juta kapitalisasi pasar dengan portfolio startup terkemuka seperti Payfazz, Nodeflux , PrivyID, Sonicboom, GoersApp, dan sebagainya.
Bagaimana cara Anda menemukan penawaran-penawaran bagus?
Filosofi investasi saya sederhana: Anda akan mendapatkan penawaran bagus dari seseorang yang tahu cara mendapatkan penawaran terbaik. Lalu, mengapa mereka mau memberikan penawaran terbaik? Di MDI Ventures, kami benar-benar mengembangkan dan membina hubungan dengan investor global papan atas. Berbagi dan menggabungkan sumber daya bersama dengan Telkom Indonesia menjadi bagian dari strategi untuk mendapatkan penawaran terbaik.
Saya pernah mendengar tentang salah satu VC di Singapura memberikan investasi kepada startup namun tanpa ada itikad baik, pada akhirnya hanya untuk meraup uang LP. Hal ini tidak bisa diterima, sebab di industri ini, berita menyebar dengan cepat, dan jika Anda benar-benar ingin bergelut dalam industri, reputasi adalah segalanya.
Belakangan, bagaimana perasaan Anda ketika berada di MDI?
MDI Ventures bisa jadi salah satu dari sedikit VC yang paling profitable di Indonesia. Bulan lalu saja (Juni / Juli), kami terlibat dalam tiga exit, dengan total lima exit selama 4 tahun beroperasi, satu IPO di TSE dan satu di ASX. Hal ini mengawali era baru bagi para pemula yang terlibat dalam industri dengan banyaknya uang mengalir. Tim ini akan selalu memiliki semangat tinggi.
Bergeser ke BRI. Bagaimana proses transfer Anda hingga sampai pada posisi ini?
MDI Ventures adalah salah satu yang pertama menerapkan model CVC (Corporate Venture Capital). Ada rumor yang menyebutkan bahwa kami menjadi referensi setiap kali ada pembahasan mengenai CVC. Saya merasakan validasi pertama kali untuk bekerja dengan entitas luar adalah ketika berkolaborasi dengan Mandiri Capital untuk meluncurkan Mandiri Digital Incubator pada tahun 2016. Itu menjadi interaksi pertama kami dengan sektor perbankan.
Sejak saat itu kami telah bekerja sama dengan Pegadaian dan Pertamina untuk memperkenalkan sinergi perusahaan rintisan dan korporasi.
Ketika Anda berbicara tentang transformasi digital di sektor perbankan, BRI telah menjadi salah satu yang paling progresif dalam mengimplementasikan inisiatif digitalnya sejak tahun 2017. Pembahasan tentang dana sudah dimulai pada tahun 2018 dan tesis ekosistem telah dibuat.
Saya menyatakan dengan jelas bahwa perpindahan ke BRI Ventures tidak berarti meninggalkan MDI Ventures sepenuhnya. Keduanya jelas bersinergi dalam banyak hal dan belajar untuk saling memanfaatkan sumber daya satu sama lain: bank terbesar, perusahaan telekomunikasi terbesar, dengan startup teknologi berada di tengah. Kami tengah menantikan kesempatan untuk berkolaborasi sesegera mungkin.
Sedikit jeda membahas industri, coba ceritakan sedikit tentang pengalaman mengajar Anda.

Lagi-lagi, hidup tidak bisa diprediksi – bahkan untuk orang-orang yang tidak menyukai institusi akademik. Saya pernah mengajar di UPH Business School selama 2010-2015 (dalam kurun waktu sama dengan Systec Ventures). Ini menjadi kesempatan menarik, bisa bersinggungan dengan pemikiran dari generasi mendatang dalam hal kepemimpinan, kewirausahaan, dsb.
Saya memiliki metode yang tidak konvensional. Ketika bertemu dengan salah satu murid saya, mereka bisa berbagi pengalaman berada di dalam kelas yang ‘kacau’. Kebanyakan, saya akan membahas tentang ekonomi digital masa kini dan memaparka studi kasus Amazon, YCombinator, Yahoo, dan lainnya, serta mengaitkannya dengan isu-isu domestik.
Apakah yang menjadi rahasia kesuksesan Anda?
Pertama, jangan takut untuk membuat kesalahan selama ada hal yang bisa dipelajari. Kedua, berani mengambil resiko serta lebih terlibat dalam prosesnya.
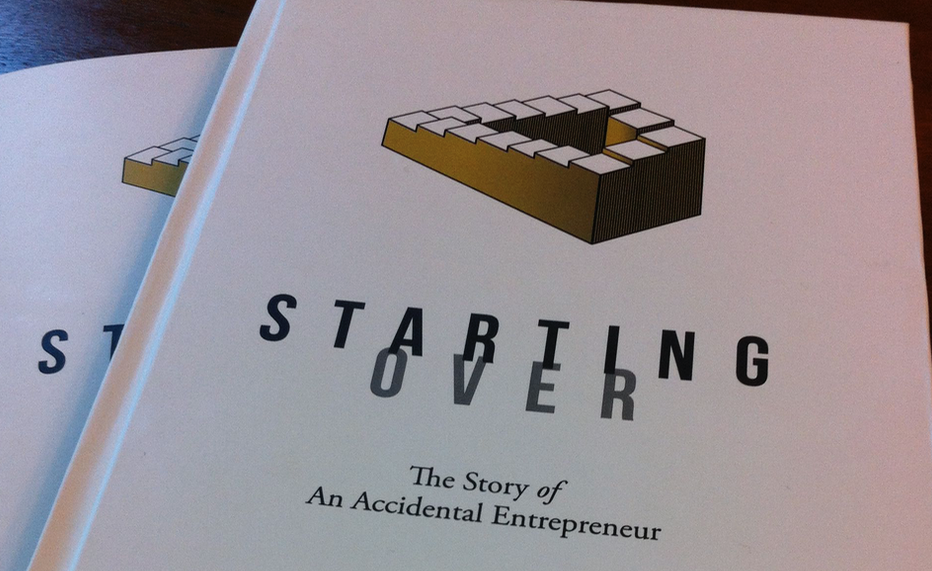
Apa saran Anda untuk para pelaku industri untuk memulai startup?
Saya dikenal sebagai seseorang yang blak-blakan dalam mengomentari startup, tapi inilah pendapat saya: Anda merasa bisa menjadi unicorn selanjutnya? Tidak, saya katakan.
Beberapa unicorn bahkan tidak pernah bercita-cita untuk menjadi unicorn. Pemikiran sebagai underdog justru yang mengantar Google, Facebook, dan Netflix ke atas panggung. Mereka menang melawan dominasi para korporat kelas atas: Netflix Vs Blockbuster, Amazon Vs Barnes & Noble (serta segenap rantai retail di Amerika), Apple Vs IBM, dsb. Jadi, jika Anda mengaku sebagai startup dan bermimpi mendominasi industri tanpa ada validasi internal maupun external, ini bukan ajang yang tepat.
–
Artikel ini ditulis dalam Bahasa Inggris, diterjemahkan oleh Kristin Siagian


















