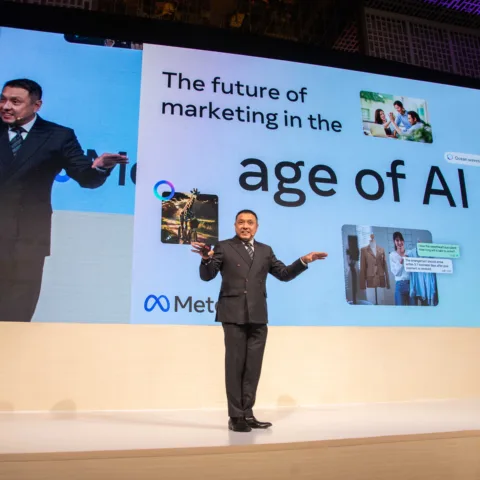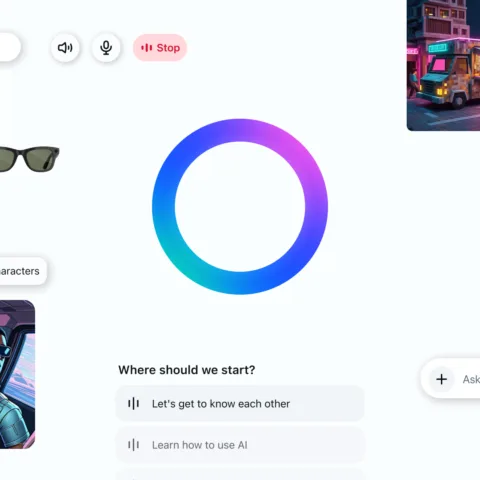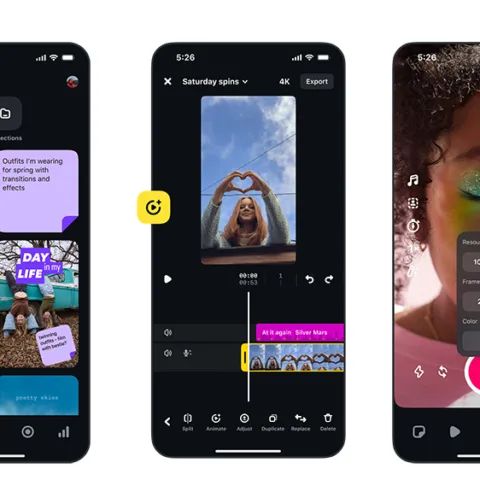Pekan ini Mark Zuckerberg berkunjung ke Indonesia. Bagi pemerhati teknologi, tentu ini hal yang menarik. Tokoh IT dunia yang terakhir berkunjung ke Indonesia adalah Bill Gates. Waktu itu, salah satu filantropis dan orang terkaya di dunia ini membawa tawaran kerjasama, salah satunya terkait dengan pengembangan lebih luas untuk penelitian anak negeri di UGM tentang penanggulangan penyakit di negara tropis. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan Mark Zuckerberg tawarkan ke Indonesia? Melihat salah satu agendanya adalah bertemu dengan Presiden terpilih Jokowi, pertanyaan tersebut tentu akan menarik dan bukan tidak mungkin melahirkan banyak spekulasi.
Sebenarnya, tidak sulit menebak makna kunjungan pendiri Facebook tersebut ke Indonesia. Sejak tahun 2013, Mark mengawali sebuah gerakan yang dikenal dengan Internet.org yang bertujuan untuk memberikan akses Internet, yang selama ini baru bisa diakses sekitar sepertiga penduduk bumi, kepada 2/3 penduduk sisanya. Gerakan dari Mark ini bukan satu-satunya.
Google, raksasa teknologi lain yang tidak tergabung dalam gerakan Internet.org, memiliki versinya sendiri yang disebut sebagai Project Loon. Untuk ini Google mencoba mengkesplorasi ide menggunakan balon berteknologi tinggi untuk memberikan akses Internet yang lebih luas kepada penduduk dunia, terutama di daerah-daerah yang sulit.
Facebook tentu tidak mau ketinggalan. Pada bulan Maret lalu, mereka meresmikan connectivity lab yang fokus meneliti teknologi baru untuk memperluas akses Internet. Mereka merekrut beberapa ahli dari NASA dan perusahaan aerospace untuk mengembangkan model pesawat “high-altitude long endurance” (HALE). Semacam drone, dengan daya terbang yang lebih tinggi, dan mampu bertahan terbang dalam waktu yang cukup lama untuk memberikan akses Internet yang lebih luas ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau kabel seperti kepulauan dan daerah terpencil.
Salah satu yang menarik dalam kampanye “everyone of us, everywhere, connected” tersebut adalah penggunaan terminologi knowledge economy. Bagi akademisi istilah ini sesungguhnya belum selesai didiskusikan. Sejak tahun 1990 sejak era informasi mulai berkembang pesat, banyak akademisi menyatakan bahwa knowledge (pengetahuan) adalah sumberdaya yang menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Walaupun demikian, karena sifatnya yang abstrak, faktor ini sukar diukur secara pasti.
Mark menggunakan istilah ini untuk memperkuat gagasan bahwa ekonomi saat ini adalah ekonomi berbasis pengetahuan dan ide, sumberdaya yang bisa diperbaharui dan tersedia bagi semua orang. Dalam kampanyenya di Amerika Serikat, Mark menekankan bahwa knowledge economy akan membawa lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup .
Studi yang dilakukan Deloitte dan disponsori Facebook atas nama Internet.org memperkirakan bahwa memperluas akses Internet di negara berkembang dapat meningkatkan produktivitas sebesar 25%, meningkatkan GDP sebesar 2,2 triliun dolar Amerika, 140 juta lapangan pekerjaan baru, dan 160 juta orang yang berhasil dientaskan dari kemiskinan. Tidak berhenti di sana Mark tidak segan mengangkat isu bahwa konektivitas bisa jadi sekarang merupakan salah satu hak asasi manusia.
Terdengar bombastis? Bagaimana jika setelah mengetahui paparan ini kemudian ada tawaran menarik dari Facebook tentang akses Internet gratis di beberapa daerah yang belum bisa dijangkau di Indonesia? Atau perluasan Internet yang sudah ada? Tawaran ini terlalu menarik untuk ditolak bukan?
Mari kita tengok situasi Internet di Indonesia. Kebanyakan netizen merujuk kepada kecepatan Internet sebagai indikator keberhasilan penetrasi Internet di negeri kita. Walaupun merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, kecepatan bukan merupakan bahasan utama jika berbicara masalah coverage atau jangkauan. Percaya atau tidak, walaupun banyak orang mengeluhkan kecepatan Internet rata-rata di Indonesia, masalah yang lebih besar sebenarnya adalah berapa banyak rakyat yang menjadi pengguna Internet?
Data APJII menunjukkan bahwa di tahun 2013 ada 71,9 juta pengguna internet di Indonesia, naik 13% dari 63 juta di tahun sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa baru sekitar 28% (dari 248 juta, termasuk anak-anak dan orang tua) penduduk Indonesia yang menggunakan Internet. Masih jauh dari target Millenium Development Goals yang menyatakan bahwa di tahun 2015 50% penduduk di negara berkembang diharuskan melek internet. Kesenjangan ini tentu sangat menarik bagi gerakan semacam internet.org atau project balloon.
Sebagai individu, tawaran Internet gratis susah ditolak. Tidak perlu membahas jauh, kita selama ini sudah menggunakan banyak layanan gratis, dari Google, YouTube, dan semacamnya. Jika misalnya ada tawaran akses Internet gratis atau murah dari Facebook, mengapa tidak?
Menurut saya, ada dua persoalan yang paling tidak membuat hal ini perlu dipertimbangkan kembali secara personal. Pertama adalah masalah privasi, dimana kita akan menjadi sasaran iklan yang muncul dari riwayat kita menggunakan Internet. Iklan tentu bukan sekedar mengganggu pemandangan, tetapi juga memecah fokus, yang bagi beberapa orang selain mengganggu produktivitas, juga mengganggu kenyamanan. Yang kedua adalah masalah keamanan, dimana data-data pribadi kita bisa jadi (dan sudah beberapa kali terjadi) akan terekspos di dunia luar. Dua persoalan ini cukup panjang apabila didiskusikan. Khusus kali ini saya ingin mengajukan beberapa persoalan terkait potensi tawaran tersebut dengan melihat kita sebagai sebuah bangsa.
Kedaulatan Informasi
Diskusi tentang kedaulatan informasi juga merupakan diskusi yang belum usai dan baru ramai di panggung wacana. Secara sederhana, terminologi ini muncul dari keinginan untuk “merdeka”, mandiri dari pihak asing, dan berdaulat dalam infrastruktur, perangkat keras, lunak, konten dan layanan teknologi informasi. Faktanya, Pak Gatot D. Subroto mengungkap 95% perangkat keras Indonesia saat ini berasal dari luar negeri. Belum perangkat lunak dan juga konten yang didominasi pihak asing. Harapannya adalah, seperti yang diungkapkan pak Gatot, pemerintah baru bisa merevitalisasi fungsinya menjadi lebih aktif berperan, tidak sekedar membuat regulasi dan tergantung kepada swasta.
Jika pemerintah melihat knowledge economy sebagai upaya pengembangan pengetahuan dan ide sebagai basis ekonomi kreatif yang mandiri seharusnya mereka mulai membuat rancangan dan perhitungan yang jelas, sejauh apa sumberdaya pengetahuan ini bisa “ditambang” sendiri dan berhati-hati dalam mengizinkan pihak asing berpartisipasi. Sebagai negeri dengan populasi yang besar, Indonesia adalah pasar sekaligus sumberdaya informasi yang besar.
Jika 28% diantaranya sudah menjadi pengguna Internet, maka kita bisa mengatakan 28% memiliki potensi sumberdaya informasi, dan 28% itu pula jadi sasaran atau pasar dari informasi. Hitungan sangat sederhananya, apabila 28% itu ternyata lebih banyak membawa keuntungan kepada pihak asing daripada ke bangsa sendiri, maka hitungannya adalah defisit. Atau dengan bahasa lain kita lebih sering jadi pasar/konsumen daripada jadi produsen. Perlu dicatat bahwa 28% populasi Indonesia ini masih lebih banyak dari seluruh penduduk Britania Raya di tahun 2014.
Akan tetapi apabila pemerintah masuk ke dalam terminologi knowledge economy versi Mark Zuckerberg, di mana untuk mengembangkan bisnis yang lebih baik, diperlukan iklan yang lebih akurat, analisis yang lebih dalam yang pada gilirannya akan memerlukan akses yang lebih luas, dan kemudian membangun kesepakatan untuk membuka akses ke daerah-daerah di Indonesia dengan istilah bantuan infrastruktur untuk akses internet, maka resikonya tidak sekedar Indonesia akan jadi pasar baru bagi bisnis ini, tetapi juga resiko ketergantungan terhadap infrastruktur asing terkait kebutuhan konektivitas yang seharusnya merupakan kewajiban pemerintah. Jika ketergantungan ini terus berlanjut dan bersambung ke ketergantungan perangkat keras, perangkat lunak dan konten, boleh dikatakan kita perlahan tapi pasti kehilangan kedaulatan informasi.
“Negara” Facebook sendiri di quarter ke dua 2014 ini tercatat memiliki ‘penduduk’ aktif sebesar 1,32 Miliar dan menghasilkan pendapatan bersih $791 Miliar [10] dan berdaulat penuh atas seluruh layanannya. Angka ini hanya gambaran sederhana dari sedikit potensi sumberdaya pengetahuan yang dikelola secara profesional.
Sumberdaya pengetahuan, seperti kata Mark Zuckerberg, bisa dimiliki siapa saja, termasuk bangsa Indonesia. Sudah saatnya kita memperhatikan dan mengelola sumberdaya ini sama pentingnya dengan sumberdaya alam seperti minyak, gas, dan kelapa sawit. Jika kita memiliki 248 juta penduduk, maka itu berarti kita memiliki potensi 248 juta knowledge worker, dan jika dikelola dengan baik, mereka bisa jadi di masa mendatang lebih mendatangkan keuntungan dari semua tambang minyak yang kita miliki.
Dalam pergaulan internasional, tentu kita tidak bisa abai dengan perjanjian, kontrak perdagangan atau term and condition. Oleh karena itu saya berharap dilibatkannya para akademisi, praktisi dan publik terkait kebijakan di sektor teknologi informasi untuk membangun peta jalan pengembangan kedaulatan informasi dengan kalkulasi yang matang. Perlu kepemimpinan dan kebersamaan yang kuat untuk memulai kemandirian dalam pengembangan perangkat keras, perangkat lunak, dan konten di Indonesia. Permasalahan ini tidak bisa selesai di satu kementrian (seperti kominfo saja misalnya), karena akan melibatkan regulasi terkait dengan perdagangan, perindustrian dan implementasinya.
Mengembangkan kemandirian dalam sumber daya pengetahuan memerlukan waktu dan perencanaan yang matang serta evaluasi berkelanjutan. Prosesnya tentu saja tidak akan sepi dari pro kontra. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan asing tentu tidak akan berhenti membuat tawaran dengan logika “kalau bisa beli, kenapa buat sendiri?”. Skema lain mereka bisa jadi berupa perjanjian-perjanjian dengan hasil instan, sudah jadi dan mudah dipopulerkan di publik tanpa perlu bersusah payah, seperti skema bantuan dan penyediaan.
Para politisi dan media bisa saja mengemas apapun perjanjian dan kesepakatan tersebut dengan kalimat-kalimat yang enak didengar. Di sini saya hanya merasa kita perlu mengingat kesalahan dalam membuat kontrak-kontrak yang tidak proporsional dengan pihak asing terkait dengan sumberdaya alam di negeri ini di masa lalu. Tulisan ini adalah sekedar upaya agar bangsa ini tidak membuat kesalahan yang sama dengan kontrak-kontrak asing terkait potensi sumberdaya pengetahuan dan informasi Indonesia di masa mendatang.
Catatan Editorial: Tulisan ini dibuat oleh Idham Ananta, mahasiswa pascasarjana S3 bidang Computer Science and Electronics Engineering di University of Essex, UK dan dipublikasi pertama kali di Selasar. Artikel dimuat ulang dengan sedikit penyuntingan atas izin penulis.
[Ilustrasi foto “Sovereignty”: Shutterstock]