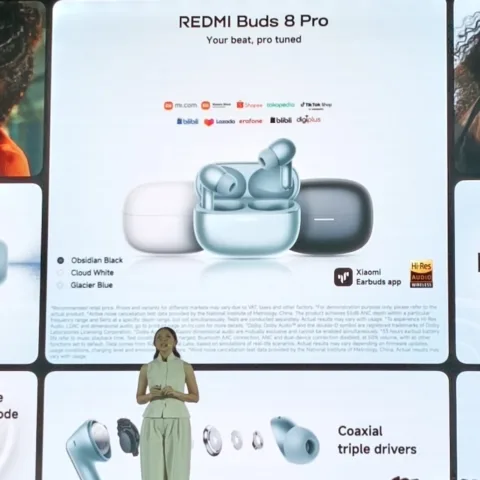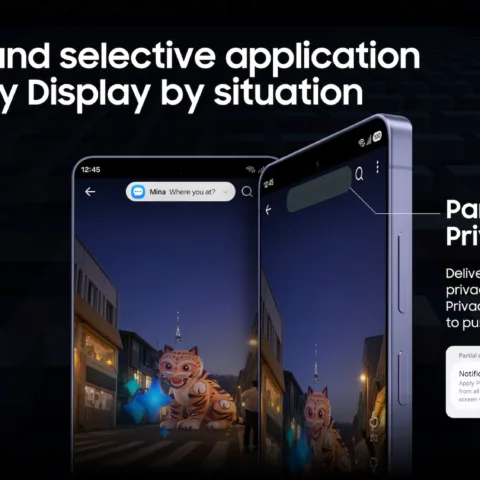Dalam berbagai artikel yang sudah saya tulis di sini selama hampir dua tahun, adalah pergeseran-pergeseran dalam industri musik, terutama yang berhubungan dengan lagu itu sendiri. Industri musik [rekaman] yang sudah berjalan puluhan tahun memang menempatkan penggandaan sebuah rekaman lagu untuk dijual sebagai intinya, baik itu dalam format vinyl, kaset, CD ataupun media digital. Hukum-hukum berbagai negara bahkan sampai tingkat internasional di WIPO sudah dirancang untuk melindungi industri penggandaan ini. Dalam konteks ini, rekaman lagu adalah komoditi.
Mungkin saya tidak perlu mengulas ulang apa yang terjadi ketika rekaman lagu bertemu dengan media digital dan internet dalam waktu yang hampir sama, yang nyaris menihilkan makna dari bisnis penggandaan rekaman lagu. Transfer lagu dari media CD ke dalam format MP3 bisa dilakukan siapa saja, dan juga disebar dengan mudah melalui internet, sehingga kontrol ketat yang dibutuhkan dalam bisnis yang mengandalkan penggandaan satu barang menjadi hilang. Sayangnya, pergeseran teknologi dan kebiasaan ini bukannya diteliti baik-baik oleh industri musik rekaman, tapi malah diserang dengan dasar pembajakan, sampai hari ini.
Di sisi lain, yang membedakan seorang musisi terhadap seniman lain, misalnya, memang adalah karyanya yang berupa musik. Karya musik ini kini bentuk yang paling umum dikenal memang adalah lagu pop, dengan struktur lirik, refrain dan kord yang mudah dicerna banyak orang, meskipun bukan satu-satunya kemungkinan berkarya di musik. Ketika media visual menawarkan berbagai produk budaya dengan tingkat penerimaan publik dan konsumsi yang berbeda-beda, dari kartun hingga lukisan kanvas, musik yang memiliki dasar audio memang idealnya disebar melalui media tertentu (seperti CD atau file MP3) sehingga dijadikan basis sebuah bisnis.
Tapi bukan berarti, menjadi seorang musisi harus mendasarkan karya (atau pemasukan) dari media audio ini. Banyak musisi yang hidup dari pertunjukan live, sampai ada juga yang berkarir dalam membuatkan soundtrack dan scoring untuk film maupun sinetron. Media audio ini dapat melekat ke berbagai hal, sampai menjadi nada panggil atau ringtone yang sempat menjadi industri cukup besar. Dan toh, para konsumen musik kan sebenarnya ingin mendengarkan lagu, bukan membeli media berisi audio – ini merupakan salah satu dasar saya dan teman-teman mendirikan Ohdio.fm.
Mungkin lagu satuan, bahkan album, sudah bukan menjadi komoditi yang menarik untuk dibeli untuk banyak orang – terbukti dari turunnya minat membeli CD atau lagu digital selama beberapa tahun terakhir. Tapi ini bukan berarti konsumsi musik turun, malah tetap tinggi, hanya saja jalur distribusi dan cara konsumsinya bergeser. Apabila industri musik masa lalu mengeluarkan lagu secara sedikit-sedikit atau satu per satu, kini konsumsi musik bergerak menuju pola yang menawarkan akses terhadap ribuan bahkan jutaan lagu. Terbukti dengan lahir dan populernya layanan seperti Spotify, Guvera dan lain-lain.
Apakah ini berarti lagu akan punah sebagai komoditi? Tidak. Sama seperti halnya ringback tone, lagu digital yang dapat dibeli untuk diunduh akan selalu memiliki peminat, sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan konsumennya, hanya saja mungkin tidak akan sebesar dahulu, dan sudah pasti tidak akan menggantikan kehilangan pemasukan dari turunnya penjualan CD, dan akan bertahan selama keseimbangan antara usaha (teknologi, manajemen licensing, dan sebagainya) dan keuntungan yang didapat.
Metode dan kebutuhan konsumsi musik itu sudah mulai terpecah ke berbagai jalur, sehingga yang dibutuhkan sebenarnya adalah berbagai inovasi dalam presentasi musik (via media) atau penjualan musik (via distribusi), yang lama-kelamaan nyaris tidak dapat dibedakan. Tapi yang pasti pengulangan pola bisnis penggandaan itu tidak akan menemui skalabilitas yang cukup besar, sehingga cara berpikir lagu sebagai komoditi perlu dihilangkan. Akses ke jutaan lagu melalui layanan streaming sedang tumbuh, sementara penjualan lagu digital satuan masih cukup kuat di banyak negara. Lalu selanjutnya apa? Dan siapa yang akan menjelajah menuju inovasi berikutnya?
 Ario adalah co-founder Ohdio, layanan streaming musik asal Indonesia. Ario bekerja di industri musik Indonesia dari tahun 2003 sampai 2010 dan sempat bekerja di industri film dan TV di Vietnam. Anda bisa mengikuti akunnya di Twitter @barijoe atau membaca blog-nya di http://barijoe.wordpress.com.
Ario adalah co-founder Ohdio, layanan streaming musik asal Indonesia. Ario bekerja di industri musik Indonesia dari tahun 2003 sampai 2010 dan sempat bekerja di industri film dan TV di Vietnam. Anda bisa mengikuti akunnya di Twitter @barijoe atau membaca blog-nya di http://barijoe.wordpress.com.
[ilustrasi foto dari Shutterstock]