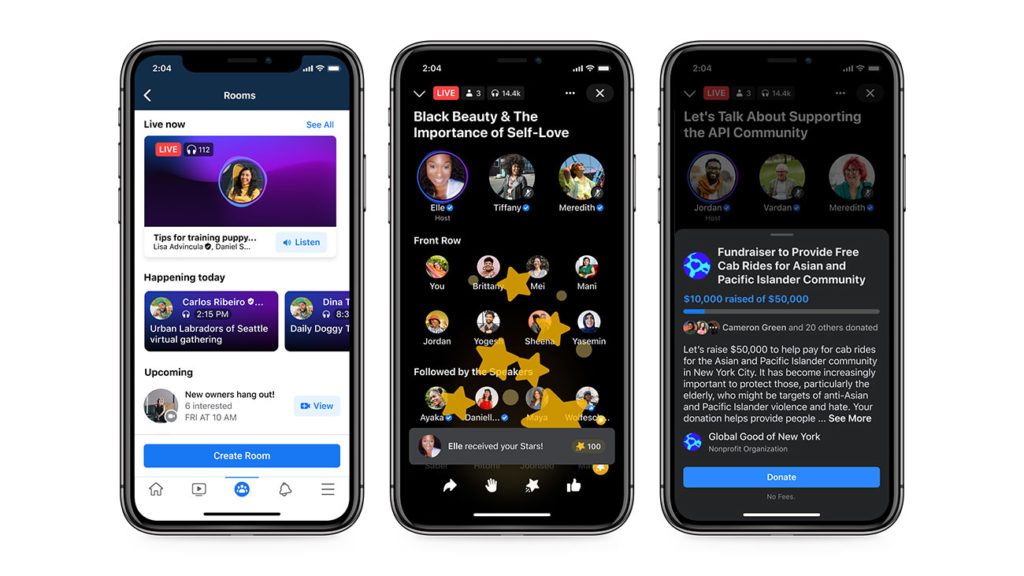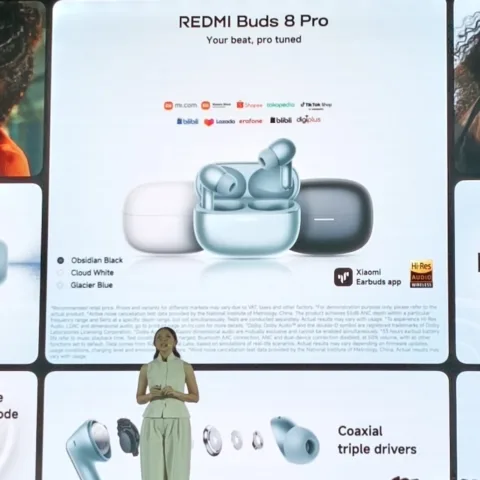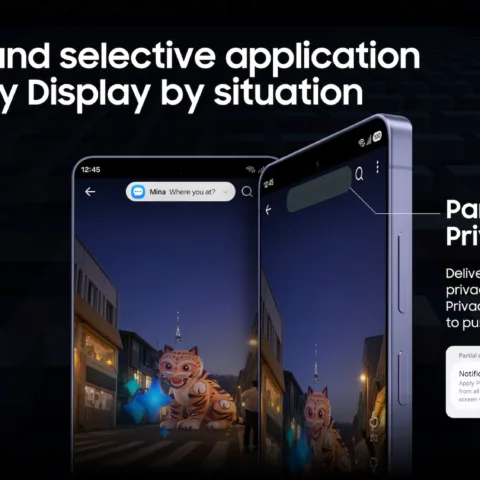Dewasa ini, istilah quad camera pada suatu smartphone mungkin sudah tidak terdengar semengesankan dua atau tiga tahun yang lalu. Pasalnya, cukup dengan modal kurang dari dua juta rupiah saja, sekarang kita sudah bisa mendapatkan smartphone yang dibekali empat kamera belakang.
Sebagai perbandingan, flagship keluaran tahun 2018 seperti Samsung Galaxy S9+ hanya memiliki dua kamera belakang. Namun saya yakin kita semua tahu bahwa jumlah kamera sama sekali tidak bisa dijadikan patokan kualitas kamera dari suatu smartphone. Lebih banyak belum tentu lebih baik, sama halnya seperti megapixel — lebih besar angkanya juga tidak selamanya berarti lebih baik.
Pertanyaannya, kalau begitu, kenapa hingga sekarang pabrikan smartphone masih seakan berlomba banyak-banyakan kamera? Apakah memang didorong permintaan konsumen, khususnya di segmen entry-level di mana jargon quad camera memang paling sering digunakan belakangan ini?
Terkait hal ini, saya pun langsung menanyakan kepada Aryo Meidianto, PR Manager OPPO Indonesia. Saya penasaran apakah konsumen di segmen entry-level lebih condong menginginkan resolusi kamera utama yang tinggi, atau konfigurasi kamera sekunder yang lengkap, yang mencakup kamera ultra-wide, telephoto, makro, dan lain sebagainya.
“Sesungguhnya untuk entry-level, konsumen hanya menginginkan kamera perangkat yang bisa menghasilkan gambar yang jernih dan terang,” jawab Aryo ketika saya hubungi lewat WhatsApp. “Mindset konsumen Indonesia memang walaupun masih salah dan sulit diubah akhirnya membuat megapixel menempati urutan kedua dari alasan konsumen di entry-level. Mereka berpendapat megapixel besar, hasil kamera akan bagus,” imbuhnya.
Jawaban ini sangat menarik karena sangat relatable bagi saya pribadi. Di sini saya ingin memakai kedua orang tua saya sebagai contoh. Mereka bukanlah orang-orang yang fasih teknologi, dan smartphone pilihan mereka adalah yang masuk di kategori entry-level. Penggunaan mereka tidak lebih dari sebatas chatting, media sosial, dan sesekali memotret maupun merekam video.
Setiap kali mereka mengambil gambar menggunakan smartphone dan mendapati hasil yang bagus, komentarnya selalu “Wah, terang ya.” Bukan “tajam”, bukan “detail”, juga bukan “bokeh-nya bagus”. Kriteria utama hasil foto yang bagus bagi mereka cuma satu: terang.
Saya tahu kedua orang tua saya tidak bisa mewakili semua konsumen entry-level, tapi setidaknya dalam konteks ini apa yang dikatakan Aryo sangat akurat. Buat konsumen entry-level, mereka bahkan tidak terlalu mementingkan megapixel alias resolusi. Lalu kenapa pabrikan smartphone masih ‘menjual’ jargon quad camera kepada mereka?
Menurut Aryo, bagaimanapun juga konfigurasi kamera yang lengkap tetap bakal menjadi nilai tambah bagi konsumen. Di titik ini, sebagian dari kita mungkin berpikir, “Kenapa tidak dikurangi saja jumlah kameranya kalau memang tidak dibutuhkan? Kan seharusnya bisa menjadikan harga ponsel lebih murah lagi karena ongkos produksinya berkurang.”
Betul, tapi saya akan ajak Anda untuk melihat perdebatan ini dari sudut pandang yang berbeda.
Smartphone adalah motor penggerak utama demokratisasi fotografi

Yang saya maksud dengan kata demokratisasi di sini adalah bagaimana suatu hal yang dulunya jarang dilakukan, kini menjadi lumrah di kalangan masyarakat luas. Jauh sebelum smartphone eksis, fotografi merupakan hobi atau pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh sebagian orang saja. Sekarang, siapapun bisa mulai mendalami hobi fotografi hanya dengan bermodalkan suatu smartphone.
Fotografi, seperti halnya banyak hobi lain, adalah hobi yang tergolong mahal. Ketika Anda baru memulai, modal awal yang dibutuhkan memang tidak terlalu banyak. Namun ketika sudah mulai ‘terjerumus’, mulailah Anda berbelanja lensa makro, lensa fisheye, lensa tele, dan seterusnya sampai tagihan kartu kredit membengkak.
Yang ingin saya tanyakan adalah, sebagai seorang penggiat hobi fotografi atau bahkan fotografer profesional, apakah Anda butuh lensa-lensa tambahan ini? Butuh. Ok. Apakah Anda menggunakannya setiap hari? Bisa iya, bisa tidak, tergantung kebutuhan. Intinya, semua lensa itu berguna buat Anda walaupun mungkin jarang dipakai.
Prinsip yang sama pun sebenarnya juga bisa kita terapkan di smartphone. Konsumen entry-level mungkin tidak butuh kamera makro atau kamera monokrom, sehingga pada akhirnya mereka jarang sekali menggunakannya. Untuk lebih memastikan kalau kamera makro dan kamera monokrom benar jarang digunakan, saya pun mencoba mengadakan polling kecil-kecilan di media sosial.
Pertanyaan yang pertama adalah, “Seberapa sering menggunakan kamera makro di smartphone?” Dari 117 jawaban, 70 orang menjawab “jarang (kurang dari 5x seminggu)”, dan 47 sisanya menjawab “sering (lebih dari 10x per minggu)”. Seperti yang bisa dilihat, separuh lebih responden rupanya jarang mengutak-atik kamera makro di ponselnya.
Pertanyaan yang kedua adalah, “Untuk menghasilkan foto hitam-putih, biasanya pakai apa?” Pilihan jawabannya sendiri ada dua: A) “Memilih filter B/W di aplikasi kamera bawaan (hasil foto langsung hitam-putih”, atau B) “Memotret seperti biasa (hasil foto berwarna), baru memilih filter B/W waktu mengedit”. 50 orang menjawab B, dan 24 orang menjawab A, selisihnya dua kali lipat.
Dari polling kecil-kecilan yang jauh dari kata ilmiah tadi, setidaknya saya bisa mendapat gambaran bahwa memang benar konsumen jarang menggunakan kamera makro maupun kamera monokrom di smartphone, dan itu bukan sebatas pendapat pribadi saja. Namun jarang dipakai bukan berarti useless, dan mungkin ini yang dimaksud nilai tambah oleh Aryo tadi.
Keberadaan kamera-kamera tambahan di smartphone pada dasarnya memungkinkan konsumen dari semua kalangan untuk bereksperimen dengan cabang-cabang spesifik fotografi. Kehadiran kamera makro misalnya, walaupun mungkin hanya beresolusi 2 megapixel, tetap memberikan peluang bagi konsumen untuk mencicipi hobi fotografi makro.
Demokratisasi, itulah kata kuncinya kalau menurut saya. Kalau menggunakan kamera biasa, Anda butuh modal ekstra yang cukup lumayan untuk mendalami teknik fotografi makro atau landscape dengan menggunakan lensa makro maupun lensa wide-angle. Di smartphone, semua itu sudah menjadi satu paket yang bisa didapatkan dengan modal sekitar dua jutaan rupiah.
Mengenai hasilnya bagus atau tidak, itu bukan masalah, yang penting aksesnya tersedia terlebih dulu. Sama halnya seperti di laptop, kualitas webcam bukanlah prioritas utama, tapi kita mungkin bakal frustasi seandainya tidak ada webcam sama sekali pada laptop tersebut, apalagi di kondisi pandemi seperti sekarang.
Tentu saja, kita juga tidak bisa menepis fakta bahwa quad camera terdengar lebih menjual daripada dual camera atau bahkan triple camera.
Memprediksi tren kamera smartphone ke depannya

Sebenarnya berapa jumlah kamera belakang yang ideal untuk smartphone? Ketika saya buat pertanyaan itu menjadi polling di media sosial, 47 orang menjawab “2”, 22 orang menjawab “3”, dan 13 orang menjawab “4”. Dua kamera belakang saja rupanya sudah cukup untuk sebagian besar orang.
Saya harus berasumsi jawaban ini bisa mewakili semua kalangan, termasuk halnya kalangan atas yang mengincar smartphone flagship. Pasalnya, di tahun 2021 ini pun masih ada ponsel flagship yang hanya memiliki dua kamera belakang saja, yakni iPhone 12. Pada kenyataannya, istilah quad camera hingga kini masih belum termasuk dalam kamus Apple, sebab LiDAR di iPhone 12 Pro tidak bisa digunakan secara terpisah sehingga tidak dapat digolongkan sebagai kamera.
Lalu apakah ke depannya Apple bakal menyusul? Atau malah sebaliknya, tren quad camera-lah yang bakal meredup dalam satu atau dua tahun ke depan? Kalau kita belajar dari sejarah, pengaruh iPhone memang sangat besar terhadap munculnya suatu tren baru di industri smartphone (Touch ID, layar berponi, hilangnya headphone jack, dan lain sebagainya). Mereka tidak harus jadi yang pertama, tapi sering kali kompetitor baru akan menempuh jalur yang sama setelah Apple memulainya.
Namun tidak jarang juga kondisinya berbalik menjadi Apple yang mengikuti tren. Kalau sekadar bicara jumlah, sepertinya triple camera atau quad camera masih akan terus bertahan. Kecil kemungkinan jumlahnya akan bertambah lagi. Kalau iya, Nokia 9 PureView semestinya tidak akan jadi ponsel pertama sekaligus terakhir yang menggunakan teknologi multi-kamera besutan Light.
Dari sisi focal length, konfigurasi triple camera seperti di iPhone 12 Pro (wide, ultra-wide, dan telephoto) saja sebenarnya sudah bisa dikatakan cukup buat sebagian besar orang. Namun seperti yang saya bilang tadi, tidak ada salahnya juga menyematkan kamera makro demi semakin mendemokratisasikan fotografi, apalagi kalau kamera makronya seunik yang terdapat pada OPPO Find X3 Pro, yang mampu mengambil gambar dengan tingkat perbesaran hingga 60x.
Tidak menutup kemungkinan juga jumlah kameranya bisa berkurang. Contohnya seperti Xiaomi Mi Mix Fold, yang mencoba menyatukan kamera makro dan telephoto ke dalam satu rumah lensa yang sama. Di luar konteks jumlah, tren lain yang tak kalah menarik adalah bagaimana sejumlah pabrikan mulai memprioritaskan kualitas kamera sekunder pada ponsel bikinannya.
Salah satu contohnya adalah OnePlus. OnePlus 9 Pro yang dirilis belum lama ini mengemas kamera ultra-wide dengan sensor berukuran lebih besar dari biasanya, bahkan hampir menyamai ukuran sensor kamera utamanya. Contoh lainnya lagi-lagi bisa kita lihat dari OPPO, yang menanamkan sensor yang sama persis pada kamera utama sekaligus ultra-wide milik Find X3 Pro.

Bicara soal OnePlus, tentu kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa mereka baru-baru ini juga ikut meramaikan tren kerja sama antara pabrikan smartphone dan pabrikan kamera. Tidak tanggung-tanggung, guna memaksimalkan kolaborasinya bersama Hasselblad selama tiga tahun ke depan, OnePlus rela menyiapkan dana sebesar $150 juta.
Di tempat lain, ada Vivo yang baru-baru ini meluncurkan X60 Pro dengan fitur unggulan berupa kamera hasil kolaborasinya bersama Zeiss. Tentu saja kita juga tidak boleh lupa dengan Huawei dan Leica, yang telah menjalin kemitraan selama lima tahun, dimulai dari diluncurkannya Huawei P9 di tahun 2016.
Apakah ke depannya kita bakal melihat semakin banyak lagi produsen smartphone yang mengambil jalur serupa? Mungkinkah ke depannya kita melihat produsen smartphone lain menggandeng produsen kamera yang lebih mainstream seperti Canon atau Fujifilm? Atau semua ini hanya sebatas tren sesaat?
Jujur saya tidak punya jawabannya, tapi saya setidaknya punya sedikit gambaran setelah menanyakan hal ini kepada Aryo. Menurutnya, langkah semacam ini terbilang populer karena perspektif konsumen cenderung baik terhadap berbagai produsen kamera atau lensa, sehingga pada akhirnya bisa mengangkat nama brand smartphone itu sendiri.
Saya tidak terkejut seandainya ada sebagian dari kita yang skeptis dan menganggap kolaborasi-kolaborasi seperti ini tidak lebih dari sekadar produsen smartphone meminjam nama produsen kamera, sebab memang tidak ada yang bisa mencegah konsumen menyalahartikannya.
Itulah mengapa pabrikan sebenarnya juga dapat mengambil opsi yang lebih subtle, yang semestinya malah lebih sulit disalahartikan. Opsi yang saya maksud adalah bekerja sama dengan produsen sensor — entah itu Sony ataupun Samsung (dua nama terbesar saat ini) — dalam menciptakan sebuah sensor kamera smartphone yang sifatnya eksklusif.
Satu hal yang pasti, kamera masih akan terus menjadi topik pembicaraan yang paling hangat ketika membahas suatu smartphone. Hal ini sungguh menarik karena kita hampir tidak pernah membahas bagaimana kamera-kamera terbaru bikinan Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, maupun pabrikan-pabrikan lainnya jadi semakin canggih layaknya smartphone.
Kita tidak butuh kamera yang mampu menyaingi kecanggihan smartphone, akan tetapi kita butuh smartphone yang semakin hari hasil jepretannya semakin mengejar kualitas yang dihasilkan kamera mirrorless maupun DSLR.
Gambar header: Redmi 9 via Xiaomi Indonesia.