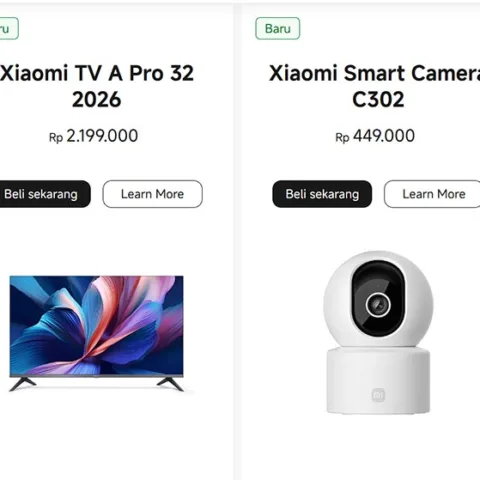Wacana tentang diikutsertakannya esports dalam ajang olahraga internasional selalu menarik untuk diikuti. Tampilnya di Asian Games 2018 sudah merupakan “kemenangan besar”, walau sifatnya hanya percobaan. Namun untuk menuju ke tahap selanjutnya, yaitu mengikutsertakan esports sebagai cabang olahraga resmi, butuh perjuangan yang lebih keras.
Komite IOC (International Olympic Committee) telah cukup lama menyatakan rasa pesimisnya terhadap pengikutsertaan esports di Olimpiade. Salah satu alasannya yaitu karena berbagai video game atau “egames” itu mengandung unsur kekerasan serta diskriminasi, bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung di Olimpiade. Kemudian baru-baru ini, dalam konferensi di kota Lausanne, Perancis, IOC menyatakan kesepakatan mereka untuk tidak menampilkan esports sebagai cabang resmi atau peraihan medali dalam Olimpiade Paris 2024.

IOC mengakui bahwa esports saat ini merupakan industri yang besar, dan mereka juga tidak menyangkal bahwa video game kompetitif layak untuk disebut “olahraga”. Pada praktiknya, esports memang membutuhkan kebugaran badan serta ketangkasan yang dapat disejajarkan dengan olahraga tradisional. Akan tetapi masih banyak ketidakpastian yang membuat IOC berpendapat bahwa masih terlalu dini untuk mengikutsertakan esports di Olimpiade.
Selain itu IOC juga mengakui bahwa cepatnya pertumbuhan teknologi, terutama augmented reality dan virtual reality, juga akan membuat wujud industri esports terus berubah. Mereka tidak menutup kemungkinan esports bisa masuk ke Olimpiade suatu saat nanti. Tapi setidaknya, untuk Olimpiade Paris 2024, hal itu dinilai masih belum waktunya.

Di samping unsur kekerasan yang tadi sudah disebut di atas, IOC juga merasa bahwa perkembangan industri esports sangat didorong oleh motif komersial. Ini berbeda dengan gerakan olahraga konvensional, di mana perkembangannya didorong oleh motivasi untuk mencapai nilai tertentu.
Kita yang mengikuti dunia olahraga profesional tentu merasa pernyataan ini agak aneh, karena bagaimana pun juga cabang-cabang olahraga terpopuler di dunia tak bisa lepas dari perputaran uang yang besar juga. Di sepak bola misalnya, perpindahan pemain dari satu klub ke klub lain bisa melibatkan transaksi senilai ratusan juta dolar. Ini baru transfer pemain, belum soal sponsorship, hak siar, merchandise, dan sebagainya. Justru karena adanya komersialisasi itulah suatu cabang olahraga bisa berkembang, menyebar, serta menghasilkan talenta-talenta hebat yang memang menjadikan olahraga tersebut sebagai mata pencaharian.

Berbicara tentang kekerasan pun, Olimpiade sendiri saat ini sudah berisi beberapa olahraga yang mengandung kekerasan. Contohnya tinju, anggar, atau gulat. Bila yang dipermasalahkan adalah tampilan visual kekerasannya (seperti darah, gore, dsb), maka solusinya adalah cukup dengan mengganti game dengan judul lain yang lebih layak ditonton. Misalnya mengganti PUBG dengan Fortnite, atau mengganti CS:GO dengan Splatoon.
Keputusan IOC untuk menolak esports (setidaknya untuk saat ini) tentu cukup mengecewakan. Apalagi SEA Games 2019 saja sudah resmi mengumumkan bahwa Mobile Legends akan jadi bagian kompetisi. Tapi IOC berjanji akan terus memantau perkembangan industri esports, serta mengadakan diskusi dengan para stakeholder industri esports untuk mencari jalan tengah. Ini tantangan yang cukup besar, baik bagi pihak yang pro maupun kontra. Tahun 2024 masih lama. IOC pun masih punya banyak waktu untuk mengubah keputusan mereka.
Sumber: IOC, Fortune, CG Esports